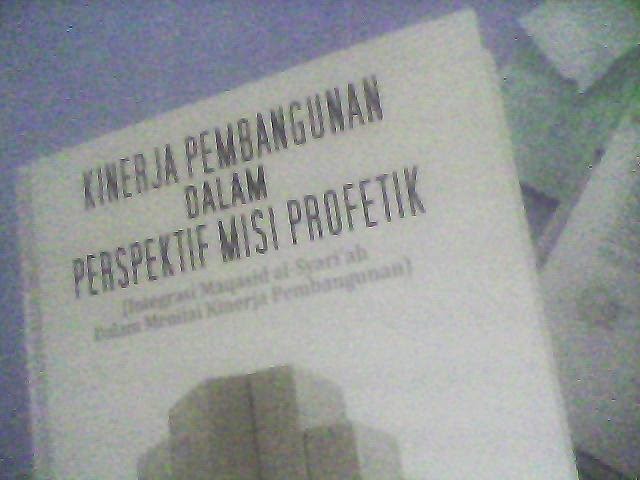(Makalah disampaikan pada acara diskusi mingguan Kelompok Studi Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan pada 10 Agustus 20101 / 01 Ramadhan 1431 H)
Suku Sasak sangat identik dengan suku muslim. Masyarakat Sasak tercatat sebagai penduduk mayoritas Pulau Lombok. Tak kurang dari 95% penduduk “pulau seribu masjid” itu adalah masyarakat Sasak. Dan, hampir semuanya memeluk agama Islam.
Karena itu, tak heran pula jika Islam diterima masyarakat Sasak secara total. Di sana, Islam dipraktikkan dalam bentuk yang ortodoks dan kaku, tetapi juga menampilkan corak lokalitas yang bervariasi. Ajaran Islam melebur dalam budaya setempat dan dimaknai ulang sesuai dengan kearifan budaya lokal (local wisdom). Lihat saja, tradisi Islam Wetu Telu dan Islam Waktu Lima.
Itulah sepenggal dialektika Islam dengan budaya masyarakat Sasak. Kini hal yang pertama kali perlu disingkap adalah bagaimana perjalanan Islam menyapa masyarakat Sasak serta dalam hal apa saja terjadi akulturasi Islam dengan budaya mereka.
Asal Usul Suku Sasak
Masyarakat Sasak adalah penduduk asli Pulau Lombok. Pulau ini dari segi geografis merupakan salah satu pulau kecil yang merupakan penghubung Benua Asia dan Benua Australia. Lombok sendiri mempunyai beberapa klaim internasional salah satunya Lombok merupakan pulau pertama yang disinggahi Alfred Wallace dan dijadikan sebagai batas pembeda fauna dan flora antarbagian timur dan barat Indonesia. Sementara itu, dalam Babat Selaparang, Pulau Lombok dikenal dengan istilah Gumi Sasak atau Gumi Selaparang.
Nama Gumi Selaparang ini pun terdapat dalam surat perjanjian antara Hendrik Djakob Husmus Koppeman, seorang Komisaris Gubenur Hindia Belanda, dengan Gusti Ketut Karang Asam. Dalam surat ini disebutkan bahwa Ketut Karang Asam adalah raja di Pulau Selaparang. Nama Gumi Selaparang juga terdapat dalam surat anak Agung Ngurah Karang Asem kepada G.G. Merkus di Batavia tertanggal 23 September 1843 M yang menyebutkan kerajaan Mataram di Pulau Selaparang.
Asal usul masyarakat Sasak sebenarnya masih diselubungi kegelapan. Sebab, sampai saat ini belum ada penelitian yang valid tentang hal ini. Maka, wajar bila para sejarawan bersilang pendapat terkait asal usul masyarakat Sasak. Namun demikian, ada catatan etnografis yang patut diangkat ke permukaan.
Dikatakan bahwa masyarakat Sasak adalah keturunan dari suku Jawa yang menyeberang ke Pulau Bali dan selanjutnya ke Pulau Lombok. Hal ini dimulai sejak Kerajaan Daha, Kalingga, Singosari sampai Kerajaan Mataram Hindu. Terlebih pada tahun 1518- 1521 peyeberangan migran Jawa ke Lombok semakin meningkat. Karena faktor ini pula, cukup bisa diterima akal sehat jika sebagian kebudayaan Sasak merupakan hasil akulturasi dengan kebudayaan Jawa. Van Vollenhoven pun menggabungkan Lombok dengan Bali dalam satu wilayah lingkungan adat. Penggabungan ini berdasarkan atas banyaknya kesamaan adat istiadat di kedua daerah tersebut.
Konstruksi Sosial-Budaya Suku Sasak
Kondisi sosial-budaya masyarakat Sasak pertama-tama dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari. Dalam tata pergaulan, bahasa yang digunakan sangat penting untuk diketahui, sebab dengan pengungkapan bahasa, selain bahasa alat komunikasi paling efektif di masyarakat, namun juga ada hubungannya dengan tata pergaulan di lingkungan warganya. Hal ini jelas terlihat dari tingkat penggunaan bahasa dalam struktur masyarakat Sasak. Perlu diingat, secara tradisional masyarakat Sasak dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu perwangse, kawula (jajar karang/bulu ketujur), dan panjak. Dari klasifikasi inilah muncul perbedaan dalam pemakaian bahasa.
Mengenai bahasa yang dipergunakan masyarakat Sasak dalam suasana tidak resmi adalah bahasa Sasak. Walau dalam pengungkapannya terdapat berbagai dialek, seperti dialek meno-mene dengan lafal ape bese, dan sebagainya. Demikian pula Bahasa Indonesia pada umumnya digunakan pada pertemuan-pertemuan formal, khususnya di sekolah-sekolah. Akan tetapi, dalam pertemuan nonformal seperti acara sarasehan atau pertemuan yang diselenggarakan pada tingkat desa, dasan, rukun tetangga, dan rukun warga, sering digunakan bahasa Sasak.
Islamisasi Suku Sasak
Sebagai unsur mayoritas penduduk Pulau Lombok, masyarakat Sasak jauh sebelum mengenal Islam adalah potret masyarakat yang memuja keyakinan animisme-dinamisme. Keyakinan ini diterjemahkan dalam sikap pengultusan terhadap benda maupun tempat yang dipandang memiliki daya linuwih alias kekuatan gaib. Hal serupa juga berlaku terhadap roh para leluhur mereka.
Selain keyakinan animisme-dinamisme tersebut, sebagian masyarakat Sasak juga diresapi agama Hindu dan Boda (bukan Budha) yang terjadi akibat adanya relasi politik dengan Kerajaan Majapahit. Maka, ketika Islam mulai memasuki Pulau Lombok beberapa waktu setelah ambruknya Kerajaan Majapahit, proses Hinduisasi sebenarnya masih berlangsung di bawah pengaruh Kerajaan Gelgel, Klungkung, Karang Asam, kemudian dilanjutkan oleh penguasa-penguasa Bali di Lombok.
Islamisasi Sasak terjadi sekisar abad ke-15 hingga ke-17 yang dilakukan oleh Pangeran Prapen dari Giri (Gresik). De Graff menyatakan bahwa paruh kedua abad ke-16 merupakan fase kemakmuran Giri (Gresik) sebagai pusat peradaban Islam sekaligus pusat ekspansi Jawa di bidang ekonomi dan politik di Indonesia Timur. Ekspansi ke Lombok berkaitan erat dengan usaha memperluas kekuasaan rohani serta hubungan dagang lewat laut ke arah timur.
Penaklukan Islam terhadap Lombok tampaknya tidak terlalu sukses dari segi rohani, kendatipun secara kultur pengaruh Jawa cukup berhasil. Hal ini tampak dari situasi keberagamaan masyarakat Sasak sampai abad ke-20 masih banyak ditemukan agama Boda dan Islam Wetu Telu. Walau penganut Wetu Telu ini sangat jarang, untuk tidak mengatakan tidak ada lagi, sebab mereka hanya dijumpai di ujung utara Pulau Lombok di Lereng Gunung Rinjani, yaitu daerah Bayan. Ajaran Islam Wetu Telu masih menunjukan sinkretisme antara ajaran Islam dengan Hinduisme dan animisme-dinamisme.
Kendati begitu, dalam perkembangannya, masyarakat Sasak bisa dibilang pemeluk Islam yang taat dan fanatik. Setiap pemukiman kampung dan desa mempunyai tempat beribadah, berbentuk musholla (santren) dan masjid. Karena itulah, Pulau Lombok dijuluki pulau seribu masjid. Musholla dan masjid itu bukan semata-semata untuk tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyebaran dan pembelajaran Islam.
Seturut perkembangan zaman, gairah keberagamaan masyarakat Sasak terus membuncah. Organisasi sosial-keagamaan semisal Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun bermunculan. Aliran Wahabiyah juga mendapat tempat di hati masyarakat Sasak. Namun organisasi sosial-keagamaan yang terbesar di sana adalah Nahdhatul Wathan yang didirikan oleh al-Magfurllah al-Mukarram al-‘Allamah Maulana Syekh Tuan Guru H. Zainuddin bin Abdul Majid.
Akulturasi Budaya Suku Sasak
Hal yang tampak mencolok dalam praktik keagamaan Islam masyarakat Sasak adalah tipologi Islam Wetu Telu dan Islam Waktu Lima. Tipologi yang pertama, Islam Wetu Telu, mengacu pada masyarakat Sasak yang meski mengaku sebagai muslim namun tetap memercayai prinsip keyakinan animistik leluhur (ancestral animistic deitis) dan kegaiban benda-benda antropomorfis (anthropomorphised inanimate objects). Dalam hal ini, mereka termasuk dalam kategori panteis. Adapun tipologi kedua, Islam Waktu Lima, adalah masyarakat muslim Sasak yang mempraktikkan ajaran Islam dengan tegas sebagaimana tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Mengikuti dikotomi Geertz dalam Religion of Java, Islam Wetu Telu lebih mirip dengan Islam abangan yang sinkretik, walaupun Islam Waktu Lima tidaklah seperti bentuk Islam santri.
Yang unik dari praktik keagamaan Islam Wetu Telu adalah adanya perbedaan tata cara ibadah antara daerah satu dengan lainnya. Di Sembalun daerah dingin Lereng Gunung Rinjani (Lombok Timur), mereka hanya menjalankan Salat Ashar. Jelas, inilah wujud dialektika Islam dengan budaya Sasak.
Islam Sasak merupakan cermin dari pergulatan agama lokal atau tradisional berhadapan dengan agama dunia yang universal—dalam hal ini Islam. Seperti yang terjadi di Bayan (Lombok Barat), Islam Wetu Telu, yang banyak dipeluk oleh masyarakat Sasak asli, dianggap sebagai “tata cara keagamaan Islam yang salah (bahkan cenderung syirik)” oleh kalangan Islam Waktu Lima—sebuah varian Islam universal yang dibawa oleh orang-orang dari daerah lain di Lombok. Tak pelak, Islam Waktu Lima sejak awal kehadirannya disengaja untuk melakukan dakwah Islamiyah terhadap kaum Islam Wetu Telu.
Secara sederhana barangkali dapat dikatakan bahwa Islam Wetu Telu merupakan praktik keagamaan yang dijalankan dengan tradisi lokal dan adat Sasak. Varian Islam ini lebih mirip dengan Islam abangan atau Islam Jawa di Jawa, seperti yang ditulis Mark Woodward dalam buku Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan. Dalam Islam Wetu Telu, yang paling menonjol adalah pengetahuan tentang lokalitas, tentang adat, bukan pengetahuan sebagai rumusan doktrin yang datang dari Arab. Akan tetapi, juga bukan tidak menggunakan Islam sama sekali, sebab masih menerapkan saran peribadatan Islam.
Penyebutan istilah wetu telu mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Komunitas Waktu Lima menyatakan bahwa wetu telu sebagai waktu tiga (tiga: telu) dan mengaitkan makna ini dengan reduksi seluruh ibadah Islam menjadi tiga. Orang Bayan sebagai penganut terbesar Islam Wetu Telu ini, menolak penafsiran semacam itu. Pemangku adatnya mengatakan bahwa, term wetu sering dikacaukan dengan waktu. Wetu berasal dari kata metu yang berarti muncul atau datang dari. Sedangkan telu artinya tiga.
Secara simbolis makna ini mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup muncul melalui tiga macam sistem reproduksi, yaitu melahirkan (disebut menganak), bertelur (disebut menteluk), dan berkembang biak dari benih (disebut juga mentiuk). Term wetu telu juga tidak hanya menunjuk kepada tiga macam sistem reproduksi, tetapi juga menunjuk pada kemahakuasaan Tuhan yang memungkinkan makhluk hidup untuk hidup dan mengembangkan diri melalui mekanisme reproduksi tersebut.
Sumber lain menyebutkan bahwa ungkapan wetu telu berasal dari bahasa Jawa yaitu metu saking telu. Maksudnya, keluar atau bersumber dari tiga hal, yaitu Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma. Artinya, ajaran-ajaran komunitas penganut Islam Wetu Telu bersumber dari ketiga sumber tersebut.
Komunitas Islam Wetu Telu ini dalam perjalanannya mulai terdesak sedikit demi sedikit oleh arus modernitas, ortodoksisme Islam, dan serangan dakwah terus menerus yang dilakukan oleh Islam Waktu Lima, serta implikasi massif dari kebijakan politik terutama proyek transmigrasi lokal ke kawasan adat mereka.
Tradisi Suku Sasak
Sebab masyarakat Sasak adalah mayoritas penduduk Pulau Lombok, demikian halnya di kawasan Lombok Timur. Di sana, tradisi Sasak berbalut ajaran keagamaan terus lestari. Namun demikian, masyarakat Sasak memiliki nilai-nilai kebajikan yang dipelihara terutama ketika menyikapi perubahan.
Masyarakat Sasak berpandangan bahwa segala bentuk perubahan, baik yang berlaku secara komunal maupun individual, perlu dikawal dengan serangkaian ritual. Ini bertujuan agar perubahan tersebut membawa keberkahan, bukan malah kerusakan.
Tradisi yang masih terpelihara di antaranya tampak dalam menyikapi peristiwa kematian. Ini pun termasuk dalam kategori perubahan, sehingga diperlukan aksi untuk memaknainya. Dalam hal ini, ritual yang lazim dilakukan misalnya doa selamat mitu (selamatan tujuh hari setelah kematian), nyiwa’ (selamatan sembilan hari setelah kematian), matang pulu (selamatan empat puluh hari setelah kematian), dan sebagainya.
Selain itu, terdapat pula ritual yang dilakukan secara bertahap seturut peristiwa penting dalam kehidupan. Pertama, retes rembet (selamatan perut) atau melak tangkel (memecahkan tempurung). Ritual ini berlaku bagi ibu hamil setelah usia kehamilan menginjak tujuh bulan. Tujuannya, tentu mendoakan agar ibu dan janin yang dikandungnya selamat hingga dalam proses persalinan. Ritual ini dalam adat Jawa sepadan dengan tradisi tingkepan, atau peled kandung dalam tradisi Madura.
Kedua, malang mali’ (buang abu atau perak api). Ritual ini berwujud upacara untuk menjaga kesehatan bayi pada usia tujuh sampai sembilan hari setelah dilahirkan, kemudian diberi nama. Ketiga, bekuris (potong rambut). Ritual ini juga berwujud upacara yang diadakan setelah bayi berumur tujuh hari atau lebih. Keempat, turun tana’ (turun tanah). Yaitu, upacara saat bayi berumur tujuh bulan dan mau menginjak tanah pertama kali.
Kelima, nyunatang (khitanan). Maksudnya, upacara khitanan untuk anak laki-laki dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan kesiapan orang tuannya. Keenam, khataman Qur’an, yaitu upacara bagi anak yang sudah mau dan tamat mengaji al-Qur’an. Biasanya diiringi dengan memberikan sesuatu kepada tuan guru atau guru mengaji sebagai ekspresi rasa syukur.
Ketujuh, mapahang gigi (potong gigi). Ritual ini berlaku bagi remaja, khusus wanita menjelang perkawinan. Kedelapan, bekawin atau merarik, yaitu melakukan akad pernikahan antara remaja pria dan gadis, atau perjaka dengan janda atau sebaliknya, atau duda dengan janda, atau bahkan suami yang melakukan poligami. Ritual-ritual tersebut hingga saat ini masih dilestarikan masyarakat Sasak sebagai bagian dari siklus hidup yang berlaku turun temurun.
Dalam hal perkawinan, tradisi perondongan (perjodohan), merarik lamar (kawin lamar), dan selarian (kawin lari) masih kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat Sasak. Dalam tradisi perondongan (perjodohan), lazimnya dilakukan sejak kecil dan baru diberitahukan saat waktu pernikahan sudah dekat. Tradisi perondongan memunculkan kesan kawin dengan terpaksa. Karena itu, tradisi ini juga disebut kawin todong.
Sementara tradisi merarik lamar (kawin lamar) terjadi akibat kultur masyarakat Sasak yang tidak membolehkan pacaran, apalagi disertai dengan adat midang (apel—huruf e dibaca seperti pada kata sate). Untuk itu, “pacaran” dilakukan melalui perantara seorang subandar. Setelah dirasa akrab, baru dilangsungkan prosesi lamaran.
Adapun selarian (kawin lari) merupakan sistem perkawinan yang paling umum terjadi di “pulau seribu masjid” ini. Sistem perkawinan ini masih berlaku sampai sekarang. Secara umum, pengaruh adat dan orang tua memegang peran penting dalam masalah perkawinan di dalam kehidupan masyarakat Sasak, terutama dalam kehidupan masyarakat di kalangan bangsawan dan tuan guru, sebab perkawinan masih terikat dengan agama, penentuan hari baik, dan masalah keturunan.
Antropologi Keberagamaan (Islam) suku Sasak
Suku Sasak dan Kearifan Lokal
Penduduk pulau Lombok terdiri dari tiga etnis besar yakni: Sasak, Samawa dan Mbojo. Sasak sebagai penduduk asli merupakan etnik mayoritas di pulau Lombok. Kelompok etnis lain seperti Bali, Jawa, Bugis, Arab, dan Cina adalah para pendatang. Diantara mereka, orang Bali merupakan kelompok etnik terbesar kedua. Orang Bali terutama tinggal di Lombok Barat dan kota Mataram. Orang-orang Sumbawa terutama bermukim di Lombok Timur, sementara orang-orang Arab di Ampenan. Lingkungan pemukiman masyarakat Arab disebut sebagai kampung Arab Ampenan. Orang Cina, mayoritas adalah pedagang yang tinggal di pusat-pusat pasar, seperti Ampenan dan Cakra. Orang Bugis, khususnya yang hidup sebagai nelayan tinggal di kawasan Tanjung Ringgit, Tanjung Luar dan di pulau-pulau kecil di sekitar Lombok Barat dan Timur. Kampung Jawa atau pemukiman orang Jawa terletak di Praya Lombok Tengah dan juga di Mataram, selain juga pendatangpendatang kemudian hari yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Disamping terdiri dari berbagai etnik, Lombok terbagi secara bahasa, budaya dan agama.
Berbagai etnis -yang telah disebutkan di atas- biasanya identik juga dengan kepemelukan pada agama tertentu, seperti etnis Sasak, Sumbawa, dan Bima adalah Muslim, etnis Bali adalah Hindu. Kemudian etnis Jawa dan Sunda sebagian besar adalah Muslim, dan hanya sebagian kecil yang memeluk Kristen/Katolik. Sedangkan Bugis adalah Islam, Tionghoa adalah Budha, dan sebagian Kristen, dan Arab adalah Islam.
Pada masyarakat suku sasak di pulau Lombok, kearifan lokal merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan agama dan adat budaya. Karenanya denyut nadi kehidupan masyarakat sasak memerlukan cara-cara yang arif lagi bijaksana. Manusia dalam hidupnya tidak cukup hanya memperhatikan materi, energy dan informasi. Dalam kehidupan modern, materi, energi dan informasi tersebut selalu diukur dengan uang, sehingga dengannya peran uang selalu menjadi dominan. Meskipun ilmu lingkungan penting, akhirnya ia bukan menjadi satu-satunya masukan dalam mengambil setiap keputusan mengenai permasalahan lingkungan hidup. Masukan lain yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemecahan permasalahan lingkungan hidup adalah ekonomi, teknologi, hukum, politik dan sosial budaya masyarakat.
Dipulau Lombok banyak dijumpai kearifan lokal dalam mengatur system sosial kemasyarakatan, seperti pengaturan pemerintahan desa dengan berbagai lembaga adat, persubakan, keamanan, ekonomi, dan begitu pula kearifan lokal yang berkaitan dengan perlakuan terhadap lingkungan alam, seperti embung sebagai penyimpan cadangan air, pengaturan system tanam, penggunaan pupuk alam dan pemberantasan hama. Seperti misalnya sistem tanam padi Gogo Rancah (Gora) sekitar 1978, oleh karena pada saat masyarakat mengalami kondisi kekurangan bahan makanan berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya kelaparan pada setiap musim dengan tingkat kematian yang begitu besar, maka secara tiba-tiba timbul upaya yang brillian dari masyarakat sendiri untuk mengatasi hal tersebut.
Karena itu sikap yang etik yang dikembangkan masyarakat sasak setidaknya juga tercermin dari petuah para orang tua yang dapat disimpulkan dalam ungkapan-ungkapan berikut: “solah mum gaweq, solah eam daet, bayoq mum gaweq bayoq eam daet” (baik yang dikerjakan maka akan mendapat kebaikan dan buruk yang dikerjakan maka akan mendapatkan keburukan), “piliq buku ngawan, semet bulu mauq banteng, empak bau, aik meneng, tunjung tilah”. Masyarakat memahami bahwa seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutkan evolusinya, hingga mencapai tujuan penciptaan. Kehidupan mahluk-mahluk Tuhan saling terkait. Bila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, maka mahluk yang berada dalam lingkungan hidup akan ikut terganggu pula.
Hubungan antara manusia dan alam atau hubungan manusia dan sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dan hamba, namun lebih merupakan hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Tuhan. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugrah Tuhan. Setelah menyadari pandangan agama tentang makna kekhalifahan manusia yang menjadi tujuan penciptaan di muka bumi, maka tidak heran bila puluhan bahkan ratusan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis yang dijadikan landasan dalam berpijak guna tercapainya kelestarian lingkungan yakni: Pertama, Tidak seorang manusiapun yang menanam tanaman atau menyemaikan tumbuh-tumbuhan, kecuali buah atau hasilnya dimakan burung atau manusia. Yang demikian itu adalah amal baginya. Kedua, bagi manusia yang memperbaiki (menyuburkan) tanah bukan milik seseorang, maka ia berhak memanfaatkan tanah tersebut. Ketiga, menghindari dua macam kutukan yakni membuang kotoran di jalan dan ditempat orang berteduh. Keempat, janganlah ada di antara manusia yang membuang air kecil pada air yang tergenang, kemudian mandi pula disana.
Peran manusia dalam kaitanya dengan lingkungan dapat dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, manusia belum memiliki peran sama sekali, sama kedudukannya dengan mahluk ciptaan Tuhan lainnya. Tahap kedua, manusia tampil dengan perannya sebagai mahluk Tuhan yang paling sempurna. Dengan akal dan pikiran yang dianugrahkan Tuhan kepadanya, manusia mengembangkan dirinya. Akan tetapi, pengembangan diri ini akhirnya menjelma menjadi penguasaan atas alam dan pengusaan atas alam ini acapkali menimbulkan kerusakan alam yang akibatnya merupakan penderitaan bagi manusia. Tahap ketiga, timbulnya kesadaran manusia bahwa pengembangan akal dan pikiran yang acapkali menimbulkan kerusakan itu perlu disertai dengan budi dan bahwa manusia dititahkan untuk mengelola alam secara bijaksana bagi kepentingan seluruh kehidupan di bumi ini. Konfrensi Stockholm tahun 1972 dapat dipandang sebagai permulaan manusia memasuki tahap ketiga ini.
Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pola kehidupan yang relative tetap memiliki aturan dasar yang turun temurun dan menjadi norma hidup dari komunitas masyarakat sasak. Aturan norma ini disimbulkan dengan “buku-ngawan” karena kehidupan itu mesti teratur dan memiliki aturan seperti halnya alam semesta. Dari mana memulai membangun “bale-langgak” (rumah dan kelengkapannya), berugaq-sekepat, alang-sambi, leah-lambur, jebak, pengorong, kemudian menjadi pemukiman dengan istilah “gubug-gempeng” dan seterusnya sehingga terbentuklah “dise-dasan”. Secara harmonis kehidupan “dise-dasan” sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam sekitar, khususnya berhubungan dengan istilah “epe-aik” yang menjadi sumber dari segala sumber hidup dan kehidupan komunitas masyarakat sasak.
Berdasarkan aturan adat budaya ini, maka muncul budaya tradisional masyarakat sasak yang tidak lepas dari pola trinitaris dasar yakni: pertama, “epe-aik” sebagai pemilik yang maha kuasa atas segala asal kejadian alam dan manusia. Kedua, “gumi-paer” sebagai tanah tempat berpijak di situ langit dijunjung, karena di “gumi-paer” ini masyarakat sasak dilahirkan. Diberi kehidupan dan selanjutnya diwafatkan. Ketiga, “budi-kaye” yang merupakan kekayaan pribadi dari kesadaran akan “budi-daye” Sang Hyang Sukseme yang menurunkan “akal-budi” pada setiap diri manusia untuk mendapatkan kemuliaan hidup yang akan dibawa sampai meninggal dunia. Ketiga hal inilah yang akan mewarnai setiap pandangan, ucapan dan perbuatan masyarakat sasak menjadi adab budaya yang tidak hanya diukur dengan hasil karya secara material namun yang lebih penting adalah nilai-nilai yang diperoleh selama hidup yang tercermin dari pelaksanaan adat istiadat mereka.
Sosialisasi Kearifan Lokal
Pengetahuan yang dimiliki masyarakat -khususnya generasi tua- biasanya disosialisasikan pada waktu terjadi perbincangan tidak resmi antar generasi. Misalnya, secara tidak disengaja generasi yang berbeda bertemu di suatu tempat, seperti masjid, mushala, di tempat hajatan, di warung atau di mana pun ada kesempatan. Pada momen dan tempat seperti itu, biasanya generasi tua dengan cara serius atau sambil bercanda memberikan wejangan-wejangan kepada generasi muda tentang berbagai hal, terutama tentang pengetahuan dan pengalaman mereka. Sosialisasi dengan cara non-formal semacam ini merupakan sosialisasi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat suku Sasak.
Sosialisasi dengan cara seperti di atas dapat dilakukan oleh hampir semua orang yang lebih tua usianya, sehingga tidak terbatas pada kalangan tokoh formal, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, orang tua yang berpendidikan, bahkan seorang pembantu pun bisa melakukan sosialisasi kepada anak majikannya. Untuk meyakinkan kepada kalangan muda, kalangan tua biasanya menyombongkan diri dengan kata-kata “dakak’et bodo, ndek uah sekolah, laguk ite uah besuh kaken paek’n sie” (Meskipun saya bodoh, tidak pernah sekolah, tetapi orang tua tetap menang pengalaman).
Cara-cara lain yang juga banyak ditempuh adalah melalui pendidikan formal di sekolah atau melalui pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat, yaitu melalui pengajian-pengajian atau dalam pertemuan anak-anak. Cara yang terakhir ini tentunya dilakukan oleh kalangan tertentu, yaitu tokoh-tokoh formal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tuan guru, ustad dan guru ngaji.
Kadang-kadang sosialisasi kearifan lokal dilakukan dengan intensitas tinggi apabila terjadi konflik antargenerasi muda atau ada anak bermasalah. Akan tetapi, apabila terjadi konflik di kalangan generasi tua tidak ada sosialisasi, keculai konflik tersebut terjadi antarindividu, dengan catatan bukan dari kalangan elite desa.
Kearifan Lokal dan Perubahan Sebagai Suatu Keniscayaan
Betapapun lambatnya perubahan terjadi di daerah pedesaan, namun seiring dengan perjalanan waktu dan semakin banyaknya anak-anak desa mengenyam pendidikan dan mereka pun menjadi semakin rasional, akhirnya perubahan -baik yang diinginkan maupun yang dikhawatirkan- menjadi keniscayaan. Selain itu, kearifan berkaitan dengan moralitas, seperti “anak gadis tidak boleh berdiri di depan pintu” dan pantangan-pantangan yang lain yang tidak logis, seperti “dilarang makan sambil berbicara”, “menduduki buah kelapa”, “menduduki bantal” telah lama diabaikan oleh generasi muda. Menyikapi perubahan dan perkembangan zaman yang sedemikian pesat itu dan pantangan- pantangan yang berkaitan dengan masalah moralitas -terutama bagi perempuan- yang sudah diabaikan, sebagaian generasi tua merasa prihatin. Mereka yang prihatin biasanya menanggapinya dengan mengungkap kembali ramalan yang konon merupakan warisan nenek moyang.
Menurut Fuad Hasan, budaya Nusantara yang plural merupakan kenyataan hidup (living reality) yang tidak dapat dihindari. Kebhinekaan ini harus dipersandingkan bukan dipertentangkan. Keberagaman ini merupakan manifestasi gagasan dan nilai sehingga saling menguat dan untuk meningkatkan wawasan dalam saling apresiasi. Kebhinekaannya menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan (virtue and wisdom)
Kebudayaan dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok orang yang selalu mengubah alam. Kegiatan manusia memperlakukan lingkungan alamiahnya, itulah kebudayaan. Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya. Kebudayaan merupakan aktivitas yang dapat diarahkan dan direncanakan. Oleh sebab itu dituntut adanya kemampuan, kreativitas, dan penemuan-penemuan baru. Manusia tidak hanya membiarkan diri dalam kehidupan lama melainkan dituntut mencari jalan baru dalam mencapai kehidupan yang lebih manusiawi. Dasar dan arah yang dituju dalam perencanaan kebudayaan adalah manusia sendiri sehingga humanisasi menjadi kerangka dasar dalam strategi kebudayaan
Dengan melihat kearifan lokal sebagai bentuk kebudayaan maka ia akan mengalami reinforcement secara terus-menerus menjadi yang lebih baik. Ali Moertopo mengatakan bahwa humanisasi merupakan ideal proses dan tujuan kebudayaan. Oleh karena itu maka kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan yang terjadi dengan penguatan-penguatan dalam kehidupannya menunjukkansebagai salah satu bentuk humanisasi manusia dalam berkebudayaan. Artinya sebagai manifestasi humanitas manusia, kearifan lokal dianggap baik sehingga ia mengalami penguatan secara terus-menerus. Tetapi, apakah ia akan tetap menjadi dirinya tanpa perubahan, benturan kebudayaan akan menjawabnya.
Dinamika kebudayaan merupakan suatu hal yang niscaya. Hal ini tidak lepas dari aktivitas manusia dengan peran akalnya. Dinamika atau perubahan kebudayaan dapat terjadi karena berbagai hal. Secara fisik, bertambahnya penduduk, berpindahnya penduduk, masuknya penduduk asing, masuknya peralatan baru, mudahnya akses masuk ke daerah juga dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan tertentu. Dalam lingkup hubungan antar manusia, hubungan individual dan kelompok dapat juga mempengaruhi perubahan kebudayaan. Satu hal yang tidak bisa dihindari bahwa perkembangan dan perubahan akan selalu terjadi. Di kalangan antropolog ada tiga pola yang dianggap paling penting berkaitan dengan masalah perubahan kebudayaan: evolusi, difusi, dan akulturasi.
Dalam perjalanannya, budaya Nusantara, baik yang masuk kawasan istana atau di luar istana, tidak statis. Ia bergerak sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan adanya kontak budaya, difusi, assimilasi, akulturasi sebagaimana dikatakan sebelumnya, nampak bahwa perubahan budaya di masyarakat akan cukup signifikan. Masih banyak lagi kajian tentang pergeseran dan perubahan budaya yang harus dieksplorasi lebih lanjut, diantaranya:
Benturan Nilai dan Relativtas Budaya
Individu dan kelompok masyarakat biasanya menganut nilai sendirisendiri. Bila terjadi pertemuan di antaranya dan satu dengan yang lain nampak tidak cocok, maka pihak yang satu biasanya merasa benar dan menyalahkan pihak yang lain. Apabila satu dianggap salah oleh yang lain maka ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan kultural bukan semata-mata bersifat subjektif atau pribadi tetapi lebih menjadi bersifat intersubjektif. Individu sesungguhnya tidak bertindak sendiri. Makna suatu tindakan adalah makna yang ditanggapi bersama dengan orang lain. Makna ini didasarkan pada asumsi-asumsi tindakan kultural. Oleh karenanya penilaian kultural menjadi relatif (meskipun dalam konteks etis ada pihak yang mengambil posisi relativisme etis dan absolutisme moral, dan menurut pandangan teologi, di atas relativitas tersebut yang mutlak adalah kebenaran Tuhan). Dalam budaya tertentu orang mungkin harus mengagung-agungkan dirinya di depan umum dalam rangka memberi semangat rakyat, tetapi dalam budaya yang lain tindakan tersebut mungkin dianggap sombong atau bahkan dilarang. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa dalam aneka ragam budaya dengan segenap nilai kulturalnya, ada pemahamanan yang tidak selalu sama antara yang dianggap baik di pihak yang satu yang berbeda dengan penilaian pihak lain.
Hal yang menjadikan masing-masing orang atau kelompok orang berbedabeda dan menilai sesuatu secara berbeda adalah karena orientasi nilai masingmasing mereka yang berbeda. Perbedaan latar belakang dan orientasi budaya inilah yang sering menyebabkan terjadinya konflik. Oleh karena itu perlu masingmasing orang atau kelompok orang menyadari perbedaan orientasi nilai budaya ini. Tentang bagaimana orang yang berbeda nilai budaya ini dapat saling memahami dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan jalan dialog. Jelas disini bahwa orientasi yang berbeda antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain akan menyebabkan bagaimana mereka menilai sesuai juga akan berbeda. Dalam konteks kearifan lokal, penjelasan ini memungkinkan akan adanya spesifikasi dari masing-masing budaya lokal yang muncul dan dapat diwacanakan.
Globalisasi
Globalisasi adalah suatu keadaan, tetapi juga suatu tindakan di mana aktivitas kehidupan tidak lokal dalam suatu negara tetapi mendunia. Globalisasi ini pada dasarnya mengacu kepada proses pembesaran, sejauh bentuk hubungan antara berbagai konteks atau wilayah sosial membentuk jaringan diseluruh permukaan bumi secara keseluruhan. Disinilah relasi sosial sedunia yang menghubungkan lokalitas yang saling berjauhan sedemikian rupa sehingga sejumlah peristiwa sosial dibentuk oleh peristiwa yang terjadi pada jarak bermil-mil dan begitu juga sebaliknya. Inilah yang merupakan proses dialektis karena peristiwa lokal mungkib bergerak ke depan dari relasi berjarak yang membentuk mereka. Hal ini misalnya dapat dilihat pada istilah ekonomi global ketika transaksi ekonomi dilakukan lintas negara secara massal. Istilah komunikasi global juga kita temukan ketika kita berbincang-bincang tentang penggunaan internet sebagai media komunikasi yang dapat mengakses berita dari seluruh dunia tanpa ada aturan yang terlalu ketat.
Globalisasi bukan gejala baru, bahkan negara-negara maju untuk masa sekarang ini sudah menggunakan istilah globalisasi baru (new globalism). Bagi Indonesia dan negara-negara Asia, globalisasi masih merupakan pengalaman baru. Globalisasi sebagai gejala perubahan di masyarakat yang hampir melanda seluruh bangsa sering dianggap ancaman dan tantangan terhadap integritas suatu Negara. Dengan demikian bila suatu negara mempunyai identitas lokal tertentu, dalam hal ini kearifan lokal, ia tidak mungkin lepas dari pengaruh globalisasi ini.
Dalam lingkungan yang pesimistik, globalisasi menyebabkan adanya globalophobia, suatu bentuk ketakutan terhadap arus globalisasi sehingga orang atau lembaga harus mewaspadai secara serius dengan membuat langkah dan kebijakan tertentu. Bagaimana pun globalisasi merupakan suatu yang tidak dapat dihindari sehingga yang terpenting adalah bagaimana menyikapi dan memanfaatkan secara baik efek global sesuai dengan harapan dan tujuan hidup kita. Dalam hal kearifan lokal Nusantara, bagaimana kearifan lokal tetap dapat hidup dan berkembang tetapi tidak ketinggalan jaman. Bagaimana kearifan lokal dapat mengikuti arus perkembangan global sekaligus tetap dapat mempertahankan identitas lokal kita, akan menyebabkan ia akan hidup terus dan mengalami penguatan. Kearifan lokal sudah semestinya dapat berkolaborasi dengan aneka perkembangan budaya yang melanda dan untuk tidak larut dan hilang dari identitasnya sendiri.
Problem Keamanan dan Kerentanan Potensi Konflik
Sebenarnya, potensi konflik di Indonesia memang sangat besar dan ada di setiap daerah. Menurut Sosiolog UI, Dr Imam B Prasojo, hal ini terkait dengan banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia, ada sekitar 656 suku yang mendiami 30 pulau. Masing-masing juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Terbesar kelompok Etnik Jawa (83.865.724/41,71 persen), disusul Etnik Sunda (30.978.404/15,41%), Etnik Melayu (6.946.040/3,35 %), Batak (6.076.440/3,02 %), Minangkabau (2,75 %), Betawi (2,51 %), Bugis (2,49 %), Banten (2,05 %), Banjar (1,74 %), Bali (1,51 %), Sasak (1,30 %), Makassar (0,99 %), Cirebon (0,94), Cina (0,86) dan etnik lainnya (15,95 %).
Menurut Imam Prasojo sumber konflik yang terjadi di Indonesia, dapat diakibatkan karena faktor struktural, seperti struktur politik, struktur sosial dan demografi, serta struktur ekonomi. Juga bisa berupa faktor-faktor akibat terjadinya saling interaksi atau hubungan sosial sebagai problem multi-kultur suku-suku yang ada. Karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya konflik, kearifan lokal yang ada perlu terus diup-date sesuai perkembangan zaman. Pluralitas masyarakat Indonesia menunjukkan hal itu, baik dari sisi suku, bangsa dan agama. Ini sebuah realitas harus disadari dan diterima oleh segenap komponen bangsa. Menurut Prof A Qodri Azizy, realitas ini merupakan garis yang telah ditetapkan Tuhan. karenanya kenyataan tersebut harus diterima.
Konflik sendiri menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta berarti pertentangan atau percekcokan. Disini konflik dapat diartikan sebagai adalah suatu bentuk hubungan interaksi seseorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain, dimana masing-masing pihak secara sadar, berkemauan, berpeluang dan berkemampuan saling melakukan tindakan untuk mempertentangkan suatu isu yang diangkat dan dipermasalahkan antara yang satu dengan yang lain berdasarkan alasan tertentu. Dengan kata lain konflik berarti ketidakstabilan, ketidakharmonisan dan ketidakamanan.
Konflik sosial yang melanda masyarakat dan dunia kita kini berakar pada konflik nilai secara holistik (pandangan hidup, kebenaran, moral, transendental). Tiap pribadi memiliki konflik dalam dirinya dan dengan orang lain karena perbedaan pendapat dan pandangan hidup. Konflik sosial muncul justru karena keterlambatan penanganan kasus individual berdasarkan penerapan hukum yang adil oleh aparat keamanan. Konflik sosial yang menggunakan bendera etnis dan agama perlu segera mendapat penanganan dan jalan keluar yang tak merugikan nilai-nilai dasar kemanusiaan.
Secara umum ada beberapa penyebab terjadinya konflik sosial. Pertama, pada tataran makroskopik, konflik sosial disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah dalam segala bidang yang sentralistik dengan dampak ketimpangan dan ketidak adilan dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan budaya. Kedua, pada tataran mikroskopik, konflik sosial yang terwujud dalam berbagai nuansa kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya kebijakan yang kurang memperhatikan kehidupan sosial kemasyarakatan pada aras masyarakat lokal
Pada masyarakat suku Sasak masalah keamanan dan kerentanan potensi konflik dapat diidentifikasi disebabkan oleh beberapa faktor yakni: Pertama. Faktor kesejarahan yang dimaksud disini adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap asal usul, perkembangan kebudayaan dan adat-istiadat yang ada sangat beragam, misalnya dalam bentuk pengelompokan perkampungan-perkampungan. Secara historis (untuk mengambil satu contoh dalam hal keagamaan misalnya) merupakan hasil peninggalan Raja Mataram Karang Asem menunjukkan adanya upaya penyatuan antara orang Sasak Muslim dengan orang Bali Hindu. Penghayatan terhadap filosofi itu semakin memudar, dan bahkan menghilang sama sekali, khususnya di kalangan generasi muda, meskipun secara geografis tinggal berdampingan. Kondisi itu telah menjadi pemicu munculnya persaingan dan solidaritas komunal, sehingga yang kemudian nampak adalah potensi konflik dan potensi integrasi semakin tenggelam dan semakin sulit untuk dapat muncul ke permukaan. Pandangan ini dibuktikan dengan karakteristik para pelaku yang berkonflik kebanyakan adalah anak-anak muda akibat emosi yang belum terkendali dan tidak adanya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kesejarahan yang mempersatukan. Selain itu yang terlibat biasanya adalah juga para pemukim-pemukim baru yang datang dari luar wilayah yang bersangkutan.
Kedua, faktor sosial dan ruang interaksi.Salah satu faktor terpenting kehidupan harmonis suku Sasak di NTB adalah adanya semangat hidup yang mengedepankan kerukunan dan terpeliharanya nilai-nilai untuk saling membantu diantara sesama meskipun berbeda kelompok. Ekspresi yang terlihat dalam praktek kehidupan sehari-hari antar komunitas ini adalah misalnya pada saat perayaan lebaran, orang-orang Hindu sangat terbiasa untuk mengunjungi tetangganya yang Muslim. Demikian pula pada kegiatan prosesi kematian. Jika ada warga Islam yang meninggal, warga Hindu dan lainnya bisa ikut melayat dan mengantar jenazah sampai ke kuburan mereka. Atau bila orang Hindu ada yang meninggal, orang Muslim datang ke rumah duka sambil membawa bahan-bahan kebutuhan yang dapat membantu keluarga yang ditinggalkan. Demikian pula dalam acara pesta perkawinan, pemeluk agama yang berbeda sudah terbiasa untuk tetap saling menghadirinya. Namun faktor ini, akan berubah menjadi konflik tatkala keadaan sosial dan ruang interaksi tidak lagi dikedepankan. Hal ini setidaknya juga diakibatkan oleh kebijakan yang kurang memperhatikan kehidupan sosial kemasyarakatan pada aras masyarakat lokal. Ketiga, faktor ekonomi, hal ini lebih diakibatkan oleh timpangnya distribusi pendapatan yang merata dan berkeadilan, tingkat kesenjangan yang demikian mencolok antara yang kaya dan miskin, disamping penjatahan “kue ekonomi” yang tidak sebanding dengan seharusnya.
Selanjutnya secara garis besar masalah keamanan dan kerentanan potensi konflik dapat kita golongan yakni yang berimplikasi menyebabkan terjadinya disintegrasi masyarakat dan faktor yang berpotensi melahirkan kerawanan ketertiban dan kenyaman masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Diantara beberapa faktor yang berimplikasi menyebabkan terjadinya disintegrasi masyarakat yakni: (1) Solidaritas komunitas kolektif yang dilandasi oleh ikatan emosional yang tidak rasional. (2) Keragaman suku/etnis/agama (3) Kegiatan agama misalnya pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, perayaan hari besar agama, perbedaan dalam keyakinan agama, perkawinan beda agama, bantuan luar negeri menyangkut hal keagamaan, dan tumbuh menjamurnya aliran keagamaan. (4) Penyelenggaraan Otonomi Daerah yakni yang terkait dengan adanya kompetisi tidak sehat dalam merebut jabatan strategis dalam pemerintahan, pendekatan struktural/primodial dalam menyelesaikan beragam permasalahan yang timbul, kebijaksanaan yang tidak mampu mengakomodir dan mengkoordinir berbagai organisasi dan keberagaman, penyediaan aset ekonomi yang eksklusif sehingga tidak dapat dijangkau secara merata oleh masyarakat dan pendekatan kekerabatan yang kental dengan nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. (5) Faktor-faktor lain semisal pembatasan ekses ekonomi dan kekuasaan, perbedaan persepsi dan benturan antar nilai, kompetisi terhadap asset yang memberi nilai tambah, kesenjangan ekonomi, perbedaan kepentingan politik, dan adanya porovokasi dan premanisme, kebencian terhadap kelompok/orang tertentu, persaingan masa lalu, perbedaan individual, tarik menarik kepentingan, benturan antara kepentingan masyarakat, perbedaan gagasan dan kebijaksanaan dalam menyikapi sesuatu, perbedaan nilai sosbud dalam merespon suatu ajaran, menggeneralisasi isu dan persoalan yang muncul, memudarnya/mandulnya kearifan lokal, dominasi pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan dalam perindustrian, simbol komunitas dihadapkan dengan simbol komunitas lain, kepadatan penduduk yang melampaui daya dukung wilayah, penyerobotan tanah, pengaruh alih tehnologi, pengaruh budaya mardial/global juga turut menciptakan kerentanan terjadinya konflik.
Disamping itu masalah keamanan dan kerentanan potensi konflik dapat juga berpotensi melahirkan kerawanan ketertiban dan kenyaman masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, misalnya: pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan perkelahian (individu maupun kelompok), pemalsuan uang, pemalsuan obat dan makanan, narkoba dan psychatropika, penyelundupan, miras, kenakalan remaja, bencana alam (gempa, banjir, kebakaran), pembakaran, premanisme, provokasi dan selebaran, Pam Swakarsa lintas Jota atau Kabupaten, penggunaan alat komunikasi HT, perebutan lahan ekonomi atau lahan usaha, pedagang kaki lima, pencemaran lingkungan (Lombok Industri), perusakan lingkungan dengan pengemboman ikan, perambahan hutan, penipuan, dukun palsu, santet, pengobatan tradisional, penjambretan, perjudian, dan lainnya.
Harus diakui, jarang munculnya konflik di daerah-daerah di Propinsi NTB masa-masa sebelumnya bukanlah berarti memang tidak ada "masalah" dalam hubungan dan interaksi sosial. Masalah-masalah selalu ada, namun dapat dipendam atau terkondisikan sehingga tidak sampai berujud menjadi konflik terbuka. Dari data-data masalah keamanan dan kerentanan potensi konflik, hal ini berarti bahwa terdapat kawasan atau wilayah yang secara nyata atau tidak sebagai kawasan atau wilayah yang mengandung potensi konflik. Potensi kerentanan konflik ada, namun potensi konflik juga nyata dan sewaktu-waktu dapat muncul, meskipun ada juga sarana peredam konfliknya.
Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Spirit Budaya dan Keagamaan
Dalam kehidupan ekonomi masyarakat suku Sasak selalu berupaya agar pengeluaran tidak boleh melebihi pemasukan. Apabila hal itu sampai terjadi, orang akan mengalami (lebih besar pasak dari pada tiang) hal ini berarti kebangkrutan. Keadaan orang itu umumnya dilukiskan sebagai “bele’an pasek daet teken”. Namun, acuan ini kadang juga diartikan sebagai keberatan beban ekonomi karena jumlah anak yang berlebihan. Selain itu, dalam kehidupan ekonomi, para orang tua suku Sasak berupaya untuk tetap bisa hidup mandiri hingga akhir hayat. Pada umumnya orang tua enggan hidup menumpang kepada anak. Karena, menumpang hidup kepada anak dianggap sebagai “belah piring” (pecah piring) yang berarti sudah tidak memiliki sumber penghidupan.
Untuk menjaga agar pemasukan dan pengeluaran tetap terkontrol, masyarakat pantang menjual padi sebelum padi masuk ke lumbung. Karena perkembangan zaman, dengan segala perhitungan untung rugi dan efisiensi, orang kadang menjual padi di sawah (tebasan). Akan tetapi, kearifan tersebut tidak bisa dikatakan tidak fungsional kerena sebenarnya kearifan tersebut lebih ditujukan kepada pantangan menjual padi secara ijon yang tentu saja harganya sangat murah dan biasanya merugikan petani.
Dipulau Lombok banyak dijumpai kearifan lokal dalam mengatur sistem sosial kemasyarakatan, seperti pengaturan pemerintahan desa dengan berbagai lembaga adat (seperti awig-awig yang terdapat di Bali), persubakan, keamanan, ekonomi, dan begitu pula kearifan lokal yang berkaitan dengan perlakuan terhadap lingkungan alam, seperti embung sebagai penyimpan cadangan air, pengaturan system tanam, penggunaan pupuk alam dan pemberantasan hama. Seperti misalnya system tanam padi Gogo Rancah (Gora) sekitar 1978, oleh karena pada saat masyarakat mengalami kondisi kekurangan bahan makanan berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya kelaparan pada setiap musim dengan tingkat kematian yang begitu besar, maka secara tiba-tiba timbul upaya yang brillian dari masyarakat sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Pada masyarakat suku Sasak di pulau Lombok, kearifan lokal merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan agama dan adat budaya. Karenanya denyut nadi kehidupan masyarakat sasak memerlukan cara-cara yang arif lagi bijaksana.
Dengan melihat kearifan lokal sebagai bentuk produk kebudayaan maka ia akan mengalami reinforcement secara terus-menerus menjadi yang lebih baik. Ali Moertopo, mengatakan bahwa humanisasi merupakan ideal proses dan tujuan kebudayaan. Oleh karena itu maka kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan yang terjadi dengan penguatan-penguatan dalam kehidupannya menunjukkan sebagai salah satu bentuk humanisasi manusia dalam berkebudayaan. Artinya sebagai manifestasi humanitas manusia, kearifan lokal dianggap baik sehingga ia mengalami penguatan secara terus-menerus. Tetapi, apakah ia akan tetap menjadi dirinya tanpa perubahan, benturan kebudayaan akan menjawabnya. Dinamika kebudayaan merupakan suatu hal yang niscaya. Hal ini tidak lepas dari aktivitas manusia dengan peran akalnya. Dinamika atau perubahan kebudayaan dapat terjadi karena berbagai hal. Secara fisik, bertambahnya penduduk, berpindahnya penduduk, masuknya penduduk asing, masuknya peralatan baru, mudahnya akses masuk ke daerah juga dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan tertentu. Dalam lingkup hubungan antar manusia, hubungan individual dan kelompok dapat juga mempengaruhi perubahan kebudayaan. Satu hal yang tidak bisa dihindari bahwa perkembangan dan perubahan akan selalu terjadi
Hierarki Pekerjaan
Secara umum masyarakat suku Sasak kurang memerhatikan hierarki pekerjaan. Artinya, pekerjaan apapun, dalam pandangan orang suku Sasak, tidak menjadi masalah, yang penting halal. Yang menjadi masalah adalah apabila seseorang tidak bekerja, apalagi jika sudah mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, orang suku Sasak tidak berkeberatan menjadi pekerja kasar, seperti kuli panggul, kuli bangunan, tukang gali kabel, tukang tarik becak dan lain-lain. Namun, sebenarnya tidak semua orang suku Sasak berpandangan demikian terhadap pekerjaan, khususnya masyarakat yang masih terikat oleh norma dan doktrin keagamaan yang tinggi misalnya ini terjadi jika mereka bekerja pada keluarga non-Muslim. Dan khususnya akhir-akhir ini dimana masyarakat suku sasak akan sangat berbangga sekali jikalau anak-anak mereka bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, pada kenyataannya tidak sedikit kalangan ini yang bekerja seperti itu. Terlebih jika daerah pekerjaan menempati daerah yang memang telah dikatagorikan sebagai daerah yang kurang menjunjung nilai-nilai etis keagamaan, semisal terminal atau pada lingkungan dengan kehidupan pekerja malam.
Pandangan negatif terhadap pekerjaan kasar tertentu itu sebenarnya lebih karena kekhawatiran sebagian kalangan suku sasak terhadap lingkungan perkerjaan yang dapat memengaruhi moral dan agama para pekerja kasar. Norma tersebut lebih ketat lagi bagi perempuan Muslim. Lebih ketat lagi bagi kalangan masyarakat yang masih terikat oleh norma dan doktrin keagamaan yang tinggi, yang memandang semua pekerjaan kasar sebagai pekerjaan yang tidak pantas bagi mereka, jika hal tersebut akan berpengaruh terhadap doktrin dan keyakinan keagamaan yang diyakini. Lingkungan para pekerja kasar tersebut, misalnya, tempat mangkal dokar atau terminal dikenal oleh masyarakat sebagai lingkungan yang kurang baik (kasar), di mana orang biasa berbicara kasar dan cabul. Hal tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi moral perkerja kasar. Demikian pula bekerja pada orang Cina atau yang beragama lain atau pribumi non-Muslim dikhawatirkan akan mempengaruhi agama mereka. Pekerjaan kasar di sawah, baik mengerjakan sawah sendiri maupun bekerja kepada orang lain -terutama yang Muslim- tidak pernah menjadi perbincangan. Sebaliknya, pandangan akan berbeda apabila menjadi pembantu pada keluarga non Muslim.
Dalam kalangan priyayi (ningrat) agama merupakan faktor utama dalam menentukan jenis pekerjaan, namun pekerjaan kasar memang tidak sesuai dengan budaya mereka yang halus, berbicara dengan lembut, memakai bahasa yang halus. Walau terkadang faktor berpakaian tidak terlalu diperhatikan, yang penting bersih, sopan dan menutup aurat Meskipun mereka di rumah dan hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong. Dengan penampilan yang sedemikian rupa tentu kalangan priyayi tidak pantas melakukan pekerjaan kasar apapun. Di balik kehawatiran dan pandangan ketidakpantasan pada pekerjaan kasar tertentu, di satu sisi pada kalangan priyayi terjadi penyempitan lapangan kerja. Lebih-lebih bagi mereka yang berasal dari keluarga berada dan terhormat, semakin banyak pekerjaan yang tidak pantas untuk mereka lakukan.
Nilai-Nilai Pendidikan
Sebagian anggota masyarakat yang memandang tinggi terhadap ilmu -untuk mencarikan biaya pendidikan- berpedoman pada pepatah “pilik buku, ngawan” (karena kehidupan itu mesti teratur dan memiliki aturan seperti halnya alam semesta). Hal inilah yang salah satunya menyebabkan orang suku Sasak mencarikan biaya sekolah dengan bekerja keras dan itupun ada tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu agar anak dapat “budi-kaye” yang merupakan kekayaan pribadi dari kesadaran akan “budi-daye” Sang Hyang Sukseme yang menurunkan “akal-budi” pada setiap diri manusia untuk mendapatkan kemuliaan hidup yang akan dibawa sampai meninggal dunia. Hal inilah yang akan mewarnai setiap pandangan, ucapan dan perbuatan masyarakat sasak menjadi adab budaya yang tidak hanya diukur dengan hasil karya secara material namun yang lebih penting adalah nilai-nilai yang diperoleh selama hidup yang tercermin dari pelaksanaan adat istiadat mereka, disamping itu dimaksudkan juga agar anak bisa memperoleh pekerjaan yang dapat meningkatkan derajat bagi dirinya dan sudah barang tentu akan berimbas kepada orang tua dan bangsanya.
Karena pendidikan, anak dapat mengangkat derajat orang tua. Hal ini sering diungkapkan oleh para penganjur pendidikan, baik orang tua maupun pendidik, dapat disimpulkan dalam ungkapan-ungkapan berikut: Solah mum gaweq, solah eam daet, bayoq mum gaweq bayoq eam daet (baik yang dikerjakan maka akan mendapat kebaikan dan buruk yang dikerjakan maka akan mendapatkan keburukan), piliq buku ngawan, semet bulu mauq banteng, empak bau, aik meneng, tunjung tilah. Seperti apa bahagianya orang tua punya anak seperti itu? Ungkapan tersebut sebenarnya mengandung nilai filosofis keagamaan yang sangat tinggi, dan dengan ungkapan tersebut diharapkan orang tua akan termotivasi untuk menyekolahkan anak dengan membayangkan kelak dia akan menuai jerih payahnya, mendapatkan anak ‘idaman’ seperti itu. Demikian pula si anak akan termotivasi menjadi anak ‘idaman’ yang dikagumi orang banyak.
Tujuan pendidikan anak untuk keutamaan akhlak bagi anak yang semakin banyak ilmu sering dianalogikan sebagai padi yang bernas yang semakin menunduk. Berbeda dengan anak yang tidak berhasil dalam pendidikan, sebagai kompensasi untuk menutupi kelemahannya ia akan bersikap congkak, yang dianalogikan sebagai padi yang tidak berisi yang semakin mendongak. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam menyekolahkan anak orang tua tidak terlalu berambisi terhadap outcomenya kelak, dengan keberhasilan yang bersifat materi. Paling tidak, anak disekolahkan agar tahu adat-istiadat, tata krama dan tidak memalukan orang tua. Karena, apabila anak tidak disekolahkan, ada kekuatiran bahwa anak bukan hanya tidak tahu sopan santun, tetapi juga akan berbuat hal-hal yang tidak terpuji, sehingga aibnya juga akan berimbas kepada orang tua. Sebagaimana kata pepatah “buah tidak jatuh jauh dari pohonnya” (sifat anak tidak jauh berbeda dengan orang tuanya)
Dalam pandangan masyarakat suku Sasak, ‘siapa anak siapa’ bahkan ‘siapa keturunan siapa’ (bobot, bebet, bibit) masih kental dalam pikiran mereka. Apabila ada anak yang berprestasi atau berbudi pekerti baik dan kebetulan orang tuanya juga baik. Seperti ungkapan di atas “buah tidak jatuh jauh dari pohonnya” (sifat anak tidak jauh berbeda dengan orang tuanya) Ucapan yang sama akan terlontar pula bila ada anak berbuat aib dan kebetulan dia dari keluarga yang kurang baik pula. Sebaliknya, orang akan kagum bila ada anak dari kelurga yang kurang baik tapi dia berbuat terpuji, meskipun hanya perbuatan kecil. Lebih mengagetkan bila ada anak berbuat aib, sementara dia berasal dari keluarga baik-baik, maka orang akan menyebut-nyebut bapaknya, bahkan kekeknya. Oleh karena itu, anak-anak dari keluarga baik-baik akan mendapat pengawasan ekstra tidak hanya dari orang tua, tetapi juga dari keluarga besar orang tuanya, bahkan dari anggota masyarakat yang lain
Interaksi Sosial Sebagai Proses Pembelajaran
Masyarakat suku Sasak sangat memandang penting pergaulan (silaturrahmi) dengan sesama anggota masyarakat lainnya. Mereka memandang pergaulan dengan sesama anggota masyarakat sebagai proses pembelajaran dan menganalogikannya dengan sapu lidi yang terkumpul, akan dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Apabila satu biji lidi yang digunakan, maka hal tersebut kurang berarti. Akan tetapi, karena sapu lidi disatukan maka permasalahan akan dengan mudah terselesaikan. Demikian pula, dalam pergaulan akan terjadi pergesekan (asah, asih, asuh (Lombok Barat) tatas, tuhu trasna (Lombok Tengah) dan patuh karya (Lombok Timur) maju dan religious (Mataram) dan visi pemerintah NTB yang beriman dan berdaya saing), sehingga proses pendidikan dan anak akan semakin dewasa dan matang tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Meliputi aspek sosial dan keagamaan.
Dalam kehidupan bertetangga, agar tetap rukun dan tidak muncul kebencian karena tidak ada pemberian dari tetangga yang punya hajat, orang tua maupun para guru sering berpesan bahwa apabila ada tetangga yang mempunyai hajat, jangan berharap pemberiannya, apalagi sampai tidak masak. Karena ada kearifan tersebut, maka masyarakat suku Sasak malu dan dirasakan sebagai aib jika ada orang ribut karena tidak diundang atau diantar makanan oleh tetangga yang punya hajat. Berbeda dengan di daerah lain, misalnya di Yogyakarta dan Klaten, masalah undangan (punjungan) ini sangat peka dan sering menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bertetangga. Oleh karena itu, di dua daerah tersebut perangkat desa membentuk kelompok-kelompok kenduren (tangga sak kenduren). Namun demikian, tidak jauh berbeda dengan hal ini, orang suku Bali atau suku Sasak saat ini, juga telah membentuk suatu komunitas yang terkabung dalam banjar. Banjar ini memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah tolong-menolong dengan tetangga yang memiliki hajatan.
Berbeda dengan banjar pada suku Sasak dan Bali, kelompok kenduren dimaksudkan agar orang tahu batas-batas tetangga yang mana yang harus diundang atau diantar makanan dalam upacara. Dengan adanya kelompok kenduren ini, bisa jadi tetangga samping rumah tidak perlu diundang atau diantar makanan, karena tidak termasuk kelompok kenduren. Namun pada suku Sasak hal tersebut tampaknya tidak berlaku, hal ini juga diperkuat oleh doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa yang termasuk tetangga adalah empat puluh rumah yang mengitari rumah orang yang melakukan hajatan, jadi harus diundang, namun adakalanya juga undangan bagi orang yang melakukan hajatan hanya dibatasi hingga sebatas RT/RW/lingkungan hal ini lebih dipertimbangkan sebagai akibibat besar-kecilnya upacara yang akan dilakukan.
Acuan untuk mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan sosial suku Sasak antara lain adalah trasna (yang berarti menjunjung tinggi budi pekerti, jiwa kasih saying terhadap sesame patuh dan taat kepada orang tua, guru, pemimpin serta masyarakat dan bangsa) sehingga hal ini akan dipersepsi sebagai kerukunan dapat membentuk kekuatan, pertengkaran mengakibatkan kehancuran. Selain hal ini, masyarakat sering menganalogikan kerukunan sebagai sapu lidi -sebagaimana yang diuraikan sebelumnya-. Sapu lidi yang merupakan suatu ikatan dari sekian banyak lidi, maka ia sulit untuk dipatahkan. Dengan demikian, kalau kita rukun kita akan dapat membentuk sebuah kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan. Akan tetapi, kalau ikatan sapu lidi itu putus dan masing-masing lidi berdiri sendiri-sendiri, maka lidi- lidi itu akan sangat mudah untuk dipatahkan. Dengan demikian, kalau kita tidak rukun dan kita berdiri sendiri-sendiri, maka kita akan mudah dikalahkan oleh lawan-lawan kita.
Dengan berpegang pada pepatah-pepatah yang memiliki nilai-nilai kerukunan, anggota masyarakat yang terlibat konflik -terutama yang merasa dirinya tidak bersalah- tidak terlalu peduli untuk mempertajam konflik. Ia dan orang-orang yang ada disekitarnya akan mengatakan “solah mum gaweq, solah eam daet, bayoq mum gaweq bayoq eam daet” (baik yang dikerjakan maka akan mendapat kebaikan dan buruk yang dikerjakan maka akan mendapatkan keburukan). Disinilah masyarakat suku Sasak memahami bahwa seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutkan evolusinya, hingga mencapai tujuan penciptaan. Kehidupan mahluk-mahluk Tuhan saling terkait. Bila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, maka mahluk yang berada dalam lingkungan hidup akan ikut terganggu pula.
Jika konflik terjadi antara individu yang tidak setara tingkat pendidikan atau tingkat sosial ekonominya, orang yang lebih tinggi tingkat pendidikan atau tingkat sosialnya akan lebih memilih diam dan menenangkan keadaan, hal ini setidaknya mengacu pada “sere’at tedok, tedok mas” (lebih baik diam dan menenangkan suasana dari pada memicu konflik, dan diam adalah emas). Demikian pula orang-orang yang ada disekitarnya akan menasehati dengan menggunakan pepatah yang sama, bahwa konflik dan perselisihan itu tidak ada gunanya, bahkan akan menambah buruk keadaan. Sehingga ia akan memilih tidak melanjutkan konflik dengan orang yang statusnya lebih rendah tersebut. Agar orang tidak timbul dendang kusumat, maka orang yang terlibat dalam konflik -yang merasa posisinya ‘di atas angin’- tidak akan berbuat berlebihan terhadap lawan konfliknya. Ia tidak akan mempermalukan lawan konfliknya di depan umum karena ada pepatah yang ia pegangi, “dende’ boyak musuh, laguk lamun datang ya’te layani” (musuh tidak dicari namun jika bersikeras maka akan dilayani) disinilah orang suku Sasak sangat menjunjung persaudaraan, namun demikian sikap tidak merendahkan juga akan ditunjukkan jikalau ia merasa “di atas angin”.
Hubungan antara manusia dan alam atau hubungan manusia dan sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dan hamba, namun lebih merupakan hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Tuhan. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugrah Tuhan. Setelah menyadari pandangan agama tentang makna kekhalifahan manusia yang menjadi tujuan penciptaan di muka bumi, maka tidak heran bila puluhan bahkan ratusan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang dijadikan landasan dalam berpijak guna tercapainya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat
Selain suku Minang dan suku Jawa, suku Sasak termasuk yang jarang terlibat konflik, meski suku Sasak tidak memiliki pepatah “dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Namun, masyarakat suku Sasak memiliki awig-awig yang menunjukkan bahwa masyarakat menyadari jikalau setiap desa atau daerah memiliki tatacara dan adat-istiadat sendiri-sendiri. Karena itu, ketika mereka akan merantau atau akan bertamu atau bahkan melamar calon menantu di daerah lain, mereka akan mencari informasi tentang adat- istiadat daerah yang akan dituju. Apabila mereka tidak memperoleh informasi sama sekali, mereka sadar adat-istiadat mereka pasti berbeda dan mereka akan sangat berhati-hati dalam berprilaku dan bertindak.
Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pola kehidupan yang relatif tetap memiliki aturan dasar yang turun temurun dan menjadi norma hidup dari komunitas masyarakat sasak. Aturan norma ini disimbulkan dengan “”buku-ngawan karena kehidupan itu mesti teratur dan memiliki aturan seperti halnya alam semesta. Dari mana memulai membangun “bale-langgak” (rumah dan kelengkapannya), berugaq-sekepat, alang-sambi, leah-lambur, jebak, pengorong, kemudian menjadi pemukiman dengan istilah “gubug-gempeng” dan seterusnya sehingga terbentuklah “dise-dasan”. Secara harmonis kehidupan “dise-dasan” sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam sekitar, khususnya berhubungan dengan istilah “epe-aik” yang menjadi sumber dari segala sumber hidup dan kehidupan komunitas masyarakat sasak.
Untuk itu pula, apabila ada seorang anak akan pergi jauh (merantau), orang tuanya, terutama sang ibu, selalu menasehati (pesan dengan sungguh-sungguh), “Jagak dirikm lek gubuk, dise, dasan dengan, solah-solah ntam daet dirikm, dendek lupak sembahyang daet kabari dengan lek bale” (Hati-hati di rantau, baik-baiklah berakhlak, jangan lupa sembahyang dan beri kabarlah kepada keluarga dirumah). “lamun arak ape-ape lebih solah ngalah, sengakn dengan sak ngalah yan daet kemulyean” (Kalau ada apa-apa lebih baik mengalah. Orang yang mengalah pada akhirnya akan memperoleh kemulyaan). Karena itu, pada umumnya dalam menghadapi konflik para perantau suku Sasak cenderung menghindar, meskipun kemudian “ngeremon” (bergumam dengan nada kesal), “lamuk ndek enget pesen inak jak ndek taon ape yak jarin!” (kalau tidak ingat pesan ibu, maka tidak tahu apa yang bakal terjadi!).
Dalam berbuat kesalahan atau penyimpangan, masyarakat suku sasak terkadang memberlakukan batas-batas kewajaran. Batas-batas tersebut sebenarnya relatif, namun masyarakat bisa memahami batas-batas tersebut. Apabila ada orang yang membuat kesalahan atau penyimpangan yang dianggap melebihi batas, orang-orang di sekitarnya akan menyindir atau menasehati, namun jangan melampuai batas.
Budaya Ekspresif dan Impresif Suku Sasak Dalam Interaksi Hidup Bermasyarakat
Di satu sisi, masyarakat suku Sasak memiliki sikap ekspresif, yang lebih mencerminkan hasrat yang meluap-luap. Di sisi lain, masyarakat suku Sasak juga berada dalam lingkungan yang memiliki kebudayaan adiluhung yang mengutamakan sopan santun, etika, budi pekerti, dan pemikiran yang lebih panjang, yang mengkondisikan masyarakat juga mampu bersikap impresif. Kondisi ini menciptakan karakter sosio-kultural-religius yang spesifik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam seni-budaya.
Dalam kehidupan sehari-hari, budaya yang bertolak belakang ini tampak pada perilaku masyarakat sesuai dengan status sosial, tingkat pendidikan dan ketaatan mereka terhadap agama. masyarakat yang pada umumnya berpendidikan rendah dan kurang taat terhadap agama, serta termasuk biasa melanggar pantangan, cenderung berbudaya ekspresif. Mereka demikian ekspresif dengan apa yang ada pada benak mereka. Misalnya, apabila marah mereka dengan mudahnya mengumpat dengan umpatan-umpatan kotor khas suku sasak, seperti bajingan! botek! acong! dan lain-lain. Sementara kalangan yang berstatus sosial tinggi, berpendidikan, dan tingkat ketaatannya dalam beragama cukup tinggi, cenderung berbudaya impresif. Demikian pula kalangan yang mengutamakan etika cenderung berperilaku impresif. Mereka lebih memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi. Kalaupun mereka marah, mereka tidak biasa melampiaskannya dengan kata-kata kasar, apalagi jorok.
Kalangan ini sangat mentabukan umpatan-umpatan kasar dan jorok. Bahkan, berbicara kasar dengan nada tinggi sudah dinggap tidak pantas. Apabila ada anak dari lingkungan mereka mengucapkan kata-kata kasar, seseorang akan menegurnya. Karena para kalangan yang berstatus sosial tinggi, berpendidikan, dan tingkat ketaatannya dalam beragama cukup tinggi lebih mengutamakan keutamaan akhlak, dan mengutamakan etika, mereka tidak suka anak-anaknya menirukan perilaku orang yang bicara (keras, kasar dan jorok), cara duduk yang mengandung macam pantangan yakni minum minuman keras, judi, berzina, menghisap candu, dan mencuri
Budaya Ekspresif versus Impresif Suku Sasak
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, budaya ekspresif dan budaya impresif tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan dalam seni-budaya. Dalam seni budaya, kedua budaya yang saling bertolak belakang itu antara lain tercermin dalam kesenian, misalnya kesenian wayang, baik wayang orang maupun wayang kulit. Misalnya dalam kesenian wayang orang ini menunjukkan kostum yang bersahaja, kisah yang sederhana, irama musik yang keras diselingi letupan bunyi pengarah cerita yang cukup keras, dengan klimaks menampilkan ide pokok sebuah cerita pewayangan. Ditambah beberapa atraksi antagonis yang makin menambah seramnya pertunjukan.
Pada waktu pemain wayang orang menampilkan beberapa adegan pewayangan, anak-anak muda yang menonton bersuit-suit, sehingga pemain bertambah semangat. Kendatipun pertunjukan wayang orang ini kurang memiliki nilai seni dan lebih memamerkan kisahnya, namun justru pada beberapa atraksi antagonis yang berbau kekerasan tersebut pertunjukan ini memiliki nilai heroisme. Contoh lain misalnya, kisah Cupak-Gerantang, Arye Banjar Getas dan Putri Mandalika (Putri Nyale). Oleh karena itu, pertunjukan ini lebih banyak disukai kalangan laki-laki muda.
Di sisi lain, dalam pertunjukan seni tari yang serba halus, meliputi irama musik, dan tariannya. Dominasi perempuan muda belia sebagai penari, bahkan untuk peran laki-laki, semakin memperhalus gumulainya tarian juga dilengkapi dengan kostum yang indah berwarna-warni dengan berbagai hiasan pernik-pernik. Ada tambahan aksesoris yang juga berwarna-warni. Semuanya itu menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap nilai estetika seni tari.
Sebenarnya baik budaya ekspresif maupun budaya impresif tidak bisa dinilai yang satu negatif dan yang lain positif. Karena, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, untuk menghindarkan dampak negatif dari budaya ekspresif yang lebih didominasi oleh hasrat yang meluap-luap, Romo Muji Sutrisno, mengatakan kurang lebih, budaya ekspresif dapat diperhalus dengan pendidikan. Dalam pendidikan orang dikenalkan kepada tata krama, moral, agama, dan budaya yang halus.
Dengan saling berhadapannya antara budaya ekspresif dan budaya impresif, baik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari maupun dalam seni-budaya, maka sebenarnya telah terjadi proses pembelajaran secara alami (natural). Para penggemar wayang dan presean misalnya yang terdiri dari anak-anak muda dan orang tua (khususnya laki-laki) menunjukkan bahwa wayang dan peresean sebagai represantasi budaya ekspresif memang sangat cocok dengan jiwa muda yang sedang menggebu-gebu. Akan tetapi, apakah anak-anak muda ini ketika sudah termakan usia tetap menjadi penggemar fanatik versi idolanya? Ternyata dengan semakin tua usia dan melalui proses pendidikan formal maupun non-formal, mereka mulai mengenal falsafah hidup -khususnya falsafah hidup suku Sasak yang bersendikan agama dan adat budaya. Maka, tanpa disadari juga telah terjadi proses pendewasaan yang hakiki, sehingga mereka tidak lagi mengagumi wayang banyak menampilkan peperangan itu. Sebaliknya mereka juga mulai senang merenungi dan menghayati, bahkan larut dalam pertunjukkan kisah-kisah masyarakat suku Sasak yang sarat dengan nilai-nilai falsafah dan pandangan hidup suku Sasak.
Disamping itu budaya ekspresif dan budaya impresif tercermin juga dalam seni dan budaya yang mengambil bentuk panjat pinang, dimana hal ini biasanya dilakukan saat perayaan-perayaan hari besar, baik agama maupun nasional, atau pada saat adanya pagelaran wisata budaya. Dan biasanya perayaan panjat pinang ini banyak digemari oleh orang laki-laki.
Aktualisasi Kearifan Lokal Dalam Mencegah Konflik
Salah satu bentuk kearifan lokal lainnya pada suku Sasak yakni institusi slametan yang berkaitan dengan kerukunan dalam kehidupan beragama. Kerukunan dan keselarasan menggunakan media slametan pada suku Sasak tercermin dalam slametan kelahiran anak, selametan kematian, slametan ibadah keagamaan seperti haji, slametan untuk menuntut ilmu dan rizki dan bermacam-macam bentuk slametan lainnya. Pada masyarakat suku Sasak jika dalam acara slametan ini maka tidak seorangpun merasa dirinya dibedakan dari orang lain.
Hal ini juga diutarakan Franz Magnis Suseno, bahwa slametan dapat dimengerti sebagai ritus pemulihan keadaan slamet (selamat). Karena semua tetangga ikut hadir, slametan mengungkapkan bahwa di antara tetangga terdapat kerukunan dan keselarasan, dengan demikian kesadaran ketentraman masyarakat diperbaharui dan kekuatan berbahaya dinetralisir.
Dengan adanya slametan masyarakat suku Sasak maka akan dapat menciptakan hubungan yang harmonis, tanpa adanya jarak antara orang per orang dan kelompok dalam komunitas masyarakat. Namun demikian meskipun dengan adanya jarak dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat suku Sasak –dan hal ini tidak dapat dipungkiri-, antara banyak varian namun dengan slametan akan tetap terjaga keharmonisannya. Dengan slametan ini masyarakat suku Sasak juga sadar dan tidak menutup mata jika kehidupan mereka memang berbeda dan mereka juga biasa memuji kepada orang-orang yang mampu menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan tercela.
Berdasarkan kearifan lokal dan aturan adat budaya ini, maka muncul budaya tradisional masyarakat sasak yang tidak lepas dari pola trinitaris dasar yakni: pertama, “epe-aik” sebagai pemilik yang maha kuasa atas segala asal kejadian alam dan manusia. Kedua, “gumi-paer” sebagai tanah tempat berpijak di situ langit dijunjung, karena di “gumi-paer” ini masyarakat sasak dilahirkan. Diberi kehidupan dan selanjutnya diwafatkan. Ketiga, “budi-kaye” yang merupakan kekayaan pribadi dari kesadaran akan “budi-daye” Sang Hyang Sukseme yang menurunkan “akal-budi” pada setiap diri manusia untuk mendapatkan kemuliaan hidup yang akan dibawa sampai meninggal dunia. Ketiga hal inilah yang akan mewarnai setiap pandangan, ucapan dan perbuatan masyarakat sasak menjadi adab budaya yang tidak hanya diukur dengan hasil karya secara material namun yang lebih penting adalah nilai-nilai yang diperoleh selama hidup yang tercermin dari pelaksanaan adat istiadat mereka.
Tantangan Penggalian dan Peluang Analisisnya
Uraian di atas sebenarnya diharapkan dapat menunjukkan adanya lahan subur untuk penggalian kearifan lokal suku Sasak di pulau Lombok. Luasnya budaya dan kemungkinan pengembangannya menjadi tantangan tersendiri. Di samping itu perspektif perubahan yang terjadi juga menjadi peluang tersendiri untuk menelusuri eksistensinya. Dari unsur internalnya sendiri sampai yang eksternal seperti pengaruh lintas budaya dan globalisasi.
Ada banyak hal untuk menjelaskan bagaimana pengaruh hubungan lintas budaya dan globalisasi mempengaruhi kearifan lokal. Dalam perspektif nilai hal tersebut dapat dilihat misalnya dalam nilai etis, apa yang dianggap baik pada budaya masa lalu tidak tentu demikian untuk masa sekarang. Apa yang dianggap wajar dan diterima pada budaya masa lalu mungkin sekarang dianggap aneh, atau sebaliknya. Kita dapat melihat bagaimana orang menanggapi cara berpakaian jaman sekarang, dengan model pakaian (agak) terbuka itu dianggap wajar, tetapi tidak demikian dengan orang dulu. Begitu juga bagaimana laki-laki dan perempuan bergaul, berbeda baik menurut pengertian budaya orang dulu dengan orang sekarang. Hal-hal tersebut menunjukkan betapa kearifan lokal itu mendapat banyak tantangan dengan adanya pengaruh budaya asing. Peluang penggalian dan analisis dapat juga dilihat dari aspek nilai lain di bawah ini
Dalam konteks nilai religi, hubungan antara religi dan perkembangan budaya juga menunjukkan hal serupa. Bagaimana keberagamaan (bereligi) orang suku Sasak berubah akibat pengaruh luar. Antara lain pergeseran ini menyebabkan penampilan budaya suku Sasak menjadi berbeda antara dulu dan sekarang terlebih yang akan dating, bagaimana nilai tertentu terkait dengan kehidupan religius lokal bertemu dengan budaya asing di Arab sendiri dan di Indonesia. Dalam kasus Indonesia juga dijelaskan bagaimana Islam yang berkarakter dinamis, elastis, dan akomodatif dengan budaya lokal dapat berjalan bersama dan -mengutip Gus Dur-, terjadi pribumisasi Islam. Dalam konteks nilai intelektual misalnya masalah kesehatan dalam penyembuhan penyakit, masyarakat suku Sasak sangat kaya dari pangalaman intelektual tentang pengobatan dengan obat tradisional sampai yang memanfaatkan kekuatan supranatural.
Sebenarnya gagasan Pribumisasi Islam yang ditawarkan Gus Dur dimaksudkan untuk mencairkan pola dan karakter Islam sebagai sesuatu yang normative dan praktek keagamaan menjadi sesuatu yang kontekstual. Dalam Pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normative berasal dari tuhan di akomodasikan kedalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpakehilangan identitasnya masing-masing. Arabisasi atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, namun justru agar budaya itu tidak hilang. Disini menurut Gus Dur, inti Pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.
Ada banyak peluang untuk pengembangan wacana kearifan lokal masyarakat suku Sasak. Dari beragam bentuk dan fungsinya yang dalam penanggulangan konflik misalnya dapat dilihat pada pemaparan di atas. Di samping itu kearifan lokal dapat didekati dari nilai-nilai yang berkembang di dalamnya seperti nilai religius, nilai etis, estetis, intelektual atau bahkan nilai lain seperti ekonomi, teknologi dan lainnya. Maka kekayaan kearifan lokal masyarakat suku Sasak menjadi lahan yang cukup subur untuk digali, diwacanakan dan dianalisis mengingat faktor perkembangan budaya terjadi dengan begitu pesatnya.
Memang, hal ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana kearifan lokal masyarakat suku Sasak menyikapi nilai-nilai kearifan lokal disosialisasikan dari generasi ke generasi, nilai-nilai kearifan lokal manakah yang masih berlaku atau fungsional, dan bagaimana nilai kearifan yang masih fungsional itu dipedomani oleh masyarakat sebagai landasan berinteraksi, baik secara individual maupun kelompok, terutama dalam lingkup kehidupan beragama, baik secara intern maupun ekstern. Pemikiran ini setidaknya merupakan sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu yang berharga atau tidak berharga dan sesuatu yang dapat menyelamatkan atau mencelakakan. Semua ini dapat terjadi karena kearifan lokal itu diselimuti oleh nilai-nilai moral yang bersumber pada agama, pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia.