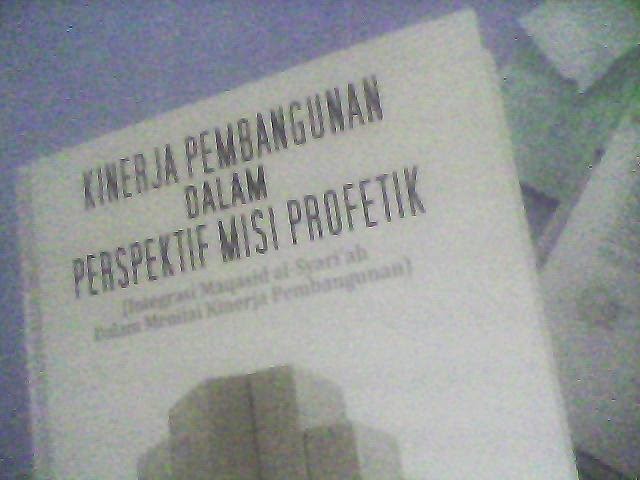Kata Pengantar
dalam Buku
KINERJA PEMBANGUNAN
DALAM PERSPEKTIF MISI PROFETIK
(Integrasi
Maqashid al Syariah dalam Menilai Kinerja Pembangunan)
(Yogyakarta:
Pustaka Cendikia Publishing, 2014).
Penulis: Hermansyah, SEI., MSI.
Penulis: Hermansyah, SEI., MSI.
MISI PROFETIS VERSUS TAFSIR STATISTIK
Oleh:
Dr. Yusdani,
M.Ag.
(Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam,
Ketua Divisi Kajian & Penelitian Pusat Studi
Islam UII Yogyakarta)
Realitas
masyarakat Indonesia sebagaimana digambarkan oleh seorang bocah yang menulis
sajak pendek: Indonesia, di mana alamatmu? Bagi bocah ini, Indonesia ibarat
rumah yang memiliki alamat administratif jelas: Senayan atau Istana Merdeka.
Namun, sangat mungkin sajak itu justru menggoda kita, benarkah negara ini punya
alamat?[1]
Jika
ditanya soal alamat negara, yang terbayang adalah posisi eksistensi dan orientasi nilai suatu bangsa. Dalam konteks ini,
frase alamat negara dapat dipahami secara ideologis dan konstitusional. Jadi,
alamat Indonesia adalah Pancasila (way of
life/orientasi nilai), sedangkan rumah Indonesia adalah UUD 1945. Namun,
bangsa ini kini semakin kehilangan Indonesia dalam konteks ideologis dan
konstitusional. Indonesia telah menjelma menjadi negeri yang berada di dunia
antah-berantah seperti dalam jagat fiksi.[2]
Sebagai
alamat dan rumah, Pancasila dan UUD 1945 semakin terasa mengabur dalam
kehidupan. Jika dicari, akan ditemukan mereka ”digembok” di dalam ruang ritual
kebangsaan yang sunyi dan terasing. Artinya, Pancasila dan UUD 1945 hanya
muncul dalam ritus-ritus peneguhan kebangsaan yang dilakukan secara retorik.[3]
Para
penyelenggara negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) masih merasa perlu
mengeksploitasi secara retorik Pancasila dan UUD 1945 agar mendapatkan
legitimasi dari rakyat. Sementara break-down
dan praksis kerja mereka cenderung tidak berwatak solider terhadap rakyat,
seperti yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, melainkan lebih membela
kepentingan kekuatan kapital dan pasar bebas (neoliberalism) yang berprinsip ”hanya yang kuatlah yang bertahan
dan berkuasa”. Ini terkait dengan perubahan paradigma kehidupan bangsa. Sebelum
tahun 1965, kehidupan masyarakat Indonesia bercorak populis, sipil, dan
anti-modal asing; sedangkan pasca-1965, masyarakat Indonesia bercorak elitis,
militeristik, dan pro modal asing.[4]
Negara
pun akhirnya tidak sepenuhnya menjadi lembaga pelayanan bagi warganya,
melainkan cenderung menjadi agen kekuatan kapital. Adapun para penyelenggara
negara cenderung menjadi kumpulan panitia pasar bebas. Kebijakan-kebijakan yang
dilakukan tidak merespons problem warga negara yang riil dan urgen, melainkan
lebih melayani kepentingan kapital dan pasar global. Rakyat pun dikategorikan
sebagai bagian dari pasar global yang sah untuk dieksploitasi secara ekonomis
dan kultural. Rakyat tidak dipahami sebagai komunitas besar yang melekat pada
eksistensi negara dan berhak dilindungi.[5]
Rakyat
pun menjelma menjadi anak yatim-piatu. Tanpa diberi modal dan kemampuan secara
optimal oleh negara, rakyat dipaksa bertarung melawan kebengisan kekuatan dan
kuasa modal. Negara tega membiarkan rakyatnya menjadi bangsa konsumen, padahal
negara semestinya mendorong bangsanya menjadi bangsa produsen yang kreatif dan
mandiri.[6]
Negara
cenderung ”tidak merasa bersalah” ketika berhasil menciptakan lapangan kerja
bagi jutaan tenaga outsourcing yang
upah harian/mingguan/bulanannya tak cukup untuk hidup minimum. Negara juga
menciptakan disorientasi kultural melalui mesin-mesin dan industri budaya massa
sehingga rakyat pun lahir sebagai kumpulan manusia yang seragam, baik dalam
budaya ide, budaya perilaku/ekspresi, maupun dalam budaya material.[7]
Ironi Tafsir Statistik
Persoalan
sosial, ekonomi, dan budaya yang menelan rakyat cenderung ditutup dengan karpet
merah bernama tafsir statistik yang
menarasikan kesuksesan negara dalam mengatasi kemiskinan, memberantas korupsi,
menekan angka pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Merasa
sebagai hero, berbagai kesuksesan itu
diucapkan secara fasih dan lantang oleh aktor-aktor politik istana.[8]
Namun,
narasi tafsir statistik itu menjadi ironi getir ketika berhadapan dengan
realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang day
to day dihadapi rakyat. Rakyat menggigil dan gemetar ditelan kehidupan
berbiaya tinggi yang serba tidak pasti dan tak bisa ditawar; bahkan hanya untuk
mendapatkan sesuap nasi. Rakyat pun dipaksa untuk kreatif, misalnya dengan
menyulap nasi basi menjadi nasi aking
(kering). Kepedihan itu terasa semakin menyayat ketika negara justru royal
membelanjakan anggarannya dengan membeli pesawat untuk presiden, mobil mewah
untuk pejabat, dan kebutuhan lain yang tak urgen.[9]
Ketika
negara off dari tanggung jawab
ideologis dan konstitusional sebagaimana digambarkan di atas, pusat dinamika
masyarakat berada di tangan kuasa modal dan kuasa pasar. Sampai-sampai, pusat
perbelanjaan yang dinyatakan melakukan praktik monopoli oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) malah dimenangkan kasusnya oleh pengadilan, tak lama
setelah petinggi negara ini bertemu presiden direktur (CEO) perusahaan itu di
Paris. Modal bukan lagi bermakna sebagai kapital an sich, tetapi menjelma
menjadi ”panglima” yang menentukan seluruh dinamika negara dan masyarakat. Begitu
pula dengan pasar yang tidak sekadar berarti ”kesepakatan jual-beli”, melainkan
sudah menjadi pusat legitimasi bagi kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan
budaya.[10]
Siapa
pun yang tidak tunduk dan patuh kepada kuasa modal dan pasar, dimohon secara
tidak hormat untuk tersingkir dan termarjinalisasi. Jangan heran jika para
pemimpin yang lahir kemudian adalah mereka yang mampu kompromi dengan kuasa
modal dan pasar. Semua harus ”dibeli”, termasuk jabatan presiden, menteri,
anggota DPR, jaksa, hakim, gubernur, bupati/wali kota, dan lainnya.
Pemimpin-pemimpin yang lahir pun tidak lagi dari rahim sosial-kultural:
integritas, kapabilitas, dan komitmen. Pragmatisme yang digerakkan kuasa modal
dan pasar telah mendisfungsionalisasi rahim itu.[11]
Kuasa
modal dan pasar melahirkan kehidupan bernegara yang serba artifisial dan tanpa
visi profetik (membebaskan dan mengangkat eksistensi manusia). Rakyat pun
memasuki ranah simulacra atau dunia seolah-olah. Seolah-olah punya pemimpin,
seolah-olah punya wakil rakyat, seolah-olah hidup sejahtera, seolah-olah
demokratis, seolah-olah mendapatkan keadilan, bahkan seolah-olah punya negara
yang melindungi.[12]
Dunia
simulacra tersebut di atas dibangun oleh negara, kuasa kapital, dan pasar
melalui budaya simbolik yang merepresentasikan impian kolektif rakyat. Rakyat
dipisahkan dari kehidupan yang riil dan otentik agar tidak kritis terhadap
realitas semu yang mengepungnya, termasuk mempertanyakan di mana sesungguhnya
”alamat” Indonesia, seperti puisi bocah tersebut di atas. Bangsa Indonesia pun semakin kehilangan Indonesia yang sangat
mereka cintai.[13]
Misi Profetik Agama
Melihat realitas persoalan bangsa
tersebut di atas, menjadi momen tepat dan urgen untuk merefleksikan kembali
keberagamaan kita. Ia bisa dikatakan sebagai upaya mengaca diri di hadapan “cermin
besar” keteladanan Rasul dalam segala aspek kehidupannya yang tidak mesti
dilakukan secara zakelijk, harfiah, atau sepotong-sepotong, pemaknaan
terhadap keteladanan perilaku Nabi harus elastis, komprehensif, substansial,
dan kontekstual. Jadi, yang diambil dari pribadi Nabi adalah dimensi
keteladanan profetiknya yang berupa hikmah, kearifan, pesan, dan pelajaran
hidup; bukan sekadar physical performance yang artifisial dan karitatif.
Konsekuensinya, tidak semua perilaku Nabi, terutama yang bersifat fisik, harus
dijiplak mentah-mentah, tanpa mempertimbangkan kesesuaian konteksnya.[14]
Urgensi memunculkan kembali
kesadaran profetik dalam ruang keberagamaan
kita didasarkan pada sejumlah fenomena kehidupan yang makin menjauh dan
semangat ke-Nabian Muhammad,
seperti kekerasan, terorisme, kriminalitas, kemiskinan, kebodohan dan
pembodohan, ketidakadilan dan ketertindasan, despotisme dan keangkuhan,
hedonisme dan pemberhalaan duniawi, dan semacamnya. Betapa di sekeliling kita sudah dipenuhi orang-orang yang konon beragama
namun sama sekali tidak mampu memaknai keberagamaannya sendiri secara profetik.
Kecintaan dan komitmen mereka terhadap agama dan Nabi tidak perlu diragukan, namun itu semua
dibungkus fanatisme buta
yang justru sering
merugikan diri sendiri.[15]
Mengharapkan agama mampu
menjawab segala persoalan kontemporer mungkin ibarat “mimpi di siang bolong”, ketika persoalan
inheren dalam agama sendiri
belum terpecahkan. Logikanya, bagaimana
agama mampu membebaskan
umatnya dari
seluruh persoalan yang ada, jika ia sendiri belum terbebaskan. Dalam
kenyataannya, cara pembacaan umat beragama terhadap realitas agamanya masih
amat sederhana jika
tidak malah
“primitif”. Agama masih dibelenggu pandangan parokial berupa keterkungkungan teks
yang diciptakan
umatnya sendiri.[16]
Dengan demikian, kesadaran
profetik meniscayakan dua hal; membebaskan agama lebih
dahulu, lain mengonstruksi agama yang membebaskan. Musuh yang melekat dalam diri agama, berupa cara pembacaan terhadap agama yang sempit, dalam
banyak hal justru
lebih berbahaya ketimbang musuh di luar dirinya. Di sinilah
letak pentingnya
pembacaan agama yang profetik guna menghadapi berbagai persoalan kontemporer
yang makin rumit dan menantang.[17]
Obyek
dan Subyek Agama Profetik
Obyek sekaligus subyek
keberagamaan profetik adalah umat manusia (humankind) secara
keseluruhan, tanpa kecuali. Persoalannya justru pembacaan terhadap agama sering
menghalangi tercapainya misi profetik agama itu sendiri, yakni menjadikan
mereka humanum (manusia sejati). Umat manusia, melalui pembacaan
terhadap realitas agamanya, sering berbuat kerusakan yang merugikan manusia
lain. Pembacaan terhadap agamanya masih teosentris (manusia untuk agama), belum antroposentris (agama
untuk manusia). Cara pembacaan seperti ini tentu tidak bisa dikatakan sebagai
pembacaan yang terbebaskan.[18]
Pembacaan agama yang
antroposentris, seperti ditegaskan Esack (1997), membawa pada dua implikasi. Pertama, pembacaan
yang selaras dengan misi
dan kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Kedua, pembacaan harus dibentuk oleh pengalaman
dan aspirasi umat manusia secara keseluruhan, bukan sebagian atau segelintir
dari
mereka.[19]
Ide dasar umat manusia sebagai
sebuah kunci hermeneutik, dengan demikian, memunculkan dua persoalan teologis
klasik. Pertama, problem menyangkut the value of mankind sebagai pengukuran kebenaran. Jika
seseorang menerima pemahaman dan peran umat manusia sebagai ukuran kebenaran,
maka pertanyaannya, bisakah kita mengartikan bahwa kepentingan Tuhan itu
identik dengan kepentingan manusia, atau sebaliknya? Jawaban atas
pertanyaan ini,
tentu saja, mengikuti prinsip kebenaran relatif yang mengakui keberadaan multi kebenaran,
sebab kebenaran absolut hanya milik Tuhan.[20]
Kedua, persoalan kepemilikan
otentisitas pembacaan terhadap agama. Persoalan ini sering melahirkan perdebatan
teologis yang panjang tentang siapa yang lebih otentik dalam melakukan
pembacaan terhadap agamanya. Tidak seorang pun berhak memonopoli otentisitas
pembacaan agama. Orang yang menganggap diri paling legitimate dalam
melakukan pembacaan terhadap agamanya oleh Esack disebut telah melakukan hermeneutical
promiscuity, perzinaan hermeneutik.[21]
Dengan demikian, pembacaan
terhadap realitas teks agama (al-Qur’an dan Hadis) harus ditakar dari, dan berpulang pada,
nilai-nilai kemanusiaan manusia sebagai obyek sekaligus subyek beragama. Meski
mengusung kriteria kebenaran, upaya pembacaan itu harus diletakkan dalam kerangka Tauhid
(pengesaan Tuhan). Dengan cara demikian, umat Islam tidak perlu lagi terkungkung oleh teks-teks agama yang
membelenggu aspek kemanusiaannya. Dan, ini prasyarat bagi terciptanya
pembacaan profetik kedua; agama yang membebaskan.[22]
Misi profetik Nabi yang paling
utama adalah misi pembebasan, yakni membebaskan umat manusia dari segala bentuk
belenggu dan ketertindasan. Dengan begitu, Nabi adalah seorang pembebas bagi
umatnya. Dalam proses pembebasan ada proses transformasi, pemindahan, atau
perubahan dari kondisi yang tidak diinginkan
menuju kondisi yang diinginkan. Inilah yang telah dilakukan Nabi untuk
masyarakat Arab
pada awal-awal
masa keNabiannya.[23]
Dalam pandangan Engineer (1990), pembacaan
terhadap perjalanan (sirah) Muhammad akan menghasilkan tiga
jenis pembebasan. Pertama, pembebasan sosio-kultural. Sebelum Muhammad diutus Allah, struktur masyarakat Arab
dikenal amat feodal dan paternal yang selalu melahirkan fenomena penindasan.
Secara garis besar, mereka terbagi ke dalam dua kelas yang saling bertentangan;
kelas terhormat yang menindas (syarif/the oppressor) dan kelas budak dan
orang miskin yang tertindas (mustad’afin/the oppressed).[24]
Islam turun membawa pesan
egalitarianisme di semua bidang kehidupan.
Islam yang dibawa Muhammad
tidak lagi mengenal polarisasi
miskin-kaya, lemah-kuat, penindas-tertindas, penguasa-dikuasai, dan seterusnya.
Tidak ada lagi perbedaan manusia berdasar warna kulit, ras, suku, atau bangsa.
Yang membedakan mereka bukan hal-hal yang bersifat fisik, tetapi nilai keimanan
dan ketakwaannya.[25]
Konsep pembebasan yang
dicetuskan 14 abad lalu itu amat revolusioner, bukan saja bagi masyarakat Arab,
tetapi umat manusia secara keseluruhan yang cenderung bertindak rasis dan
diskriminatif terhadap sesama. Konsep ini amat relevan diangkat kembali ke
dalam konteks kehidupan mutakhir
yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang berawal dan arogansi rasial,
etnik, dan budaya. Artinya, dengan
beragama kita hilangkan kemiskinan, kebodohan, dan kezaliman, bukan sebaliknya.[26]
Kedua, keadilan ekonomi. Sejak
diturunkan, al-Qur’an amat menekankan pemerataan dan keadilan untuk semua, bukan
untuk sekelompok orang. Ia
amat menentang penumpukan
dan perputaran harta pada orang-orang kaya saja, sementara orang miskin selalu
tertindas secara struktural dan sistemik. Untuk keperluan ini, al-Qur’an juga menganjurkan
orang berpunya menafkahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Bagi mereka
yang tertindas, Allah
tidak saja telah menganjurkan untuk melawan segala bentuk penindasan dan
penjajahan, namun juga menjanjikan mereka kemenangan. Di negara kita,
keadilan masih menjadi
barang luxurious, terlebih bagi
kalangan lemah-tertindas. Keadilan hanya milik kaum berpunya. Hal ini
amat dirasakan
manakala kita
melihat kebijakan pembangunan yang selalu merugikan wong cilik.[27]
Keseluruhan
uraian yang dikemukakan di atas secara substantif mengindikasikan di tengah hiruk-pikuk
berbagai teori, paradigma dan pendekatan tentang kinerja pembangunan adalah
dibutuhkannya suatu paradigma alternatif sebagai pendekatan untuk merumuskan
indikator atau tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan bangsa. Sudah tentu pendekatan
dimaksud selain solutif juga bersifat holistik. Dalam hubungan inilah kehadiran
buku Kinerja Pembangunan dalam Perspektif Misi Profetik yang ditulis oleh Sdr.
Hermansyah, SEI., MSI. seorang penulis dan dosen muda yang produktif dan mempunyai
visi keberpihakan atas persoalan-persoalan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat menjadi urgen dan penting serta perlu diapresiasi.
Salah satu gagasan yang
merupakan benang merah dalam buku yang ada di tangan pembaca ini adalah bahwa
penulis berupaya mengintegrasikan teori -maqasid
al-Syari’ah[28]
yaitu suatu teori fundamental yang berasal dari dan dikonstruk oleh para juris
muslim sebagai suatu perspektif dalam melihat kinerja pembangunan. Dengan kata
lain, buku ini mencoba menawarkan cara pandang alternatif dalam melihat
persoalan kinerja pembangunan. Jika teori maqasid
al-Syari’ah ini diterjemahkan ke Bahasa Indonesia secara substantif dapat
juga diartikan sebagai ajaran profetik.
Tanpa ada keinginan untuk
mengarahkan pikiran pembaca atas buku ini, kepada pembaca yang budiman
dipersilahkan membaca langsung buku ini secara kritis. Dengan harapan dengan
terbitnya buku ini akan memberi sedikit semangat dan optimisme dalam menyikapi
kinerja pembangunan di Indonesia. Selamat membaca.
[1] Indra
Tranggono, “Semakin Kehilangan Indonesia” (artikel opini) Harian Kompas dikutip http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/04/05441959/semakin.kehilangan.indonesia
diunduh 4 Maret 2010.
[2]Ibid.
[3]Ibid.
[4]Ibid.
Baca juga
Jeery Mander,
Debby Barker dan David Corten, Globalisasi
Membantu Orang Miskin?, Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan, (Yogyakarta: Cinderalas, 2003),
hlm. 4-5.
[5]Ibid.
[6]Ibid.
[7]Ibid.
dan Jeery Mander, Debby Barker dan David Corten, Globalisasi Membantu Orang
Miskin?, Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan, (Yogyakarta: Cinderalas, 2003),
hlm. 4-5.
[8]Ibid.
[10]Ibid.
[12]Ibid.
[13]Ibid.
dan Jeery Mander, Debby Barker dan David Corten, Globalisasi Membantu Orang
Miskin?, Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan, (Yogyakarta: Cinderalas, 2003),
hlm. 4-5.
[14] Masdar Hilmy, Islam Profetik Substansiasi Nilai-Nilai
Agama dalam Ruang Publik (Yogyakarta: Impulse Kanisius,2008),hlm.244-245.
[16] Ibid, hlm.245
[17] Ibid, hlm.247, baca juga Zuly Qodir, Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2009), hlm.279-280 dan Jeery Mander,
Debby Barker dan David Corten, Globalisasi
Membantu Orang Miskin?, Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan, (Yogyakarta: Cinderalas, 2003),
hlm. 4-5.
[19] Ibid, hlm.248 dan baca Parsudi Suparlan, “Pendahuluan” dalam Parsudi
Suparlan (Penyunting), Kemiskinan di
Perkotaan Bacaan untuk Antropologi Perkotaan (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1995), hlm.x
[20] Ibid. dan baca
juga Zuly Qodir, Gerakan Sosial Islam:
Manifesto Kaum Beriman (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm.279-280
[21] Ibid, hlm.248
[23] Ibid, hlm.248
[25]Ibid, hlm.249, baca Q.S.
48: 13. dan baca
juga Zuly Qodir, Gerakan Sosial Islam:
Manifesto Kaum Beriman (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm.279-280.
[28] Sarjana
muslim kontemporer yang membahas dan mengintegrasikan teori ini dengan teori-teori ilmu sosial
kontemporer antara lain adalah Jasser Auda,
Maqasid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach,
(London: IIIT,2008).