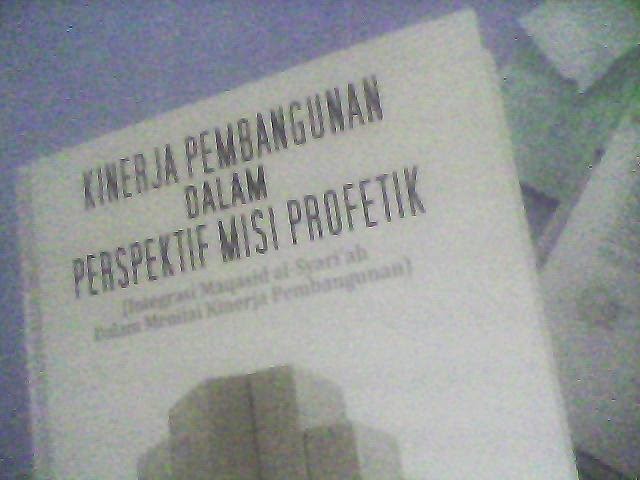Tulisan ini
telah terbit pada Jurnal Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah
Program
Studi Ekonomi Syariah STAI An Najah Surabaya
Volume 1
Nomor 1 Maret 2014. Hal. 27-41. ISSN:
2730-02
Abstract
The entire scientific
disciplines must be built upon a foundation of epistemological. Epistemology is the branch of philosophy that discusses in depth the whole process of obtaining knowledge. In this
paper will describe how the
flow of positivism influence on Islamic economic
studies that have been developed. This study will start from
the description of several streams
in the philosophy of science, positivism influence on
Islamic economics and the future course
of action in an effort that led
to a paradigmatic change in addressing the practical teachings of the Islamic economic system.
Keywords: epistemology, positivism, Islamic economics
Abstrak
Seluruh disiplin ilmu
pengetahuan ilmiah mesti dibangun atas landasan epistemologis. Epistemologi
merupakan cabang filsafat yang membahas secara mendalam segenap proses untuk
memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana
pengaruh aliran positivisme terhadap kajian ekonomi Islam yang selama ini
berkembang. Kajian ini akan dimulai dari uraian atas beberapa aliran dalam
filsafat ilmu, pengaruh positivisme
terhadap ekonomi islam dan arah tindakan masa depan dalam usaha yang berujung pada perubahan paradigmatik
dalam menyikapi ajaran praktis sistem ekonomi Islam.
Kata
kunci: Epistemologi, positivisme, ekonomi Islam
A.
Pendahuluan
Seluruh
disiplin ilmu pengetahuan ilmiah mestilah dibangun atas landasan epistemologis.
Hal ini berarti bahwa sebuah ilmu, akan dapat dijadikan sebagai suatu disiplin
ilmu jika ia telah memenuhi syarat-syarat ilmiah (scientific). Salah satu syarat dalam kajian filsafat adalah
epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas secara
mendalam segenap proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam studi ini
dicari rumusan-rumusan untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan mendasar
menyangkut ilmu pengetahuan.[1]
Epistemologi
pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang terkait dengan
asal-usul (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut
(metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut. Ilmu ekonomi Islam
(Islamic economics) sebagai sebuah disiplin ilmu, jelas memiliki landasan
epistemologis. Membahas epistemologi ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul
(sumber) ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah.
Pengertian epistemologi Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata Yunani
episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori,
uraian atau alasan. Jadi epistemology berarti studi atau penelitian tentang
pengetahuan.
Secara
terminology, epistemology is the branch
of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity
of knowledge. Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang
filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula
pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.[2]
Epistemologi
ini pada umumnya disebut filsafat pengetahuan. Dalam bahasa Inggris
dipergunakan istilah theory of knowledge.
Istilah epistemologi untuk pertama kalinya muncul dan digunakan oleh JF Ferrier
pada tahun 1854 Dalam pengertian terminologis ini, Miska Muhammad Amin,
mengatakan bahwa epistemologi terkait dengan masalah-masalah yang meliputi: a)
filsafat, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakekat dan
kebenaran pengetahuan, b) metoda, sebagai metoda, bertujuan mengantar manusia
untuk memperoleh pengetahuan, dan c) sistem, sebagai suatu sistem bertujuan
memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri.[3]
Jika
ontology merupakan pengkajian mengenai teori yang sudah ada, maka epistemology
merupakan upaya untuk menyusun teori yang baru, dan jika kita masih berkehendak
untuk mengislamkan ilmu pengetahuan, maka prosesontologilah yang membantunya,
atau dengan memperbaiki ilmu pengetahuan dari awal hingga akhir. Namun jika
yang dilakukan adalah mengislamkan ilmu pengetahuan terhadap ilmu yang sudah
ada maka kita cukup untuk menentukan yang baik dan layak menurut Islam atau
tidak.[4]
Dengan
demikian dalam pembahasan kali ini, setelah sedikit di atas diuraikan
menyangkut epistemology, maka disini kita akan melihat bagaimana pengaruh
aliran positivism terhadap kajian ekonomi Islam yang selama ini berkembang.
B.
Aliran
Filsafat Ilmu
Dalam
tradisi keilmuan Barat setidaknya ada 3 aliran besar filsafat ilmu yang sangat
berpengaruh, yaitu, empirisme,[5]
rasionalisme[6]
dan positivisme.[7]
Di era modern empirisme dikembangkan pada zaman Renaisans dengan tokoh utamanya
Francis Bacon (1561-1626). Filsafat Bacon ini mempunyai peran penting dalam
metode induksi dan sistematisasi prosedur ilmiah, bersifat praktis dan empiris.
Aliran ini memberi kekuasaan pada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah
secara empiris.
Sedangkan aliran
rasionalisme menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan.
Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia menurut aliran
ini yakni memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Bagi
aliran ini kekeliruan pada aliran empirisme, adalah kelemahan alat indera yang
terbatas. Kelemahan itu dapat dikoreksi seandainya akal digunakan. Rasionalisme
tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan, pengalaman
indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang
menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi untuk sampainya manusia kepada
kebenaran diperlukan akal Laporan indera menurut rasionalisme merupakan bahan
yang belum jelas, belum sistimatis atau masih chaos. Bahan pengalaman inderawi harus dipertimbangkan oleh akal.
Akal mengatur dan mensistimatoisasi pengalaman itu secara logis sehingga
terbentuklah pengetahuan.
Aliran
positivisme ini dikemukankan oleh August Comte (1798-1857). Sebagai sebuah
metode ia berpangkal dari gejala yang faktual, yang positif. Ia
mengenyampingkan berbagai persoalan di luar fakta. Karena itu Ia menolak
metafisika dan agama. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang
tampak dan segala gejala. Dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan, positivisme
terbatas pada gejala-gejala empiris saja.[8]
Sementara
itu, terdapat beberapa perbedaan antara Filsafat Pengetahuan Islam
(Epistemologi Islam) dengan epistemologi pada umumnya. Yang pada garis
besarnya, perbedaan itu terletak pada masalah yang bersangkutan dengan sumber
pengetahuan, dalam Islam sumber pengetahuqn, yakni wahyu dan ilham. Sedangkan
masalah kebenaran epistemologi pada umumnya (Barat) menganggap kebenaran hanya
berpusat pada manusia sebagai makhluk mandiri yang menentukan kebenaran.
Epistemologi Islam membicarakan pandangan para pemikir Islam tentang
pengetahuan, dimana manusia tidak lain hanya sebagai khalifah Allah, sebagai
makhluk pencari kebenaran. Manusia tergantung kepada Allah sebagai pemberi
kebenaran. Misalnya menurut pandangan Syed Nawab Haider Naqvi, ada empat
aksioma etika yang mempengaruhi ilmu ekonomi Islam, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan
dan tanggung jawab.[9]
Pengaruh asumsi dan pandangan yang dipakai dalam penelitian ekonomi Islam harus
terbukti faktual, karena berbagai dimensi manusia adalah kenyataan faktual.
Epistemologi
di dalam Islam tidak berpusat kepada manusia yang menganggap manusia sendiri
sebagai makhluk mandiri dan menentukan segala-galanya, melainkan berpusat
kepada Allah, sehingga berhasil atau tidaknya tergantung setiap usaha manusia,
kepada iradat Allah. Epistemologi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai
subjek untuk membicarakan filsafat pengetahuan, maka di satu pihak epistemologi
Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber pengetahuan dan
sumber segala kebenaran. Di lain pihak, epistemologi Islam berpusat pula pada
manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan (kebenaran). Di
sini manusia berfungsi subyek yang mencari kebenaran. Manusia sebagai khalifah
Allah berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan sekaligus memberi
interpretasinya. Dalam Islam, manusia memiliki pengetahuan, dan mencari
pengetahuan itu sendiri sebagai suatu kemuliaan.
C.
Pengaruh
Positivisme Terhadap Ekonomi Islam
Penelitian-penelitian
dalam bidang sosial, terutama bidang ekonomi selama ini lebih banyak
menggunakan pendekatan positivistik kuantitatif.[10]
Sebagian besar peneliti ekonomi beranggapan bahwa pendekatan ini dianggap lebih
canggih, lebih baik dibandingkan dengan pendekatan kualitatif. Sehingga mereka
beranggapan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak obyektif dan
diragukan kebenarannya.
Adalah Auguste
Comte pihak yang bertanggungjawab di sini. Comte memberi kita visi
tentang idealitas keilmuwan, tentang ilusi keagungan penerapan prosedur
eksperimen dalam penyelidikan sosial, tentang pentingnya “memajukan” masyarakat
untuk lepas dari belenggu pemikiran teologis serta metafisis menuju masyarakat
positif yang “ilmiah”. Ironisnya, pandangan ini telah menjadi satu-satunya
norma ilmiah -sebuah norma yang tanpa pernah dipertanyakan, telah menjadi
tradisi untuk mengklaim diri paling ilmiah dan yang lain sebagai tidak ilmiah.
Atas visi yang keblalasan
tersebut, cabang ilmu yang pada awalnya murni logika, misalnya ekonomi dan ilmu
sosial, telah ikut-ikutan mengadopsi visi filosofis Comte. Setiap pernyataan
atau proposisi, menurut klaim positivis, tidak akan pernah dapat dibuktikan
kebenarannya apabila tidak melalui prosedur eksperimen yang empiris.
Positivisme
dalam ranah epistemologi mensyaratkan bahwa ilmu tindakan manusia harus
menerapkan prosedur yang sama seperti yang dilakukan dalam ilmu alam. Bagi Comte,
masyarakat positif dikatakan dapat berhasil secara ilmiah ketika para ilmuwan
telah meninggalkan sesuatu yang a
priori. Metode yang paling tepat, menurut Comte, ialah pencarian
hukum-hukum ilmu sosial melalui eksperimen. Baginya hanya metode eksperimenlah
yang dapat mendekatkan kita pada objek observasional. Prasyarat kedua, menurut
Comte, dalam menuju masyarakat positif adalah dengan menggantikan pendidikan
teologi, metafisika dan sastra dengan pendidikan filsafat positif. Comte
mengartikan pendidikan positif sebagai ajaran yang mendidik masyarakat agar
persepsinya dapat sesuai dengan objek factual -dengan kata lain gagasan-gagasan
abstrak serta fiksi seharusnya ditiadakan. Dengan demikian ajaran-ajaran
teologis, metafisik dan sastra merupakan ajaran yang tidak sesuai dengan objek
faktual. Jadi keberadaan mereka perlu digantikan dengan ilmu-ilmu alamiah,[11]
atau dengan kata lain hal-hal yang bukan fakta non-metafisis tidak bermakna
apa-apa. Masyarakat ilmiah dalam menelaah ilmu sedapat mungkin harus mampu mengombinasikan
beberapa sudut pandang cabang ilmu. Bagi Comte kombinasi dalam berperspektif
sangatlah penting. Akhirnya Comte beranggapan bahwa untuk mengatasi krisis
masyarakat, hanya pandangan filsafat positivisme-lah yang mampu mengatasi
krisis sosial. Dengan filsafat positif anarkisme intelektual, yang biasanya
melewati jalan rumit untuk diperdebatkan dalam mencari kebenaran, harus
dilenyapkan.[12]
Tujuan utama
ilmuwan yang berpandangan positivis ialah mencari keteraturan dari sebuah
fenomena dengan menggunakan statistik. Alasannya adalah hanya dengan statistik
yang dapat menguji fenomena sosial layaknya pengujian ilmu alam.[13]
Bagi kaum positivis, sebuah teori yang tidak dapat diverifikasi atau
difalsifikasi oleh pengalaman empiris -yang biasanya melalui data statistic-
tidak akan dapat dianggap sahih. Bahkan sebuah pernyataan tanpa dukungan
analisa statistik tidak bisa disebut “ilmiah”. Tegasnya, positivisme berpandangan bahwa ilmu merupakan
satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sajalah yang mungkin
menjadi objek pengetahuan. Apa yang ada dibalik fakta ditolak.[14]
Dengan
prosedur induktif, para ahli ilmu sosial berharap akan menemukan hukum-hukum
sosial seperti layaknya hukum fisika, sehingga penggunaan prosedur yang kaku,
dengan berbagai varian metodologi kuantitatifnya, telah berhasil membuat
sebagian besar akademisi kita sudah merasa “paling ilmiah”. Doktrin tersebut,
tidak dapat dipungkiri, menyiratkan pandangan yang kacau. Statistik tidak
menggambarkan keteraturan. Dia hanya sebuah kumpulan kejadian-kejadian yang
beragam, yang kemudian direduksikan menjadi angka-angka. Dengan demikian,
kejadian-kejadian tersebut bukanlah sebuah variabel yang dapat dipastikan akan
mempengaruhi kejadian di masa depan. Fenomena yang telah direduksi ke dalam angka
statistik adalah fenomena masa lalu dan merupakan sejarah masa lalu, sehingga
sangat musykil untuk membangun teori dari data statistik.[15]
Dalam bidang
ekonomi misalnya dapat diambil contoh bahwa tiga
ekonom yang tulisannya sebagian besar mencerminkan pengaruh dari positivisme
adalah T.W. Hutchison, Paul Samuelson dan Milton Friedman. Pada tahun 1938 buku
yang berjudul: The Significance and Basic
Postulates of Economic Theory yang ditulis oleh Hutchison menyerang pendapat
tentang pemilihan berdasarkan logika murni, suatu doktrin yang dipertahankan
oleh Lionel Robinson enam tahun sebelumnya dalam bukunya The Nature and Significance of Economics
Science. Lebih dari 50 tahun Hutchinson[16]
melanjutkan kritikannnya terhadap ilmu
ekonomi yang berdasarkan pada landasan
yang tidak dapat diuji. Target kritikan tersebut mulai dari apriori yang dikembangkan oleh Ludwig von Mises sampai pada
penggunaan model matematika tentang
teori keseimbangan umum. Pada bab pendahuluan dalam bukunya yang berjudul: Foundation of Economic Analysis, Samuelson mengambil dari karya ahli fisika, Percy Bridgman, mendesak para ekonom
mencari teorema yang secara operasional
bermanfaat. Pendekatan revealed preference dari
Samuelson pada teori permintaan telah
menempatkan teori konsumen pada basis yang dapat diobservasi. Akhirnya, Friedman[17]
pada tahun 1953 dalam bukunya yang berjudul: The Methodology of Positive Economics memberikan
argumentasi yang populer yaitu realitas asumsi suatu teori tidak relevan, apa
yang diperhitungkan dalam pengkajian suatu teori adalah cukup untuk membuat prediksi dan sederhana. Melalui ciri khasnya,
Friedman diakui sebagai pelopor penggunaan metodologi instrumental (yang
banyak dipengaruhi oleh pandangan pragmatis Amerika dari pada positivisme),
metodologi ini akhirnya disinonimkan dengan positivisme pada periode tahun 1950
sampai tahun 1960[18]
Dengan
demikian, ilmu ekonomi telah mengklaim bahwa ia telah mampu menemukan
“hukum-hukum alam” yang mengatur aktivitas perekonomian dan distribusi
produk-produk sosial, serta memperlihatkan bahwa campur tangan terhadap
hukum-hukum ini akan menyebabkan terjadinya “chaos” dan “disequilibrium”.
Ilmu ekonomi dengan demikian merupakan sintesa eklektik dari
proporsisi-proporsisi moral tertentu yang berasal dari ajaran-ajaran Berkeley,
David Hume, Hegel dan Bentham. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu
ekonomi Islam juga adalah cabang dari ekonomi neoklasik. Ia mencari fungsi
utilitas individu pada basisi interpretasi Islam dari filsafat utilitarian,
metodologinya juga disusun dari kerangka analisis makro-mikro yang dikembangkan
Stigler, Friedman, Keynes dan Klein. Ekonomi Islam dengan demikian membangun
suatu gambaran ideal mengenai suatu ekonomi, dimana individu-individu,
perusahaan-perusahaan dan pemerintah harus menjadi “Islamis”.[19]
Tidak
terkecuali dalam upaya pengembangan metodologi ekonomi Islam, ekonom Muslim di
Indonesia dalam memformulasikan metodologi ekonomi Islam secara massif
menggunakan logika positivisme. Seakan-akan nilai-nilai ekonomi dalam Islam
menjadi tidak ilmiah bila tidak didukung oleh pendekatan kuantitatif-nomotetik
-sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Memang ada nilai plus dari usaha
penggabungan itu. Namun hal ini seakan dipaksakan dan sisi gelapnya adalah,
para ekonom Muslim tersebut dalam perumusannya malah masuk pada ranah yang
tidak bisa disentuh oleh logika positivisme,[20]
maupun ilmu sosial, -sebagaimana hal ini telah banyak mendapat kritik
sebelumnya. Namun demikian, penekanan pada logika positivisme ini bisa saja
dilakukan, dengan catatan terdapat pengelompokan dalam lapangan kajian ekonomi
Islam misalnya menyangkut mana yang dapat diukur dan dikembangkan dengan
menggunakan logika positivism semisal dengan teori-teori matematik, fisika,
statistic dan ekonometrik, dan mana yang tidak, misalnya menyangkut
nilai-nilai.
Misalnya
dalam hal mencapai falah (kebahagiaan
dunia dan akhirat) yang diarahkan untuk mencukupi lima jenis (Maqasid al‑Syari'ah: agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta) kebutuhan guna menghasilkan mashlahah
(kemaslahatan) yang diukur dengan: (1) mashlahah
yang lebih besar lebih disukai daripada yang lebih sedikit; (2) mashlahah diupayakan terus meningkat
sepanjang waktu, disamping berkah atau barakah
(keberuntungan yang bersifat spiritual). Pengartian seperti ini, sebenarnya
sah-sah saja, akan tetapi hal ini akan menjadi pertanyaan manakala mengukur dan
mereduksi kedua indikator ini hanya berdasar pada logika positivis dan dapat
diuji saja, tanpa mempertimbangkan kekayaan khazanah teori dan metode pemikiran
Islam. Pertanyaannya selanjutnya yang muncul, adalah reduksi pemaknaan yang
ditimbulkannya, karena hal ini juga menyangkut penilaian. Padahal untuk hal ini
Chapra[21]
telah mewanti-wanti bahwa meskipun pencarian hubungan antara sebab akibat
adalah penting guna memungkinkan kita untuk menjelaskan dan memprediksikan,
namun terdapat rambu-rambu yang harus diingat yakni, manusia sangat tergantung
pada keterbatasan-keterbatasan dan tidak dapat menjelaskan atau memperidiksikan
segala sesuatu. Kita mungkin hanya mengetahui satu “bagian hubungan yang diarahkan
lampu senter ditengah hutan yang gelap”. Dan terdapat begitu banyak fenomena
didalam kehidupan sosial, ekonomi dan keagamaan yang tidak dapat kita jelaskan
jika kita bersikeras mengenai analisis empiris. Kedua, kaum Muslim secara
intrinsik meyakini jauh kemungkinan terjadinya konflik antara pengamatan
empiris dan proposisi yang termaktub dalam nash.
Setiap konflik yang nyata mungkin berasal dari kesalahan penafsiran proposisi
atau bukti, atau implementasi yang tidak efektif, atau kesalahan pengamatan.
Misalnya
dalam pengukuran mashlahah bagi konsumen yakni dengan ukuran semakin tinggi
frekuensi kegiatan yang ber-mashlahah,
maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi dan
mashlahah yang diterima tersebut merupakan perkalian antara pahala dan
frekuensi kegiatan tersebut. Demikian halnya dengan berkah yang diterima oleh
konsumen tergantung pada frekuensi konsumsinya, yakni semakin banyak
barang/jasa halal-tayyib yang
dikonsumsi, maka akan semakin besar pula berkah yang akan diterima. Selain itu,
berkah bagi konsumen ini juga akan berhubungan secara langsung dengan besarnya
manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsi[22]
Jika acuan
hukum yang digunakan adalah maslahat manfaat, pertanyaan yang akan segera
muncul adalah, bagaimana "maslahat, atau manfat" itu dapat
didefinisikan, dan siapa punya otoritas untuk mendefinisikannya. Tidak syak
lagi, pertanyaan ini sangat penting dan menentukan. Gagal menjawab pertanyaan
ini, akan kembali berimplikasi untuk memperkatakan bahwa maslahat‑manfaat
sebagai tujuan syari’at (hukum), telah dijadikan tujuan bagi dirinya sendiri.
Maslahat manfaat hanya jargon kosong belaka.[23]
Disamping
itu, jika konsep-konsep etika religious dalam Islam seperti halnya berkah,
pahala dan dosa dikuantivikasi bagaimana kita akan menentukan secara
kuantitatif seberapa besar perolehan yang dicapai, lalu bagaimana pula
menjelaskan analisis konsep-konsep pokok yang mendasari etika religious
tersebut?[24]
Padahal pencapaian maksimum dalam konsep-konsep etika riligius tidak berarti selamanya
dianggap sebagai sesuatu yang patut dan layak karena “….boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu baik bagi kamu, padahal tidak
demikian disisi Allah…..” dan menurut hadis bahwa “……yang baik dan bermanfaat adalah yang sedikit dan secara istiqomah dilakukan…..”
Penafsiran
reduktif inilah yang beranggapan bahwa pemaknaan-pemaknaan etika religius dapat
dipotong sekecil-kecilnya hingga hingga menjadi atom, yang pada akhirnya
kemaslahatan dan keberkahan akan dilihat dari hal-hal yang dapat diindera,
selanjutnya etika dan religius keberagamaan akan dinilai dari jenggot dan
busana, sehingga “muslim yang baik” “ekonomi yang berkah dan maslahat” bukan
saja berkewajiban memelihara jenggot, tetapi juga bentuk dan panjangnya harus
disesuaikan dengan Nabi! Nilai-nilai etika religious direduksi menjadi tanda
dan symbol, semangat perilakunya, dimensi moral dan etis, keberkahan dan
kemaslahatan dan prinsip-prinsip umum yang dianjurkan, semua terserap kedalam
logika reduksi yang absurd.[25]
Karena
Berdasarkan cakupan dan implikasinya, ulama ushul fiqih membagi maslahat menjadi dua, yaitu[26]
al-maslahah al-’ammah dan al-maslahah al-khossoh. Yang pertama
adalah maslahat yang berimplikasi pada orang banyak, dalam hal ini,
otoritas yang berhak memberikan penilaian yang dan sekaligus menerima
manfaatnya tidak lain adalah orang banyak yang bersangkutan, melalui mekanisme syura
untuk mencapai kesepakatan (ijma'). Jadi, apa yang disepakati oleh
orang banyak dari proses pendefinisian maslahat melalui musyawarah itulah
manfaat yang sebenarnya. Kesepakatan orang banyak, di mana kita merupakan
bagian daripadanya, itulah manfaat tertinggi yang mengikat. Sementara yang kedua berakibat hanya pada
kebaikan pribadi atau golongan saja. Dalam maslahat kategori ini, karena
sifatnya yang sangat subyektif, yang berhak menentukan dan sekaligus penerima
manfaatnya tentu saja adalah pribadi bersangkutan. Tidak ada kekuatan kolektif
mana pun yang berhak menentukan apa yang secara personal‑subyektif dianggap
maslahat oleh seseorang.
Kalau
dipertanyakan kedudukan hukum atau ketentuan‑ketentuan legal‑normatif yang
ditawarkan oleh wahyu (teks al-Quran atau hadis), kedudukannya adalah sebagai
material yang ‑juga dengan logika maslahat sosial yang obyektif, bukan dengan
logika kekuatan atau kepercayaan yang subyektif‑ masih harus dibawa untuk
ditentukan statusnya ke dalam lembaga permusyawaratan. Apabila kita berhasil
membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfungsi sebagai
hukum yang secara formal‑positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal
memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas
pada orang‑orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh
hanya bersifat moral‑subyektif, tidak bisa sekaligus formal‑obyektif.
Al-Syatibi, berdasarkan segi kualitas dan
kepentingan kemaslahatan, membagi
mashlahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu al-daruriyat, al-hajiyat dan al-tahsiniyat. Mashlahat menurutnya, tidak jauh berbeda dengan
apa yang dirumuskan oleh al-Ghazali, yaitu
memelihara lima hal pokok berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala
bentuk upaya untuk memelihara kelima macam ini dipandang sebagai maslahat, dan merusaknya adalah mafsadat.[27]
Daruriyat adalah
kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai
syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik dunia maupun akhirat.
Dengan kata lain jika daruriyat ini
tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Daruriyat ini mencakup pemeliharaan lima unsure pokok dalam
kehidupan, yakni yakni agama/keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta. Contoh
untuk penunaian aspek ini misalnya menunaikan rukun Islam, pelaksanaan
kehidupan manusiawi serta larangan mencuri yang masing-masing merupakan salah
satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap
eksistensi harta[28]
Di sisi lain, hajiyyat merupakan
segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup manusia bahagian
dan sejahtera dunia dan akhirat, serta terhindar dari berbagai kesengsaraan.
Jika kebutuhan ini tidak tertunaikan, manusia akan mengalami kesulitan (masyaqqah) meski tidak sampai
menyebabkan kepunahan[29] Tingkatan terakhir adalah tahsiniyyat
yakni berupa kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan
kesejahteraan hidup manuisa. Jika kemaslahatan tahsiniyyat ini tidak
dipenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat
meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup. Contoh jenis maqashid
ini adalah antara lain mencakup
kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi
dan hasil pekerjaan.
Sebenarnya
maslahah atau ‑dalam ungkapan yang lebih operasional‑ adalah "keadilan
sosial” dapat kita artikan sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan
dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Disini ditegaskan bahwa ia harus
sesuai dengan tujuan-tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan
manusia. Hal ini disebabkan karena tujuan-tujuan manusia tidak selamanya sesuai
dengan tujuan syarak, pendapat ini misalnya diuraikan oleh al-Ghazali[30]
Ungkapan
al-Ghazali ini memberikan isyarat bahwa ada dua bentuk kemaslahatan, yaitu
kemasalahatan menurut manusia dan kemaslahatan menurut syari’at. Kemasalahatan
menurut manusia ukurannya adalah akal dan perasaan, sedangkan kemaslahatan menurut
syari’at ukuranya
adalah wahyu. Memelihara
tujuan syari’at yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara
harta. Dengan kata lain, upaya menambil manfaat atau menolak kemudaratan yang
semata-mata demi kepentingan duniawi manusia tanpa mempertimbangkan kesesuaian
dengan tujuan syara’, apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut
segbagai al-maslahah, tetapi sebaliknya itu merupakan mafsadah.
Kemudian
dari formulasi di atas, jika berkah yang diterima oleh konsumen tergantung pada
frekuensi konsumsinya, yakni semakin banyak barang/jasa halal-tayyib yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula berkah
yang akan diterima maka hal ini akan berarti mafsadah bagi mereka yang
kekurangan yakni para fakir dan miskin, karena jangankan untuk tingkat
frekuensi yang tinggi, jenis produk dengan label halal pun akan sangat sulit
bagi mereka untuk dikonsumsi. Untuk itulah disini patut untuk di cermati bahwa
maslahat juga perlu
dipandang dari sisi keumumannya dan kekhususannya. Bisa saja dianggap
maslahat bagi orang-orang elit dan menjadi mafsadat bagi orang-orang awam.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa definisi
maslahat,[31]
sangat beragam dan dapat mengarah pada adanya kontradiksi antar kemaslahatan.
Ada kemaslahatan yang kita yakini dan anggap benar, namun dalam perjalanannya
justru menyingkirkan kemaslahatan lain, atau malah terjerumus dalam mafsadat.
Dalam kondisi inilah semua orang harus meletakkan ragam pendapat tersebut pada
porsinya masing-masing, kemudian dianalisis dari segala sudut pandang. Baru
akan diketahui maslahat
yang harus didahulukan dan maslahat yang diakhirkan. Proses inilah yang akan mengantarkan pada
maslahat yang benar.
Sebenarnya,
konsep mashlahah yang dibingkai oleh
teori maqasid al‑Syari'ah dapat
dijadikan sebagai metode dalam membaca berbagai fenomena perekonomian, tanpa
harus terjebak dalam logika positivistik dan bersikeras dengan melakukan
degradasi konsep yakni misalnya dengan mengaitkannya dengan tujuan yang
didampingi oleh tujuan sekunder dan tujuan tertier berdasarkan estetika dan
kemampuan lokal. Misalnya dalam hal menyelamatkan harta, Islam mengharuskan
orang mengetahui ilmu bela harta. Demi kelancaran proses tujuan primer ini,
dibutuhkan fasilitas bela harta, misalnya bank sebagai tempat penyimpanan uang.
Tanpa bank, penyimpanan uang tetap bisa dilakukan misalnya di bawah tilam, di
dalam celengan atau dikubur disuatu tempat. Namun demikian, kehadiran lembaga
keuangan dalam hal ini perbankan syariah sangat membantu pemilik dari banyak
kemungkinan yang akan mengganggu, baik itu perampok, maling atau bahaya lain
semisal kebakaran. Pada tahap tertier, pilihan untuk menentukan bank syariah
mana diserahkan kepada kemantapan dan kemampuan lokal. Mungkin sebagian orang
akan memilih bank syariah milik pemerintah, dengan alas an keamana yang lebih
terjamin. Dan mungkin sebagian lainnya akan menjatuhkan pilihan pada bank
syariah yang lain, dengan alasan gengsi, jarak yang jauh atau yang lain.
Sedangkan pengharusan penempatan uang di tempat tertentu akan menimbulkan
mafsadat yakni terbunuhnya spesialisasi dan lapangan kerja perbankan. Jika
dalam melaksanakan kewajiban menyelamatkan, yang disertai dengan niat yang
ikhlas demi ketaatan kepada allah, ini orang meninggal dunia karena
mempertahankan hartanya dari serangan orang lain, maka ia adalah seorang
syuhada’.[32]
Penempatan konsep mashlahah
sebagai metode ini, juga didasarkan atas prinsip kepasangan, sehingga dikenal
prinsip tidak ada maslahah (kebaikan, rahmat, manfaat) tanpa mafsadat
(keburukan, fitnah), sebaliknya tidak ada mafsadat tanpa mashlahah. Prinsip ini
berasumsi bahwa tujuan (hukum) Islam (dalam bingkai mashlahah) disamping
bersifat ilahi juga wad’I (manusiawi), absolute tetapi juga relative, universal
juga sekaligus local, abadi sekaligus sementara, harfiah sekaligus maknawiyah.[33]
Disinilah dapat dimengerti mengapa (hukum) Islam bergerak antara lima dasar
yakni halal, haram, mubah, makruh dan sunnah karena implikasi membawa kita
untuk lebih memahami konsep-konsep tersebut secara
kualitatif-multikulturalis-profetik.
Ini bukan
berarti metode positivistik-degradatif harus ditinggalkan. Yang dibutuhkan
adalah kemampuan untuk membuka diri terhadap berbagai disiplin ilmu sosial. Hal
ini perlu dilakukan, agar pemahaman terhadap ilmu ekonomi Islam benar-benar
sesuai dengan konteksnya, baik konteks sejarah pemikiran Islam masa lalau
maupun kondisi perekonomian umat Islam kontemporer. Pengintegrasian berbagai
macam keilmuan (eksak maupun sosial) dalam kajian ekonomi Islam, jika dilakukan
dengans serius dan tepat, justru akan menciptakan suatu sinergi ilmiah yang
akan berguna untuk memecahkan problem metodologi dan pengembangan system
ekonomi Islam, tetapi dengan tetap tidak keluar dari kaidah rancang bangun
keilmuan yang Islami.
Alternative
lain terhadap pendekatan realis‑positivis ini yakni suatu pendekatan yang
lebih memadai untuk memahami agama adalah pendekatan transformatif; suatu
pendekatan yang memandang perubahan (change) sebagai sarana untuk
mencapai cita kebaikan kualitatif yang bermuara pada cita kebaikan mutlak ‑dalam
bahasa agama disebut Tuhan. Pendekatan ini diusulkan bukan karena agama (yang
mana saja) tidak pernah datang sekadar untuk membenarkan apa yang tengah
menjadi "nyata" dalam kehidupan manusia, melainkan ‑sebagaimana
terbukti dalam sejarah‑ agama selalu datang dengan gugatan‑gugatan yang
mendasar mengenai makna dari "apa yang tengah menjadi kenyataan"
itu. Kalau tidak, kalau agama datang dengan semangat membenarkan apa yang ada
seperti yang dipersepsikan oleh kaum realis, agama memang hanya berfungsi
sebagai sistem legitimasi yang tidak memiliki prinsipnya sendiri dan
jika benar begitu, kisah kesulitan setiap rasul dalam berhadapan dengan
"unsur pembentuk dan pembela realitas" (yakni kelompok elit penguasa)
menjadi aneh dan sungguh tidak perlu. Karenanya pendekatan
transformatif mengemuka sebagai suatu pendekatan alternatif dari
pendekatan realis-positivistik. Esensi kemaslahatan dalam syarak
bukan hanya berfungsi sekadar sistem legitimasi melainkan sebagai
pemenuhan terhadap sesuatu yang mendasar mengenai makna dari apa
yang tengah terjadi.[34]
Jalan lain
yang ditawarkan Sardar dalam menuju apresiasi yang segar dan kontemporer
terhadap Islam mensyaratkan keberanian untuk menghadapi bencana metafisik dan
beralih dari reduksi menuju sintesis. Hal ini mengharuskan umat Islam untuk
berani menghadapi gagasan absurd dan dengan gerakan sintesis mereka dituntut
untuk bergerak maju menuju makna dan pesan utama Islam -sebagai cara pandang
moral dan etis dan cara membentuk dunia, sebagai ranah budaya kewargaan-
sebagai sebuah dukungan partisipatoris dan sebagai sistem pengetahuan dan
perilaku serta tindakan yang holistik.[35]
Disamping
itu, pemahaman syariat secara kontekstual dengan memperhatiakn keseluruhan
proses yang terkait dengan perwujudan mashlahah juga merupakan salah satu dari
rangkaian ijtihad. Sedangkan untuk ini, diperlukan kemampuan membaca berbagai
perkembangan soaial disamping perwujudan untuk mencapai mashlahah
setinggi-tingginya. Kemampuan demikian memang tidak perlu dirumuskan secara
kuantifikasi. Namun dalam konteks pengembangan, semua pengkaji system ekonomi
Islam, selayaknya peduali dengan berbagai aspek kemaslahatan. Dan membahas
tentang kemashlahtan dalam perspektif ekonomi Islam berarti membahas mengenai
hal-hal yang bersifat kontekstual.
Dan jika
mayoritas kalangan ekonom akademik saat ini masih berkutat melalui
asumsi-asumsi positivistik, maka tidak ada cara lain kecuali mengkaji ulang
asumsi-asumsi tersebut, permasalahan tentang apakah suatu bidang ilmu bisa
dikatakan ilmiah atau tidak ilmiah bukanlah terletak pada penggunaan model
matematis dan analisis statistik yang canggih maupun yang tidak canggih.
Tapi pada kesesuaian asumsi-asumsi dalam epistemologisnya dalam melihat objek
material ilmu tersebut -yang tentunya dalam ilmu-ilmu sosial berbeda jauh dengan
asumsi epistemologis ilmu alam. Karena itulah maka pemahaman terhadap basis
‘nilai’ manusia menjadi sangat penting. Sebuah penilaian manusia tidak dapat
direduksi ke dalam sesuatu yang cardinal. Penilaian manusia akan selalu
berbentuk ordinal. Sebuah nilai tidak akan dapat direduksi ke dalam
agregrat-agregat melalui bahasa matematis dan juga statistik. Tetapi
sebaliknya, nilai adalah sebuah prioritas. Dia tidak dapat menjadi A sekaligus
dalam waktu yang sama menjadi B. Manusia akan selalu dibatasi untuk memilih
-melalui penilaiannya- prioritas antara A atau B, ataupun memprioritaskan B
daripada A.
Dalam ranah
ini maka mempelajari epistemologi ilmu ekonomi akan menjadi penting bagi para
ekonom dan para ahli ilmu sosial. Artinya, filsafat ilmu bukanlah sekedar
digunakan dalam ilmu-ilmu alam, seperti fisika atau matematika. Lebih dari itu,
filsafat ilmu juga sangat berguna sebagai sebuah pengujian terhadap pemikiran
materi-materi metodologis. Namun cara kerja epistemologi bidang kajian ilmu
manusia berbeda dari fisika atau matematika. Dia beroperasi berdasarkan
hukum-hukum logika tindakan. Walaupun preposisi apriori matematis berbeda
dengan preposisi apriori dalam logika tindakan, keduanya mengkarakteristikan
hal yang sama, bahwa kedua proposisi apriorinya tidak mungkin lagi di analisis
menjadi lebih kecil lagi. Artinya, dia menjadi batas akal/rasio dalam
bekerja. Proposisi apriori matematis seperti; +, -, /, x adalah
kaidah-kaidah yang membatasi hukum-hukum berfikir tentang realitas (yang dalam
hal ini bukan ranah tindakan), yang apabila diuji secara empiris akan membawa
pada kesimpulan yang sahih—dengan syarat tidak terjadi kesalahan logis dalam
pendeduksiannya. Dengan demikian, dia sahih baik secara apriori maupun riil.
Demikian halnya dalam logika tindakan. Kaidah-kaidah tentang identitas dan
kontradiksi ialah kaidah yang membatasi dalam memandang realitas.
Kategori-kategori logika seperti “ada”, “semua” serta implikasi-implikasinya
seperti “dan”, “tidak”, “atau”, “jika-maka” merupakan batas-batas yang tidak
dapat dianalisis lebih lanjut. Dia akan begitu dan tetap seperti itu, baik
secara logis maupun riil .
Walaupun
karakter apriori logika tindakan serta karakter apriori matematis memiliki
karakteristik yang sama, akan sangat keliru bagi kaum positivistik, yang
menekankan fungsi prediktif, dengan cara menggunakan perhitungkan matematis
dalam menggambarkan realitas tindakan. Alasannya, kerena proses pendeduksian
matematis tidak dapat ditarik dari aksioma tindakan. Dalam perspektfi ini, maka
sebenarnya positivisme tidak memiliki basis epistemologi apapun. Di sinilah
pentingnya kajian praksiologi atau logika tindakan. Pencarian kebenaran dalam
logika tindakan tidak dilakukan dengan cara mengukur; dia hanya dapat ditelaah
melalui identifikasi reflektif. Identifikasi tersebut mengisyaratkan
bahwa setiap tindakan manusia sepenuhnya subyektif. Jadi memprediksikan
sebuah tindakan adalah sesuatu yang muskil, karena ketika kemarin saya makan
jam 6 pagi, hal tersebut tidak akan menjamin bahwa saya besok akan makan pada
jam yang sama seperti kemarin, secanggih apapun metode statistik yang anda
gunakan, anda tidak akan mampu memprediksikan jam berapa besok saya akan makan.
Karena sebab-sebab konstan dalam sebuah tindakan tidak akan pernah ada sama
sekali. Kemudian kaum positivis mungkin akan bertanya-tanya, untuk apakah science
jika tidak memiliki fungsi prediktif? Yang jelas tanpa memiliki fungsi
prediktif suatu ilmu tetap akan dapat memberi petunjuk bagi manusia untuk
memahami dunianya. Dengan tujuan yang lebih sederhana, tugas ilmu pengetahuan
adalah menguak realitas-realitas yang masih terhalang. Sains tentang manusia
tidak dapat membangun ide-ide apapun, dia hanya dapat menguak realitas.
D.
Arah
Tindakan Masa Depan
Sebagai
sebuah disiplin baru, ekonomi Islam hingga saat ini masih dalam suatu proses
pencarian body of science-nya. Berbagai upaya telah dilakukan dalam
rangka pencarian tersebut, salah satunya adalah dengan mengkaji ulang sejarah
perekonomian dan umat Islam masa lalu, merekonstruksi pemikiran para tokoh (ekonomi)
Islam dan kemudian memberikan interpretasi-interpretasi kritis terhadap sejarah
dan pemikiran tersebut.
Proses
interpretasi sejarah dan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mengalami
pergumulan yang cukup dinamis, dimana muncul pro dan kontra terhadap
terminologi ekonomi Islam itu sendiri, instrumen-instrumen teoritisnya maupun
perdebatan yang bersifat metodologis. Perdebatan-perdebatan itu juga melahirkan
berbagai macam corak pemikiran di bidang ekonomi Islam, dari yang bersifat
liberal hingga radikal.
Metodologi
ekonomi Islam mengungkap permasalahan manusia dari sisi manusia yang multi
dimensional. Keadaan ini digunakan untuk menjaga obyektivitas dalam
mengungkapkan kebenaran dalam suatu femomena. Sikap ini melahirkan sikap
dinamis dan progressif untuk menemukan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki
adalah ujung dari kebenaran. Masudul Alam Chowdhury misalnya, merumuskan
metodologi Islamic Economic dengan istilah shuratic process. Penggunaan istilah
shuratic berasal dari dari kata syura/musyawarah, untuk menunjukkan bahwa
proses ini bersifat konsultatif dan dinamis. Metodologi ini merupakan upaya
untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, sekaligus
didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolak ukur utama
kebenaran ilmiah saat ini.
Sementara
seorang muslim meyakini bahwa kebenaran utama dan mutlak berasal dari Allah,
sedangkan kebenaran dari manusia bersifat tidak sempurna. Akan tetapi manusia
dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris di sekitarnya sebagai wahana untuk
memahami kebenaran dari Allah. Perpaduan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah
akan menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi.
Menurut Chouwdhury sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengatahuan
(primordial stock of knowledge) adalah al-Qur’an, sebab ia merupakan kalam
Allah. Pengetahuan yang ada dalam al-Qur’an memiliki kebenaran mutlak
(absolute), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (complete) dan
karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (irreducible). Akan tetapi,
al-Qur’an pada dasarnya tidak mengetahui pengetahuan yang praktis, tetapi lebih
pada prinsip-prinsip umum. Ayat-ayat al-Qur’an diimplementasikan dalam perilaku
nyata oleh Rasulullah, karena itu as-Sunnah juga adalah sumber ilmu pengetahuan
berikutnya. Al-Qur’an dan Sunnah kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum
dengan menggunakan metode epistemological deduction, yaitu menarik
prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan
dalam realitas individu.
Selanjutnya
dalam epistemologi Ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan
rasio/akal. Ijtihad,[36] yang
terbagi kepada dua macam, yaitu ijtihad istimbathi
dan ijtihad tathbiqi. Ijtihad istimbathi bersifat deduksi, sedangkan
ijtihad tathbiqi bersifat induksi.
Dari segi kuantitas orang yang berijtihad, ijtihad dibagi kepada dua, yaitu
ijtihad fardi (individu) dan ijtihad jama’iy (kumpulan orang banyak). Ijtihad
yang dilakukan secara bersama disebut ijma’ dan dianggap memiliki tingkat
kebenaran ijtihad yang paling tinggi. Dalam membicarakan epistemologi ekonomi
Islam, digunakan metode desuksi dan induksi. Ijtihad tahbiqi yang banyak
mengunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab
ia didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini -yaitu
kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan as- Sunnah dengan pemikiran
dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad akan menghasilkan hukum
dalam berbagai bidang kehidupan. Jika diperhatikan, maka sesungguhnya Shuratic
proses ini merupakan suatu metode untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang
memiliki akar kebenaran empiris (truth based on empirical process).
E.
Penutup
Sudah
cukup lama umat manusia mencari sistem untuk meningkatkan
kesejahteraan khususnya di bidang ekonomi. Selama ini memang sudah ada beberapa
sistem, diantaranya dua aliran besar sistem perekonomian yang dikenal di dunia,
yaitu sistem ekonomi kapitalisme, dan sistem ekonomi sosialisme. Tetapi
sistem-sistem itu tidak ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi optimal. Konsekuensinya orang-orang
mulai berpikir mencari alternatif. Dan alternatif yang oleh banyak kalangan diyakini lebih
menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam. Karena sistem ini berpijak pada
asas keadilan dan kemanusiaan. Oleh karenanya, sistem
ini bersifat universal, tanpa melihat
batas-batas etnis, ras, geografis, bahkan agama.
Untuk
mewujudkan tujuan ini, setidaknya dibutuhkan usaha yang berujung pada perubahan
paradigmatik dalam menyikapi ajaran praktis sistem ekonomi Islam. Perubahan
paradigmatik ini sangat diperlukan. Sistem ekonomi Islam tidak hanya dapat
diukur melalui pendekatan kuantitatif-nomotetik selanjutnya dereduksi menjadi
angka-angka, namun juga dapat didekati dengan menggunakan pendektan kualitatif
dan dalam pemahaman multikulturalisme untuk mewujudkan sistem ekonomi sebagai
suatu sistem profetis dengan cara membaca realitas sosial untuk kemudian
merumuskannya dalam sistem perekonomian Islam. Sehingga sistem ekonomi Islam
dapat berfungsi ganda, disamping sebagai alat untuk mengukur tingkat
kesejahteraan sekaligus sebagai alat rekayasa perekonomian Islami sebagaimana
tujuan yang hendak dicapai yakni menuju falah.
F.
Kepustakaan
Abdul
Aziz Dahlan (ed). 1997. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar
Baru van Hoeve.
Adiwarman
A. Karim. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi
Islam, Edisi Ketiga. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
Agustianto.
Epistemologi Ekonomi Islam pada http://agustianto.niriah.com/2008/03/11/epistemologi-ekonomi-islam
di akses pada 21 November 2009.
Bruce
J. Caldwell. 2004. Beyond Positivism Economics Methodology in the Twentieth
Century. London: Routledge, 2004.
Deliarnov .1997. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta:
P.T. Raja Grafindo Persada.
F.
Budi Hardiman. 2003. Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus
Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas. Yogyakarta:
Kanisius
F.
Budi Hardiman. 2007. Filsafat Modern dari
Machiavelli hingga Nietzsche. Jakart: Gramedia Pustaka Utama
Giyanto.
Melawan Positivisme dalam Jurnal
Kebebasan: Akal dan Kehendak Volume III, Edisi No. 70, Tanggal 22 Maret 2009
pada (Http://akaldankehendak.com)
diakses pada 27 Desember 2009
Goenawan
Muhammad. 1999. Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Bagian 2.
Yogyakarta: P3EI FE UII
Hermansyah,
2010. Kultursigrafi Ekonomi Islam di Indonesia. Mataram: CV. Dimensi
Raya.
Hamka
Haq. 2007. Al-Syathibi Aspek Teologis
Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-Muwafaqat. Jakarta. Erlangga
Javed
Ansari. 1985. Gerakan Islamisasi: Sebuah Pengantar dalam buku Islamisasi Ekonomi Suatu Sketsa Evaluasi dan
Prosdek Gerakan Perekonomian Islam. Yogyakarta: PLP2M.
M. Umer Chapra. 2001. The Future Of Economics: An Islamic
Persfektive. Jakarta: SEBI.
Masdar
F. Mas’udi. 1998. Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi dalam
Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas.
Muhammad Baqir
Ash-Shadr. 1999. Falsafatuna. (Terj.
M. Nur Mufid bin Ali). Mizan: Bandung
Neong
Mahadjir, 2001. Filsafat Ilmu: Positivisme, PostPositivisme, dan
PostModernisme. Yogyakarta: Rakesarasin.
Soedjono Dirdjosisworo.
1985. Pengantar Epistemologi dan Logika
Bandung: CV. Remadja Karya
Syed
Nawab Haider Naqvi. 1994. Islam, Economics, and
Society. London & New York: Kegan Paul International.
Tim P3EI. 2008. Ekonomi
Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Toshihiko
Izutsu. 1993. Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Al Qur’an. (Terj. Agus Fahri
Husein dan A.E. Priyono). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Yudian
W. Aswin. 2007. Maqashid al-Syariah
Sebagai doktrin dan Metode dalam buku M. Amin Abdullah Re-Strukturisasi Meodologi
Islamic Studies Mazhab Yogyakarta. Yogyakarta: Suka Press.
Yudian
Wahyudi. 2007. Maqashid Syariah Dalam Pergumulan
Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga. Yogyakarta:
Nawesea Press.
Yusdani,
at-Tufi dan Teorinya tentang Maslahat,
Makalah disampaikan pada acara bedah metodologi kitab kuning seri ushul fikih
humanis, UII selasa 7 September 2004
Ziauddin
Sardar. 2003. Kembali ke Masa Depan
(Terj. R. Cecep Lukman dan Helmi Mustofa). Jakarta: Serambi.
[1] Lihat Soedjono
Dirdjosisworo, Pengantar Epistemologi dan
Logika (Bandung: CV. Remadja Karya, 1985), hal. 1
[2] Lihat Goenawan Muhammad. Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Suatu
Pengantar. Bagian 2 (Yogyakarta: P3EI FE UII, 1999), hal. 24.
[3] Lihat Agustianto. Epistemologi Ekonomi Islam pada http://agustianto.niriah.com/2008/03/11/epistemologi-ekonomi-islam
di akses pada 21 November 2009
[4] Goenawan Muhammad. Metodologi….hal. 25
[5] Empirisme berpendapat bahwa
penginderaan adalah satu-satunya yang membekali akal manusia dengan
konsepsi-konsepsi dan gagasan-gagasan, dan (bahwa potensi mental akal budi)
adalah potensi yang tercerminkan dalam berbagai peristiwa inderawi. Lihat
Muhammad Baqir Ash-Shadr. Falsafatuna.
Terj. M. Nur Mufid bin Ali (Mizan: Bandung, 1999), hal. 31-32
[6] Rasionalisme berpendapat
bahwa terdapat dua sumber bagi pengetahuan yakni penginderaan (sensasi). Kita
mengkonsepsi panas, cahaya, rasa dan suara karena penginderaan kita terhadap
semua itu. Dan kedua, adalah fitrah dalam arti bahwa akal manusia memiliki
pengertian-pengertian dan konsepsi-konsepsi yang tidak muncul dari indera,
namun ia sudah ada (tetap) dalam lubuk fitrah. Lihat Muhammad Baqir Ash-Shadr. Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali
(Mizan: Bandung, 1999), hal. 28-29
[7] Positivism beranggapan agar
pengetahuan tidak melampaui fakta-fakta. Fakta dimengerti sebagai fenomena yang
dapat di observasi, karena itu disini kita melihat bahwa positivism masih
terakait erat dengan empirisme, namun perbedaannya lebih pada penolakan
positivism terhadap pengalaman subyektif yang bersifat rohani, sedangkan empirisme
masih menerimanya. Lihat F. Budi Hardiman. Filsafat
Modern dari Machiavelli hingga Nietzsche (Jakart: Gramedia Pustaka Utama,
2007), hal. 205
[8] Lihat F. Budi Hardiman. Filsafat…. hal. 204-213
[9] Lihat Syed Nawab Haider
Naqvi. Islam, Economics, and Society. (London & New York: Kegan Paul International, 1994)
[10] Pengaruh positivisme dalam ilmu ekonomi meliputi rentang waktu sekitar
40 tahun, dimulai pada akhir tahun 1930 sampai pada akhir tahun 1970.
Sepanjang waktu tersebut tidak berarti pada ekonom dengan penuh kesadaran
mengikuti filosofi seperti diuraikan di
atas. Dalam kenyataannya, ekonom tertentu menulis tentang metodologi yang diambil dari aliran positivisme, sedangkan
ekonom lainnya menggunakan pendapat
ilmuwan positivis untuk membenarkan atau untuk mempertahankan adanya perubahan tertentu dalam praktek ilmu ekonomi
yang terjadi pada waktu itu. Sehingga positivisme
berpengaruh secara tidak langsung, baik dalam penulisan metodologi maupun dalam pekerjaan para praktisi ekonomi.
Lihat F. Budi Hardiman. Filsafat
Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).
[11] Soedjono Dirdjosisworo. Pengantar….hal. 1-3
[12] Lihat Giyanto. Melawan Positivisme dalam Jurnal
Kebebasan: Akal dan Kehendak Volume III, Edisi No. 70, Tanggal 22 Maret 2009
pada (Http://akaldankehendak.com)
diakses pada 27 Desember 2009
[13] F. Budi Hardiman. Melampaui
Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan
Problem Modernitas. (Yogyakarta: Kanisius,
2003). hal. 56
[14] Neong Mahadjir, Filsafat
Ilmu: Positivisme, PostPositivisme, dan PostModernisme (Yogyakarta:
Rakesarasin, 2001), hal. 69
[15] Ibid. Lihat juga Hermansyah, Kultursigrafi Ekonomi Islam di
Indonesia (Mataram: CV. Dimensi Raya, 2010).
[16] Lihat juga Bruce J.
Caldwell, Beyond Positivism Economics Methodology in the Twentieth Century.
(London:
Routledge, 2004) pada Bab 6 dan 7.
[17] Fiedman secara tegas
menyatakan bahwa banyak terdapat kekeliruan dalam ilmu ekonomi, terutama
terkait dengan pengambilan kebijakan, yang timbul dari kebingungan dalam
membedakan antara ilmu ekonomi positif dan normatif. Ia merasa bahwa banyak
argumen-argumen terhadap effek positif sebuah kepastian tindakan kebijaksanaan
lebih jelas sebagai isu-isu normatif. Ibid. hal. 173-180
[18] Deliarnov Perkembangan Pemikiran Ekonomi,
(Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 1997).
[19] Javed Ansari. Gerakan Islamisasi: Sebuah Pengantar dalam buku Islamisasi Ekonomi Suatu Sketsa Evaluasi dan Prosdek Gerakan
Perekonomian Islam (Yogyakarta: PLP2M,
1985), hal. 102
[20] Misalnya dalam persoalan
berkah atau nilai maslahah dalam perilaku ekonomi, dimana keberkahan dan
kemaslahatan, diukur berdasarkan variabel-veriabel yang bersifat empiris.
Disini mestinya diakui bahwa keberkahan dan kemaslahatan itu berhubungan nilai
dan rasa serta pengalaman spiritual pelaku ekonomi yang tidak dapat
dikuantifikasi antara pengalaman saya dan yang anda rasakan. Lihat Tim P3EI, Ekonomi
Islam, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2008)
[21] Lihat M. Umer Chapra. The Future Of Economics: An Islamic
Persfektive (Jakarta:
SEBI, 2001), hal. 141-142
[22] Tim P3EI, Ekonomi…hal. 135
[23] Yusdani, at-Tufi dan Teorinya tentang Maslahat,
Makalah disampaikan pada acara bedah metodologi kitab kuning seri ushul fikih
humanis, UII selasa 7 September 2004
[24] Lihat misalnya Toshihiko
Izutsu. Konsep-Konsep Etika Religius
Dalam Al Qur’an. Terj. Agus Fahri Husein dan A.E. Priyono (Yogyakarta: PT.
Tiara Wacana, 1993)
[25] Lihat juga pada
Ziauddin Sardar. Kembali ke Masa Depan
Terj. R. Cecep Lukman dan Helmi Mustofa (Jakarta:
Serambi, 2003), hal. 40-41
[26] Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam.
(Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hal. 1144.
[27] Haq, Hamka, Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah
Dalam Kitab al-Muwafaqat. (Jakarta.
Erlangga 2007), hal. 57
[28] Adiwarman A. Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi
Ketiga (Jakarta.
PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 382
[29] Haq, Hamka, Al-Syathibi Aspek….. hal. 103
[30] Abdul
Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi…hal.1143
[31] Untuk mengetahui beberapa
definisi menyangkut masalah ini mislanya dapat dilihat pada Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum….hal. 1144
[32] Lihat Yudian W. Aswin. Maqashid al-Syariah Sebagai doktrin dan
Metode dalam buku M. Amin Abdullah Re-Strukturisasi
Meodologi Islamic Studies Mazhab
Yogyakarta (Yogyakarta: Suka Press, 2007),
hal 147
[33] Lihat Yudian Wahyudi. Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik
Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (Yogyakarta:
Nawesea Press, 2007), hal.28-29
[34] Masdar F.
Mas’udi, Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi dalam Polemik
Reaktualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hal.
180
[35] Ziauddin Sardar.
Kembali ke…hal. 43
[36] Lihat Amir
Mu’allim dan Yusdani. Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer. (Yogyakarta: UII Press, 2005)