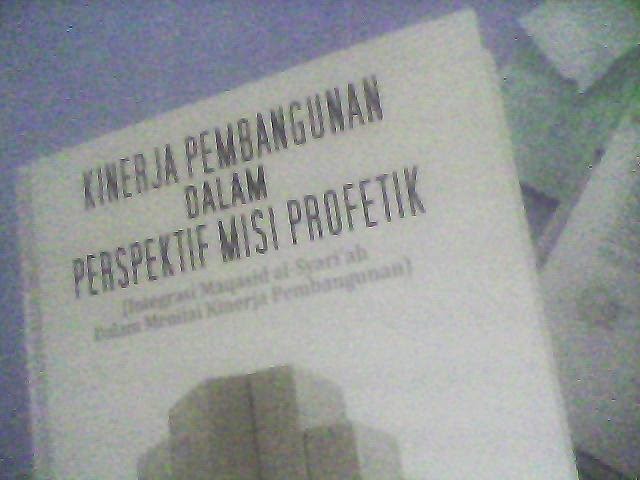Pendahuluan
Pada 21 Mei 1998 Suharto tumbang hal ini menandakan babak baru perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gerakan massa yang luar bisa menakjubkan (yang lebih diidentifikasi sebagai gerakan mahasiswa dan buruh pekerja), telah menemukan momentumnya dan meraih kemenangan besar guna mengakhiri satu rangkaian cerita tentang kekuasaan rezim otoriter Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Inilah awal sebuah revolusi, mirip seperti tahun 1931, saat monarki Spanyol diruntuhkan dan berdirinya Republik Spanyol. Sepertinya Indonesia saat itu memasuki jalan yang sama, yakni revolusi. Revolusi seperti banjir, gempa bumi dan gunung meletus tidak seorangpun dapat mengendalikannya. Apapun yang kita lakukan, ia mengikuti jalannya sendiri, tanpa menghiraukan kita yang menciptakannya.(Muchtar Lubis, dalam Anthony J.S. Reid, “Revolusi Nasional Indonesia” 1996:103).
Beragam pemikiran yang mengatakan perubahan yang terjadi di bulan Mei 1998 adalah sebuah perubahan revolusioner. Gerakan massa menumbangkan kekuasaan rezim Suharto berawal dari gerakan mahasiswa yang memprotes terjadinya krisis moneter (Lihat Manan, 2005:71-84). Memang tak ada yang luar biasa dari hal tersebut, namun dari sinilah cikal bakalnya sebuah gerakan revolusioner untuk penggulingan kekuasaan dalam masa kekuasaan yang disebut Suhartonisme. Meskipun diakui bahwa elemen mahasiswa dan para cendekiawan tak dapat memainkan peran independen dalam masyarakat, namun mesti diakui juga bahwa mereka telah dan mampu merepresentasikan barometer yang sangat sensitif yang secara setia merefleksikan animo yang bergerak dalam masyarakat. Hal ini mirip dengan revolusi yang terjadi di Rusia dan revolusi di Spanyol dimana dalam tahap-tahap awalnya, revolusi Rusia dimulai sebagai gerakan revolusioner kaum cendekiawan antara 1860-70an. Revolusi Spanyol di awal 1930-an juga dimulai sebagai gerakan mahasiswa." (Trotsky, dalam C. Wright Mills, 2003:169)
Demikian pula di Indonesia, para mahasiswa merasa bahwa mereka merepresentasikan animo umum dari ketidakpuasan yang dialami masyarakat, mereka membangun kekuatan dan keberanian dari kenyataan ini. Sebegitu cepat protes-protes mahasiswa menyebar ke berbagai sektor di Indonesia, hingga menyeret hampir seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Elemen terpenting adalah keberanian para mahasiswa yang tak mengenal takut, keteguhan mereka berhadapan dengan pemukulan, pemenjaraan, dan kematian dalam perjuangan. Hingga akhirnya gerakan ini menumbangkan kekuasaan rezim Orde Baru.
Dalam konteks ini beberapa pertanyaan muncul; pertama, mengapa di Indonesia gerakan revolusioner selalu muncul dalam setiap gerakan menggusur suatu rezim, padahal Indonesia penduduknya bukanlah komunis seperti Rusia, Kuba, Cina dan negara lainnya? Kedua, bilamana Indonesia punya kecenderungan dan berpotensi melakukan revolusi, namun mengapa setiap gerakan revolusioner khususnya tahun 1998 tidak sampai pada titik revolusi sosial, sebagimana yang diangankan oleh pencetus revolusi?
Akar Historis Gerakan Revolusioner Di Indonesia
Gerakan radikal dan revolusioner di Indonesia bukanlah fenomena yang datang tiba-tiba, bahkan ia telah menjadi bagian tersendiri dari proses sejarah perjuangan bangsa ini. Kelahirannya tentu tidak dapat dielakkan dari situasi politik, ekonomi dan sosial budaya bahkan agama yang menopangnya. Bilamana ditilik kebelakang, pemikiran radikal dan revolusioner muncul di tahun tahun 1914, yang dibawa oleh Sneevliet (lengkapnya, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, lahir di Rotterdam, 13 Mei 1883) orang Belanda (Tabloid Pembebasan, 2004:1). Ia dikenal sebagai seorang penyemai virus ideologi komunisme.
Sebelum 1914 ---saat dimana kelas buruh tidak mempunyai organisasi politik seperti negara lain--- tak ada seorang pun dapat mempredikisi bahwa yang beranama Indonesia, sebuah bangsa jajahan dan bangsa terkebelakang, namun beberapa tahun saja akan ada pemikiran radikal, bahkan sebuah partai komunis. Di bumi Indonesia ini pulalah pertama kalinya dalam sejarah dunia kolonial sebuah partai komunis yang berbasis massa berkembang pesat.
Orang Indonesia sebelum tahun 1914 telah mengenal organisasi yakni Boedi Oetomo dan Sarekat Islam. Boedi Oetomo adalah organisasi pertama yang didirikan oleh kaum muda Indonesia kelas ningrat tahun 1908. Organisasi ini yang hampir seluruh anggotanya terdiri atas para administrator dan intelektual Jawa lebih merupakan jembatan antara pejabat pemerintahan kolonial yang sudah maju dan kaum terpelajar Jawa (Audrey, 2005:11). Namun Boedi Oetomo hanya didasarkan pada gagasan idealis gotong royong tanpa adanya kesadaran politis. Program-program Boedi Oetomo sama sekali bukan berorientasi ideolgis dan politis, melainkan bertujuan mengembangkan pendidikan tradisional dan pendidikan barat di kalangan suku Jawa dan Madura, memajukan pertanian, industri dan perdagangan di kalangan mereka serta segala yang memberi mereka jaminan untuk bisa hidup secara terhormat (Kahin, 1995:84). Sedangkan Sarekat Islam (SI) berdiri tahun 1912, sebuah organisasi nasionalis pertama yang berskala Indonesia dan menuntut kemerdekaan Indonesia, akan tetapi tahun 1913 partai ini dilarang karena tuntutan kemerdekaan tersebut. Satu catatan penting bahwa gerakan Sarekat Islam bukan menitik beratkan pada nasionalisme ataupun program politik, melainkan pada agama. Disebabkan oleh 90% penduduk Indonesia menganut Islam, maka otomatis Islam merupakan institusi utama dari masyarakat tradisional. Oleh karena itulah mengapa Sarekat Islam berkembang pesat ke pelosok tanah air dan Islam menjadi ikon satu-satunya pusat perlawanan anti pemerintahan asing, walaupun pada dasarnya oposisi ini tanpa bentuk dan tanpa program politik (Reid, 1996:6).
Sebenarnya Sarekat Islam lahir dari rahim masyarakat pedagang Indoensia. Ia bermula dari Sarekat Dagang Islam yang dibentuk tahun 1909 oleh seorang bangsawan Jawa Raden Mas Tirtaodisoeryo, dan pada tahun 1911 mendapat dukungan yang luas setelah mendapat respon dari pengusaha batik Indonesia Haji Samonhadi yang juga pemimpin agama Islam berpengaruh. Dua tahun kemudian, 1913, di bawah pimpinan Tjokroaminoto, membuang "dagang" dari namanya menjadi Serikat Islam. Meskipun pada kenyataannya Sarekat Islam jauh dari gagasan pejuangan nasionalis dan politis, tidak mempunyai program politik di luar "melayani kepentingan orang Islam", dan keorganisasiannya longgar sekali, namun Sarekat Islam tatap saja dipercaya dan memegang peran perjuangan nasional sehingga keanggotaannya tumbuh dengan dahsyat, sampai ratusan ribu pada tahun 1916, terutama berpusat di kota (Kahin, 1995:86-90). Hal ini secara grafikal mencerminkan pencarian massa buruh menemukan alat perjuangan guna melawan kondisi mereka yang makin memburuk.
Hal apakah yang menyebabkan, hanya beberapa tahun dan di dalam sebuah negeri yang luar biasa terbelakang, munculnya sebuah partai komunis dengan basis massa yang kemudian merubah situasi politik bangsa Indonesia? Tak dapat disangkal, peran kunci dimainkan oleh Hendricus Sneevliet, pemimpin sayap kiri Serikat Buruh Kereta Api dan sebelumnya merupakan tokoh sayap kiri gerakan sosialis, yang terpaksa mengungsi ke Indonesia tahun 1913 sesudah dimasukkan daftar hitam oleh birokrasi reformis dan kaum majikan Belanda.
Ketika ia datang ke Indonesia, situasi dunia pergerakan di Hindia Belanda tengah mengalami musim semi. Sneevliet, yang pada awalnya bekerja sebagai jurnalis di sebuah harian di kota Surabaya, mulai terusik kembali berpolitik, ia kemudian pindah ke Semarang dan menjadi sekretaris di sebuah perusahaan. Pada tahun 1914, ia mendirikan sebuah organisasi politik yang diberi nama Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Awalnya anggotanya hanya 65 orang terdiri dari Belanda dan kalangan Indo-Belanda. Dalam waktu setahun kemudian, organisasi tersebut mengalami perkembangan pesat menjadi ratusan anggotanya. Beberapa tokoh Belanda yang aktif membantu Sneevliet adalah Bersama, Adolf Baars, Van Burink, Brandsteder dan HW Dekker dan di kalangan pemuda Indonesia tersebut nama-nama Semaun, Alimin dan Darsono (Kahin, 1995:92).
Pada waktu yang bersamaan, pergerakan di Hindia Belanda tengah mengalami masa terang. Sarekat Islam, terus membesar dengan jumlah anggota mencapai puluhan ribu yang tersebar di berbagai daerah. Melihat kondisi tersebut, ISDV merubah haluan untuk menitik beratkan pengorganisiran pada anggota-anggota Sarekat Islam, dan inilah cikal bakal generasi pertama perekrutan kader-kader Marxis. Maret 1917 Sneeveliet menulis artikel berjudul Zegepraal (kemenangan) sebagai penghormatan dan memuliakan Revolusi Februari Kerensky di Rusia (Tabloid Pembebasan, 2004:2):
“Telah berabad-abad di sini hidup berjuta-juta rakyat yang menderita dengan penuh kesabaran dan keprihatinan, dan sesudah Diponegoro tiada seorang pemuka yang menggerakkan massa ini untuk menguasai nasibnya sendiri. Wahai rakyat di Jawa, revolusi Rusia juga merupakan pelajaran bagimu. Juga rakyat Rusia berabad-abad mengalami penindasan tanpa perlawanan, miskin dan buta huruf seperti kau. Bangsa Rusia pun memenangkan kejayaan hanya dengan perjuangan terus-menerus melawan pemerintahan paksa yang menyesatkan. Apakah penabur dari benih propaganda untuk politik radikal dan gerakan ekonomi rakyat di Indonesia memperlipat kegiatannya? Dan tetap bekerja dengan tidak henti-hentinya, meskipun banyak benih jatuh di atas batu karang dan hanya nampak sedikit yang tumbuh? Dan tetap bekerja melawan segala usaha penindasan dari gerakan kemerdekaan ini? Maka tidak bisa lain bahwa rakyat di Jawa, diseluruh Indonesia akan menemukan apa yang ditemukan oleh rakyat Rusia: kemenangan yang gilang gemilang”.
Organisasi ISDV bergerak cepat dengan strategi merekrut massa dari Sarekat Islam. Semaun, Darsono dan Alimin, adalah pimpinan-pimpinan Sarekat Islam Semarang yang berhasil direkrut oleh Snevlieet. Mereka punya kesamaan pandangan, prinsip-prinsip ideologi radikal dengan ISDV. Ini pulalah yang pada akhirnya menyebabkan perpecahan di tubuh Sarekat Islam, perpecahan antar sayap moderat dan sayap radikal. Sarekat Islam (Putih/moderat) dipimpin HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim dan Abdul Muis, sedangkan SI (Merah/Radikal) dikepalai oleh Semaun dan teman temannya. Selain dari propaganda ISDV ditambah lagi kemenangan revolusi Rusia yang banyak menjadi bahan perbincangan rakyat membuat pengaruh ISDV cepat meluas di kalangan masyarakat. Pemogokan-pemogokan buruh kian hari makin bertambah kuat dan meluas. Pengaruh ISDV yang kuat ternyata mengkhawatirkan Belanda dan hal ini kemudian membuat berdampak kurang menguntungkan bagi ISDV dimana Sneeliet pada Desember 1918 terpaksa ditangkap dan diusir dari Indonesia oleh Belanda. Ironisnya ISDV juga mulai dijauhi massa akibat prinsip-prinsip radikal mereka yang masih belum bisa dipahami massa. Semaun pun mengambil keputusan, mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tujuh bulan kemudian, partai ini mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia, dimana Semaun langsung yang menjadi ketuanya (Kahin, 1995:95).
Pidato pembelaan Snevlieet yang disampaikannya sewaktu ia diproses oleh jaksa dan hakim di depan pengadilan pada bulan November 1917 setebal 366 halaman merupakan sumber referensi mengenai ajaran-ajaran sosialisme secara ilmiah, yang dipakai oleh banyak pemimpin-pemimpin bangsa. Salah satunya adalah Indonesia Menggugat, pidato pembelaan Bung Karno yang dibacakan di muka Pengadilan di Bandung pada tahun 1930. Pledoi setebal 183 halaman itu jelas-jelas menunjukkan pengaruh yang besar sekali dari jalan pikiran Sneevliet yang dikembangkannya di tahun 1917. Sejak saat itulah ajaran-ajaran Marxisme meluas di Indonesia. PKI berdiri di Semarang, pada tahun 1920 dengan Semaun-Darsono yang mempeloporinya. Di Surabaya Tjokroaminoto dari Serikat Islam, mulai juga memakai referensi-referensi kiri dan literatur yang disebut oleh Sneevliet di dalam pembelaannya, seperti: artikel Das Kapital-nya Marx. Berbagai literatur tersebut mulai dicari-cari beberapa aktivis. Ada juga yang berusaha mendapatkannya dengan membeli dan meminjam dari toko buku ISDV, dan dikaji di rumah Tjokroaminoto bersama-sama Surjopranoto, Alimin dan lain-lain. Termasuk salah satunya adalah Bung Karno, yang tahun 1916-1920 indekos pada keluarga Tjokroaminoto, seorang tokoh pergerakan di Surabaya. Bung Karno mengakuinya dalam sebuah surat yang ditulisnya saat dia menjalani masa pembuangan di Bengkulu, tahun 1941 (Tabloid Pembebasan, 2004:4):
“Sejak saya sebagai seorang anak plonco, untuk pertama kalinya saya belajar kenal dengan teori Marxisme dari mulut seorang guru HBS yang berhaluan sosial demokrat (C. Hartough namanya) sampai memahamkan sendiri teori itu dengan membaca banyak-banyak buku Marxisme dari semua corak, sampai bekerja di dalam aktivitas politik, sampai sekarang, maka teori Marxisme bagiku adalah satu-satunya teori yang saya anggap kompeten buat memecahkan soal-soal sejarah, soal-soal politik, soal-soal kemasyarakatan.”
Menurut Kahin (1995:96) kesuksesan usaha Sneevliet terutama bukan karena kualitas pribadinya melainkan akibat pengertiaannya atas pembelajaran Marxisme dan cara mengorganisir kaum buruh dan kepemimpinan organisasi kelas buruh. Pengalamannya dalam gerakan buruh yang termaju dan terorganisir di Eropa Barat suatu hal yang penting sekali dalam usahanya menjadi katalis, menyatukan ide-ide Marxisme dan pengalaman itu dengan gerakan kaum buruh Indonesia. Pikiran dan metode sayap kiri yang dibawa oleh Sneevliet ke Indonesia, bukan pemahaman Leninis mengenai pembangunan kader. Kontribusi Sneevliet terutama terletak pada orientasi kelas yang konsisten yang ia bawa ke dalam perjuangan bangsa Indonesia, mengaitkan antara perjuangan kemerdekaan nasional dan perjuangan kelas buruh.
Usaha Sneevliet di Indonesia, yang meletakkan pondasi bagi PKI, ada tiga segi: membentuk nukleus kaum sosialis (dimulai dari para pekerja asing berkebangsaan Belanda); membangun gerakan serikat buruh, dan melakukan intervensi ke dalam gerakan nasionalis. Dan atas prakarsa Sneevliet lah pada tahun 1914 didirikan Persatuan Sosial Demokrat Indonesia (ISDV), yang merupakan cikal bakal Partai Komunis. Sejak mulanya tendensi revolusioner mengendalikan ISDV, sikapnya militan terhadap isu-isu lokal dan selain itu ISDV juga melibatkan diri dalam pergerakan nasional.
Revolusi dan Perubahan Sosial di Indonesia
Gerakan massa oleh mahasiswa, cendekiawan dan buruh pekerja di tahun 1998 menggulingkan rezim Suharto telah berhasil melumpuhkan kekuatan rezim berkuasa, namun cita-cita revolusi tak kunjung menemukan sosoknya. Penyerahan kekuasaan Suharto kepada wakilnya BJ Habibie, yang dijustifikasi oleh MPR merupakan pembelokan dari cita-cita revolusi. Sesungguhnya, "legitimasi" Habibie ada pada kenyataan bahwa secara personal ia ditunjuk oleh Soeharto dan disetujui oleh majelis nasional. Dukungan para pimpinan oposisi kaum boujuasi dan kawan-kawan bahwa pemerintahan Habibie adalah “pemerintahan Indonesia yang sah” kian mengaburkan perjuangan revolusi.
Para petinggi ABRI juga mendukung Habibie. Segera setelah Habibie diambil sumpahnya, Pangab Jenderal Wiranto menyatakan bahwa “pihak militer memberi dukungan kepada presiden baru dan mengatakan bahwa militer akan mencegah kekacauan di masa datang. Ia juga berjanji untuk melindungi Soeharto dan keluarganya yang sama sekali tidak populer bagi rakyat" (Manan, 2005:101). Meskipun terjadi resistensi yang luar biasa terhadap pemerintahan Habibie seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa yang telah dan terus menuntut agar Soeharto dan kroni-kroninya diseret ke pengadilan: "Kami menolak pemilihan Habibie ke kursi kepresidenan karena ia adalah bagian dari rezim yang sama," kata Rama Pratama, ketua Senat Mahasiswa UI Jakarta, (Lihat Manan, 2005:179-184), namun bagaimanapun semua itu tidak memberi arti signifikan terhadap perjuangan mewujudkan revolusi.
Dalam situasi transisi yang acak dan tak menentu ---setelah penyerahan kekuasaan dari Suharto ke Habibie--- bermacam alternatif solusi muncul dari berbagai pihak, mulai yang paling moderat hingga yang radikal: Revolusi adalah kata yang paling sering muncul dan kata revolusi menjadi ikon dalam jargon politik dan gerakan massa. Misalnya pada minggu kedua bulan Juni 1998 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan jargon politik "Revolusi dari Surabaya" yang diangkat bertepatan dengan kunjungan Habibie ke Surabaya. Beberapa orang juga sudah menyamakan konsep "Reformasi Total" dengan "Revolusi". Alternatif solusi tersebut timbul karena kegagalan Habibie dalam memimpin negara. Setidaknya dua tokoh dengan massa besar sudah menyatakan hal itu: K.H. Abdurrahman Wahid dengan 30 juta massa NU-nya sudah menyatakan bahwa pemerintahan Habibie gagal. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia, Megawati Soekarno Putri juga sudah mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa pemerintahan Habibie tidak dipercaya oleh rakyat. Dalam bentuk yang lain, Amien Rais, ketua umum Partai Amanat Nasional sudah mengancam akan mengerahkan massa jika Habibie tidak serius mengusut kekayaan Soeharto. Walau bagaimana pun usaha Gus Dur mencanangkan dan mengkampanyekan revolusi sosial yang kemudian diiukuti secara latah oleh beberapa pemimpin lainnya, ditambah lagi dengan gejolak kekacauan dan kekerasan yang kian mengalami chaos, toh pada akhirnya revolusi yang diangankan tidak juga terwujud.
Apa yang dapat dipahami dari peristiwa 1998 tersebut; adakah memang perubahan yang terjadi adalah sebuah revolusi ataukah hanya reformasi atau replacment. Bila ditilik lebih seksama senyatanyalah terma revolusi merupakan sebuah persepektif dalam teori perubahan sosial dalam kajian sosiologi. Revolusi adalah puncak dari perubahan sosial itu sendiri. Revolusi merupakan wujud perubahan sosial paling spektakuler. Ia dapat dimaknai sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis; revolusi melakukan pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan pembentukan ulang manusia. Revolusi tak menyisakan apa pun seperti keadaan sebelumnya. Revolusi menutup epos lama dan membuka epos baru.
Menurut Piotr Sztompka, (2005:357) yang membedakan revolusi dengan teori perubahan sosial lainnya seperti evolusi dan gerakan sosial adalah; pertama, revolusi menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas, menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat; ekonomi, politik, kultur, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia. Kedua, revolusi melakukan perubahan secara radikal, fundamental, menyentuh inti bangunan dan fungsi sosial. Ketiga, perubahan yang terjadi sangat cepat, tiba-tiba di tegah aliran lembat proses historis. Keempat, revolusi adalah pertunjukan perubahan paling menonjol; waktunya luar biasa cepat. Kelima, revolusi membangkitkan emosional khusus dan reaksi intelektual pelakunya dan mengalami ledakan mobilisasi massa, antusiasme, kegemparan, kegirangan, kegembiraan, optimisme, dan harapan; perasaan hebat dan perkasa, keriangan aktivisme dan menggapai kembali makna kehidupan, melambungkan aspirasi dan pandangan utopia ke masa depan. Ted Grant dan Alan Woods, (1998:13) mengatakan bahwa revolusi terjadi apabila; pertama, terbelahnya kelas berkuasa. Kedua, berbalik arahnya kaum bourjuasi kecil dari status qou ke revolusi. Ketiga, persiapan kelas pekerja untuk melakukan perubahan radikal. Keempat, adanya sebuah partai revolusioner.
Merujuk Ted Grant dan Alan Woods di atas, benarlah bahwa kelas yang berkuasa di Indonesia terbelah, sebagian ingin membuang Soeharto secepatnya, bahkan ketua MPR Harmoko --kroni lama presiden- menyarankan Suharto mundur; sebagian yang lain menolak langkah yang tersebut karena takut bahwa dalam pemerintahan akan timbul gerakan yang tak dapat dikontrol oleh siapapun (Lihat Manan, 2005:85-88). Pernyataan-pernyataan yang kontradiktif dari jenderal Wiranto misalnya jelas mengindikasikan bahwa telah terjadi perpecahan-perpecahan dan keterombang-ambingan kelas penguasa. Syarat kedua terjadinya revolusi adalah bahwa kaum borjuis kecil, lapisan menengah dari masyarakat, harus berganti arus dari status quo ke revolusi. Nyatanya di Indonesia, mayoritas kelas menengah telah berbalik dari rezim atau secara aktif memeranginya sebagaimana diperlihatkan oleh gerakan mahasiswa. Syarat ketiga adalah bahwa kelas pekerja harus disiapkan untuk berjuang bagi perubahan radikal dalam masyarakat (Lihat Manan, 2005:190-196). Dan memang kelas pekerja Indonesia, telah memasuki kancah perjuangan. Namun ada faktor menentukan yang masih belum ada yaitu faktor subjektif --sebuah partai revolusioner dan kepemimpinan yang mampu menyediakan organisasi yang diperlukan, program dan perspektif untuk menyatukan gerakan dan mengarahkannya untuk merebut kekuasaan.
Walaupun telah terjadi perubahan tahun 1998 dengan tumbangnya Suharto namun tidak cukup alasan mengatakan bahwa tragedi itu adalah sebuah revolusi karena revolusi secara hakiki adalah sebuah krisis politik yang diakibatkan tindakan-tindakan ilegal dan inkonstitusional yang bermaksud mengganti lembaga-lembaga politik, merombak struktur sosial atau menggulingkan pemerintahan. Selain itu, Piotr Sztompka, (2005:361) mengikhtisarkan bahwa pertama, revolusi mengacu pada perubahan fundamental, menyeluruh dan multidimensional, menyentuh inti tatanan sosial. Oleh karena itu perombakan sebagian hukum dan administrasi, penggantian pemerintah dan sebagainya bukanlah dikategorikan kepada revolusi. Kedua, revolusi melibatakan massa rakyat yang besar jumlahnya yang dimobilisasi dan bertindak dalam suatu gerakan revolusioner. Dan revolusi dalam banyak kasus melibatkan pemberontakan petani dan pemberontakan urban. Dengan demikian, meski suatu gerakan dapat menimbulkan perubahan paling dalam dan fundamental tetapi jika dipaksa oleh penguasa dari atas, maka ia tidak termasuk pada kategori revolusi, juga tidak termasuk kedalam kategori revolusi bila terjadi perubahan fundamental yang ditimbulkan oleh kecenderungan sosial spontan.
Gagalnya Revolusi Sosial Di Indonesia
Kegagalan revolusi tahun 1998 bukanlah hal yang pertama kali terjadi di Indonesia, malah jauh sebelumnya misalnya pada tahun 1945, ketika kelompok pergerakan yang dikomandoi oleh Syahrir dalam merebut kekuasaan dari Jepang juga mengalami kegagalan, dan pada tahun 1926 gerakan revolusioner yang dimotori oleh PKI melawan Belanda juga mengalami kegagalan (Lihat Audrey, 2005, Kahin,1995 dan Reid, 1996).
Dalam membantu menelaah dan memahami mengapa revolusi di Indonesia sering mengalami kegagalan, agaknya tepat merujuk pada apa yang disinyalir oleh Theda Skockpol. Dalam bukunya Sosial Revolution in the Modern World, (1995:260), Theda Skockpol mengajukan pertanyaan menarik; "begitu banyak negara-negara miskin di Dunia Ketiga, namun revolusi-revolusi hanya terjadi di sebagian kecil negara, dan tidak benar-benar dibutuhkan di negara paling miskin. Mengapa revolusi sosial terjadi di Cina dan Vietnam, tetapi tidak terjadi di India dan Indonesia?" Skockpol menjawab sendiri pertanyaan itu dengan mengutip Leon Trotsky: "The mere existence of privation is not enough to cause an insurrection; if it were, the masses would be always in revolt!".
Indra J. Piliang
(dalam Manan, 2005:219) menjelaskan hambatan besar terjadi revolusi di Indonesia adalah; pertama, substansi teori atau bahkan ide revolusioner telah menjadi milik intelektual dan kelas menengah kota. Kedua, terputusnya rantai gagasan antara "juru bicara" revolusi sosial dengan massa di pedesaan. Ketiga, adanya dua elemen bangsa yang antipati kepada gagasan atau aksi revolusi, yaitu militer dan mayoritas penduduk beragama Islam.
Apa yang dikemukakan oleh Indra J Piliang di atas merupakan kenyataan historis yang terjadi di Indonesia. Dalam terminologi klasik misalnya ide atau terma revolusioner selalu dihubungkan dengan dan menjadi milik sah dari intelektual dan kelas menengah kota, mereka adalah bagian dari kelas borjuasi, bukan pemilik kekuasaan. Mayoritas kelas menengah Indonesia adalah kelas yang tidak memiliki basis yang cukup kuat, bahkan sebagian dari mereka malah hanya perpanjangan tangan dari kelompok elite dominan. Hal ini mengakibatkan gagasan revolusi tak punya pengaruh banyak.
Ketiadaan mediator yang akan mengkomunikasikan gagasan revolusi antara pemegang ide revolusioner dengan massa di pedesaan menjadi faktor yang menyebabkan gagalnya revolusi, sebab merujuk pada sejarah revolusi sosial Indonesia, barisan kaum tani miskin adalah penggerak utama revolusi sosial. Sebenarnya Indonesia cukup kaya dengan literatur revolusi petani, juga kalangan pedesaan (para menak dan jawara) juga pemuda dan ulama, dalam mendekonstuksi stratifikasi sosial. Studi yang dilakukan oleh Antony Reid, Anton Lucas, Sartono Kartodidjo, Benedict Anderson, Robert Brison Cribb, dan lain-lain misalnya, telah menunjukkan bagaimana revolusi sosial terjadi di tingkat lokal, baik desa maupun kota, namun hal ini, sekali lagi, tidak berlangsung secara nasional.
Sekalipun Skocpol percaya bahwa kekuatan-kekuatan revolusioner petani hanya bisa berhasil apabila dibantu oleh kelompok-kelompok profesional yang membangun organisasi revolusioner, tetapi tetap saja di Indonesia terhalang oleh tembok besar hyper-modernisme yang memperkokoh pilar individualisme. Modernisme telah melahirkan ambigu kebudayaan, ketika individualitas membelah masyarakat, bahkan melahirkan kultus individu. Dan disinilah kekuatan rasionalitas justru terkubur. Yang terjadi bukan lagi solidaritas sesama warga miskin, melainkan lebih banyak warga miskin yang menjadi pengikut fanatik pemimpin A, akan mudah untuk menyerang warga miskin pemimpin B misalnya. Oleh karena demikian "benturan sosial" yang sempat terjadi selama proses perubahan sosial/reformasi di Indonesia lebih pada rebutan antar pemimpin yang didukung massa rakyat tertentu, ketimbang melihatnya dari perspektif Marxis: perbenturan antar kelas. Elite yang terbelah, diikuti massa yang terbelah, akan menyulitkan masuknya pikiran-pikiran revolusi kelas/struktural
Antipatinya milter dan mayoritas orang Islam terhadap gagasan atau aksi revolusi, ikut menjadi faktor penghambat terjadinya revolusi di Indonesia. Sekalipun ulama Aceh pernah bergabung dengan kelompok pemuda sosialis dalam revolusi sosial tahun 1946, namun tetap saja kepentingan utamanya adalah menggeser peranan kelompok uleebalang. Oleh karena itu, dalam berbagai kasus revolusi sosial yang digerakkan oleh kelompok Marxis, kedua elemen itu nyaris bersatu. Memang, revolusi Islam Iran tahun 1979 menunjukkan betapa berbagai kalangan intelektual kota, mahasiswa, usahawan, pekerja, kaum miskin kota, dan para mullah bergabung menjadi kekuatan revolusioner, tetapi ciri kekuasaan yang ditumbangkan adalah rezim aristokrasi-diktatorial yang disokong oleh kapitalisme global Amerika.
Tentunya agak sulit menemukan kondisi pra-revolusi Iran di Indonesia, mengingat sejumlah daerah justru hidup dengan tradisi warisan aristokrasi etnik. Unsur etnik boleh jadi lebih menonjol, ketimbang unsur kesamaan agama. Seperti ditulis Skockpol (1995:262), bahwa revolusi lebih dari sekadar perjuangan ideologi, apakah di kalangan agamawan ataupun di kalangan kaum Marxis. Kaum Marxis lebih banyak berhasil dalam revolusi, ketika menggabungkan nasionalisme dan perjuangan kelas, seperti di Cuba, Nigaragua dan Vietnam. Dan sepertinya tradisi ahlul sunah wal jamaah yang lebih dominan di Indonesia relatif kering dari ide-ide revolusi. Selain hal di atas, alasan lain mengapa tidak terjadi revolusi sosial di Indonesia menurut Umaruddin Masdar (Kedaulatan Rakyat, 13/2/2004) adalah bahwa masyarakat Indonesia cenderung menolak perubahan yang bersifat revolusioner, mereka lebih memilih perubahan secara damai.
Potret Kesejahteraan di Indonesia
Selanjutnya kita akan melihat keterkaiatan antara revolusi sosial yang dikehendaki masyarakat dengan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang salah satunya merupakn faktor penunjang terciptanya revolusi sosial yang dikehendaki masyarakat itu
Belum lama ini, Media Indonesia menyajikan hasil survei Litbang Media Group, terhadap 480 responden yang diambil secara acak dari daftar pemilik telefon enam kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar) (Halida, 2008). Responden ditanya bagaimana pendapatannya sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah dirasakan semakin berat atau ringan? Mayoritas responden (73%) merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin berat; sebanyak 21% responden merasakan sama saja; dan hanya 6% yang merasakan semakin ringan. Ketika ditanyakan apakah sekarang ini mendapatkan pekerjaan baru dirasakan semakin sulit atau semakin mudah, sebagian besar responden (89%) merasakan sekarang makin sulit mencari pekerjaan baru; sebanyak 5% responden merasakan sama saja; 4% merasakan makin mudah; dan 2% tidak tahu.
Hasil survei ini tidak berbeda dengan laporan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk tahun 2007/2008 dari United Nations Development Programme (UNDP). Peringkat IPM Indonesia tahun 2007 berada di urutan 107 dari 177 negara. Selain semakin jauh tertinggal oleh Singapura (peringkat 25), Brunei Darussalam (30), Malaysia (63), Thailand (78), dan Filipina (90), peringkat Indonesia juga sudah terkejar oleh Vietnam (105) yang pada tahun 2006 berada di peringkat 109. Tanpa perbaikan strategi pembangunan ekonomi dan sosial secara mendasar, peringkat IPM Indonesia tidak menutup kemungkinan segera disusul oleh Laos (130), Kamboja (131) dan Myanmar (132) di tahun-tahun mendatang (Suharto, 2007; UNDP, 2007).
Capaian yang tergambar melalui IPM tersebut berkorelasi dengan dimensi kesejahteraan. Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan (capabilitas) manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat; indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak. Dengan demikian, rendahnya peringkat IPM Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah. Bahkan, karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep basic human capabilities, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih ketar-ketir. Dengan kata lain, alih-alih hidup berkecukupan, masyarakat Indonesia masih belum bisa terbebas dari lilitan kemiskinan.
Hingga saat ini, jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat mencemaskan (Suharto, 2007). Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin adalah 37,17 juta orang atau 16,58% dari total penduduk Indonesia. Satu tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 39,30 juta atau sebesar 17,75% dari total jumlah penduduk Indonesia tahun tersebut (TKPK, 2007). Ini berarti jumlah orang miskin turun sebesar 2,13 juta jiwa. Meskipun terjadi penurunan, secara absolut angka ini tetap saja besar dan melampaui keseluruhan jumlah penduduk Selandia Baru (4 juta), Australia (12 juta), dan Malaysia (25 juta). Angka kemiskinan ini menggunakan poverty line dari BPS sekitar Rp.5.500 per kapita per hari.3 Jika menggunakan poverty line dari Bank Dunia sebesar US$2 per kapita per hari, diperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia berkisar antara 50-60% dari total penduduk.
Meski terkadang tumpang tindih, potret kesejahteraan ini akan lebih buram lagi jika dimasukkan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang oleh Departemen Sosial diberi label Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di dalam kelompok ini berbaris jutaan gelandangan; pengemis; Wanita Tuna Susila; Orang Dengan Kecacatan; Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA); Komunitas Adat Terpencil (KAT); Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus atau Children in Need of Special Protection (CNSP) (anak jalanan, buruh anak, anak yang dilacurkan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang terlibat konflik bersenjata); jompo telantar dan seterusnya. Mereka seringkali bukan saja mengalami kesulitan secara ekonomi, melainkan pula mengalami social exlusion – pengucilan sosial akibat diskriminasi, stigma, dan eksploitasi.
Negara dan Kebijakan Sosial
Francis Fukuyama (2005) dalam bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, menunjukkan bahwa pengurangan peran negara dalam hal-hal yang memang merupakan fungsinya hanya akan menimbulkan problematika baru. Bukan hanya memperparah kemiskinan dan kesenjangan sosial, melainkan pula menyulut konflik sosial dan perang sipil yang meminta korban jutaan jiwa. Keruntuhan atau kelemahan negara telah menciptakan berbagai malapetaka kemanusiaan dan hak azasi manusia selama tahun 1990-an di Somalia, Haiti, Kamboja, Bosnia, Kosovo, dan Timor Timur (Fukuyama, 2005; lihat Suharto, 2007).
Selain memperlihatkan kejujuran ilmiah Fukuyama, buku State-Building sekaligus menjelaskan bahwa dia telah “insyaf” dari “kekeliruan” pemikiran sebelumnya. Dalam bukunya yang terdahulu, The End of History and The Last Men (1992), Fukuyama dengan yakin menyatakan bahwa sejarah peradaban manusia (seakan) telah berakhir. Pertarungan antara komunisme dan kapitalisme juga telah usai dengan kemenangan kapitalisme (neoliberalisme). Mengapa kapitalisme menang. Jawabanya adalah karena sistem ini dianggap paling cocok untuk manusia abad ini. Dan kita tahu semua, kapitalisme sangat menganjurkan peran negara yang sangat minimal dalam pembangunan ekonomi, apalagi pembangunan sosial.
Sekarang, dalam bukunya State-Building dengan lantang Fukuyama berkata bahwa “negara harus diperkuat!”. Kesejahteraan, kata Fukuyama, tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang kuat; yang mampu menjalankan perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan warganya.
Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat significant dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi paling absah yang memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat, dan karenanya paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Globalisasi dan kegagalan pasar sering dicatat sebagai faktor penyebab mencuatnya persaingan yang tidak sehat, monopoli dan oligopoli, kesenjangan ekonomi di tingkat global dan nasional, kemiskinan dan keterbelakangan di negara berkembang, serta ketidakmampuan dan keengganan perusahaan swasta mencukupi kebutuhan publik, seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Mishra (2000) dalam bukunya Globalization and Welfare State menyatakan bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menjual kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa Timur agar memperkecil pengeluaran pemerintah, memberikan pelayanan sosial yang selektif dan terbatas, serta menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta.
Benar, negara bukan lah satu-satunya aktor yang dapat menyelenggarakan pelayanan sosial. Masyarakat, dunia usaha, dan bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Namun, sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial dan public goods, pelayanan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada masyarakat dan pihak swasta. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (obligation) dalam memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan menghargai (to respect) hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat daripada masyarakat atau dunia usaha. Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat “wajib”. Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat “tanggungjawab” (responsibility).
Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan sosial yang berkeadilan, peran negara dan masyarakat tidak dalam posisi yang paradoksal. Melainkan, dua posisi yang bersinergi. Bahkan di Indonesia, komitmen dan peran negara dalam pelayanan sosial seharusnya diperkuat dan bukannya diperlemah, seperti diusulkan kaum neoliberalisme pemuja pasar bebas. Pada era desentralisasi sekarang ini, penguatan negara mencakup juga pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan memiliki agenda kebijakan sosial yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Pemberian wewenang yang lebih luas kepada Pemda tidak hanya dimaknakan sekadar peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara ekonomi, tanpa kepedulian terhadap penanganan “PAD” (Permasalahan Asli Daerah) secara sosial.
Menggugat kapitalisme
Setelah kapitalisme memonopoli hampir seluruh sistem ekonomi, kini semakin banyak pengamat yang menggugat apakah sistem yang didasari persaingan pasar bebas ini mampu menjawab berbagai permasalahan nasional maupun global. Masalah seperti perusakan lingkungan, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan sosial, meroketnya pengangguran, dan merebaknya pelanggaran HAM serta berbagai masalah degradasi moral lainnya ditengarai sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari beroperasinya sistem ekonomi kapitalistis.
Sinyalemen tersebut bukan tanpa bukti. Berdasarkan studinya di negara-negara berkembang, Haque dalam Restructuring Development Theories and Policies (1999) menunjukkan bahwa kapitalisme bukan saja telah gagal mengatasi krisis pembangunan, melainkan justeru lebih memperburuk kondisi sosial-ekonomi di Dunia Ketiga. Menurutnya, compared to the socioeconomic situation under the statist governmentts during the 1960s and 1970s, under the pro-market regimes of the 1980s and 1990s, the condition of poverty has worsened in many African and Latin American countries in terms of an increase in the number of people in poverty, and a decline in economic-growth rate, per capita income, and living standards (Haque, 1999:xi).
Menurut Rudolf Hickel, setelah kapitalisme mengalahkan semua lawannya, ia akan cenderung menjadi lupa diri karena tiadanya "tangan pengatur keadilan". Pemikir sosialis Jerman Robert Heilbroner kemudian mengajukan strategi bahwa perlawanan terhadap kapitalisme di masa depan seharusnya tidak diarahkan untuk membongkar total sistem ini, melainkan lebih diarahkan agar sistem yang "unggul" ini lebih berwajah manusiawi (compassionate capitalism). Contoh paling mirip dengan gagasan Heilbroner ini adalah diterapkannya sistem negara kesejahteraan (welfare state) khususnya di negara-negara Barat yang dikenal selama ini pendukung loyal kapitalisme. Di Eropa dan AS negara kesejahteraan diwujudkan dalam bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, penganggur agar terhindar dari gilasan mesin kapitalisme.
Bapak-bapak pemikir besar dunia tentang konsep terjadinya sebuah negara: Thomas Hobbes, John Locke, Rosseau, ataupun Montesqieu bersependapat bahwa negara terlahir dari adanya sebuah ‘ikatan’. Ikatan yang dalam istilah Thomas Hobbes ataupun Locke dikatakan sebagai “Perjanjian masyarakat atau social contract”.
Konvensi Montevideo tahun 1933, lebih mengkonkretkan arti dari sebuah negara yang telah menjadi wacana pada tahun-tahun sebelumnya. Dimana perlunya pemenuhan syarat-syarat adanya sebuah negara, yaitu: (a) mempunyai penduduk yang tetap; (b) mempunyai wilayah tertentu; (c) adanya kekuasaan yang berdaulat.
Di lain pihak dalam perjalanannya, negara akan berinteraksi dengan negara-negara lain, seperti kita ketahui bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang paling kuat, hal tersebut terjadi karena adanya : “kedaulatan” atau sovereignty. Menurut Max Huber, kedaulatan teritorial digambarkan sebagai berikut: “Kedaulatan dalam hubungan antara negara-negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan berkenaan dengan suatu bagian dari muka bumi ini adalah hak untuk melaksanakan didalamnya, tanpa campur tangan negara lain, fungsi-fungsi suatu negara.”
Begitu pula seperti apa yang terjadi dengan Negara kita, Indonesia. Dimana telah terjadi sebuah ‘kontrak sosial’ pada aras nasional pada 19 Agustus 1945, saat pembacaan proklamasi kemerdekaan diucapkan oleh Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menggungkapkan banyak hal mengenai hal tersebut diatas, terutama pada bagian Pembukaan (preambule).
Kesadaran akan pembentukan sebuah negara didasarkan kepada hak setiap bangsa serta berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan suatu pemerintahan Negara Indonesia yang berbentuk republik, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat serta menjunjung tinggi hukum?
Revolusi Melalui Kertas Suara?
Banyak ketakutan yang bermunculan sehubungan dengan pemilu legislatif beberapa saat yang lalu dan salah satunya adalah ketakutan akan tidak terselenggaranya pemilu, termasuk pemilu Presiden dan wakil presiden mendatang sebagai akibat satu atau beberapa hal, akankah Negara Indonesia ini dapat dipertahankan? Atau dalam arti lain kita akan bubar sebagai negara kesatuan dan kemudian menentukan arahnya sendiri-sendiri.
Mengingat bahwa Pemilihan Umum adalah instrumen politik yang sangat stategis untuk menegakkan demokrasi pada setiap negara dan bukan saja sebuah acara seremonial belaka untuk memilih para wakil, tapi juga merupakan manifestasi dan memainkan peranan yang sangat signifikan bagi kehidupan politik masyarakat dan penegakan hak asasi manusia.
Dimana tujuan dari pemilu adalah sebagai berikut: (a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif dari kebijakan umum; (b) Sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi rakyat tetap terjamin; (c) Sebagai sarana memobilisasi dan atau mengalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.
Masih ingatkah kita semua ketika Negara Indonesia ini belum ada (sebelum 1945)? Benih-benih kesadaran akan arti berbangsa dan bernegara sangat dipegang dengan baik, peristiwa 28 Oktober 1928, mungkin menyegarkan bayangan kita semua bahwa sebelum Negara Indonesia lahir sebenarnya kita telah hidup dalam kesadaran akan bernegara.
Kesadaran-kesadaran yang mulai tumbuh juga seiring dengan tumbuhnya lembaga/institusi dimana lembaga tersebut berfungsi sebagai wadah dalam memayungi gerakan tersebut, ambil contoh, seperti yang telah diuraikan di atas semisal pergerakan Budi Utomo. Ada lagi Sarekat Islam, Indies Partai, Taman Siswa, Pasantren-pesantren di daerah-daerah (mungkin lebih spesifik kepada Nadhatul Ulama dan Muhammadyah), ataupun yang lainnya.
Mereka menenpatkan posisi mereka sebagai pilar-pilar dalam upaya pencapaian akan arti pentingnya kebangsaan dan kenegaraan, hal tersebut dapat berlangsung dengan baik karena mereka lebih dekat/menyentuh dengan masyarakat tanpa ada birokrasi yang harus dilalui. Namun sangat sayang, kondisi yang kondusif bagi lembaga/institusi tersebut diatas tidak berlangsung lama. Hal tersebut menurut Nick , dikarenakan oleh (1) krisis politik; (2) kebangkrutan ekonomi; (3) berubahnya haluan mereka kepada politik aliran dan pertarungan berbagai ideologi; serta diperparah dengan (4) Penguatan akan posisi negara yang terus melakukan intervensinya yang sangat mendalam.
Negara terlihat mempunyai rasa resistensi/mereduksi terhadap gerakan-gerakan tersebut, yang menurut penulis disalah artikan negara sebagai upaya untuk menyaingi posisi negara itu sendiri, sehingga tidak diperlukan lagi gerakan-gerakan seperti itu.
Sejatinya, negara harus memelihara keberadaan dari institusi/lembaga-lembaga tersebut, mengapa? Karena dengan terwujudnya keberagaman, kemandirian, dan kapasitas politik di dalam gerakan-gerakan (dapat muncul dalam sosok, misalnya, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi non-Pemerintah, organisasi sosial/keagamaaan, paguyuban-paguyuban, serta kelompok-kelompok kepentigan lainnya) tersebut, maka warga negara akan mampu mengimbangi serta mengontrol kekuatan negara.
Negara Kesejahteraan
Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam Suharto (2008), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father of welfare states).
Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris, dalam laporannya mengenai Social Insurance and Allied Services, yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge menyebut want, squalor, ignorance, disease dan idleness sebagai ‘the five giant evils’ yang harus diperangi (Spicker, 1995; Bessant, et al, 2006). Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandangnya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (from cradle to grave). Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negaranegara lain di Eropa dan bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negara-negara tersebut. Sayangnya, sistem ini memiliki kekurangan. Karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, ia tidak dapat mencakup resiko-resiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi).
Pengertian negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya (lihat Suharto,2008). Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (market failure) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (state failure) pada masyarakat sosialis (lihat Husodo, 2006).
Menurt Suharto (2007), sedikitnya ada empat model negara kesejahteraan yang hingga kini masih beroperasi
Model Universal. Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai the Scandinavian Welfare States yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Sebagai contoh, Negara kesejahteraan di Swedia sering dijadikan rujukan sebagai model ideal yang memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya. Negara kesejahteraan di Swedia sering dipandang sebagai model yang paling berkembang dan lebih maju daripada model di Inggris, AS dan Australia.
Model Korporasi atau Work Merit Welfare States. Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai Model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck dari Jerman.
Model Residual. Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Ada tiga elemen yang menandai model ini di Inggris: (a) jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum; (b) perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan (c) pemberian pelayanan sebaik mungkin. Model ini mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Namun, seperti yang dipraktekkan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek daripada model universal. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial juga diberikan secara ketat, temporer dan efisien.
Model Minimal. Model ini umumnya diterapkan di gugus negara-negara latin (seperti Spanyol, Italia, Chile, Brazil) dan Asia (antara lain Korea Selatan, Filipina, Srilanka). Model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Di lihat dari landasan konstitusional seperti UUD 1945, UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut negara kesejahteraan model ini.
Pertemuan Negara dan Pemerintah
Perkembangan lebih lanjut mengenai pemaknaan atas negara menjadi pembicaraan lebih mendalam dari Hagel, Karl Marx, Gramsci, Woodrow Wilson, Hans Kelsen, ataupun pemikir-pemikir lainnya. Menurut Hagel sendiri, negara merupakan semacam roh kemuliaan yang besar yang akan membawa manusia ke arah kemakmuran. Hal tersebut dapat diartikan bahwa manusia baik secara individu maupun berkelompok harus tunduk kepada negara yang merupakan representasi dari roh kemuliaan besar tersebut agar tercipta apa yang diiginkan, yaitu kemakmuran. Hal tersebut dapat kita lihat menjadi dasar utama bagi kaum Hegelian (pengikut ajaran Hagel) dalam penekanan mereka tentang arti pentingnya sebuah negara.
Kritik keras akan keberadaan negara sekaligus mengkontra apa yang menjadi pemikiran Hegel dilontarkan oleh Karl Marx. Dimana Marx mengungkapkan bahwa masyarakat tidak perlu tunduk kepada negara, karena negara tidak berposisi diatas masyarakat tapi lebih kepada alat belaka yang digunakan oleh penguasa untuk menindas yang dikuasainya .
Dalam perkembangan kemudian perihal Negara dan Pemerintah diatas menurut penulis akhirnya menjadi lebih mengerucut pada satu konsep pemikiran dari Hans Kelsen mengenai Negara Kesejahteraan. Yang dimaksud dengan negara kesejahteraan menurut ide dari Hans Kelsen adalah negara yang banyak mencampuri dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat (negara administrative).
Lebih lanjut dipaparkan bahwa tindakan administrative tersebut harus dilakukan dengan sebuah hukum, atau dalam istilah kerennya konstitusi, dimana dalam memuat segala tetek bengek masalah ketatanegaraan (fungsi, wewenang, tanggungjawab,…) serta mengatur juga perihal negara dan warga negaranya. Yang dalam bahasa penulis dapat dikatakan sebagai aturan main baku/birokrasi, yang menjadi batasan-batasan bagi keduanya, baik bagi negara dan pemerintah juga warga negaranya.
Namun pada kondisi seperti inilah, dimana mayarakat memberikan kewenangan/kekuasaan kepada pemerintah (yang merupakan pengejawantahan dari negara), tercipta suatu ketakutan yang disampaikan oleh Marx. Dalam hal tersebut, hukum (konstitusi) dapat berubah menjadi alat kekuasaan politik dalam upaya mengontrol masyarakat yang kemudian akan berpotensi disalah artiakan oleh pemerintah sebagai bentuk klaim atas pembenaran terhadap semua tindakannya .
Ketakutan Marx yang menurut penulis sangat beralasan dan masuk akal, karena kekuasaan yang diberikan masyarakat kepada negara dalam rangka mengatur masyarakat tersebut kerap kali tidak mampu memenuhi keinginan masyarakat sebagai akibat dari peyelewengan kekuasaan oleh negara. Namun mampukah masyarakat yang notabene sebagai pemberi kekuasaan kepada negara tersebut mencabut kembali mandatnya? Menurut teori yang dikemukakan oleh John Locke mengenai pertanyaan tersebut dia berpendapat bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menumbangkan negara jika negara tidak mampu lagi menyelenggarakan kekuasaan tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dapat dilayangkan sehubungan dengan pernyataan dari John Locke tersebut, seperti: (1) Apa yang akan terjadi terhadap negara jika masyarakat bersepakat untuk mencabut kekuasaan negara? (2) Bisakah masyarakat hidup tanpa adanya negara? Ataupun (3) Adakah bentuk/varian lain yang mampu mengimbangi peran dari sebuah negara? Serta kita dapat mengumpulkan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
Islam dan Negara Kesejahteraan
Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa :
”Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan. zakat, orang-orang yang menpati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.” QS, Al-Baqarah: 177
Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah di atas, sejatinya memiliki nilai mengenai pentingnya kesejahteraan masyarakat ketimbang sekadar menghadapkan wajah kita ke barat atau timur dalam shalat. Tanpa memarginalkan pentingnya shalat, Al-Qur’an mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberi pesan tentang keimanan, Al-Qur’an mengingatkan penganutnya bahwa pernyataan keimanan kepada Allah, KitabNya, dan Hari Kiamat saja tidaklah cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan.
Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada di atas keuntungan segelintir atau sekelompok orang. Sistem ekonomi Islam, misalnya, memiliki dua tujuan: memerangi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib. Diantaranya melalui :
1. Zakat
Zakat adalah sumber dana pembangunan dalam Islam dan memiliki kedudukan istimewa. Bukan saja diwajibkan, melainkan merupakan salah satu Rukun Islam. Zakat adalah instrumen penting kesejahteraan dalam Islam. Diwajibkannya zakat mencerminkan kebijakan (sosial) negara. Sebagai kebijakan negara, alokasi pajak harus mengacu pada hajat hidup orang banyak. Negara harus adil, tegas dan transparan dalam mengelola Zakat. Peruntukan zakat sejatinya untuk rakyat banyak, terutama yang lemah dan mengalami kesulitan.
Negara harus berpihak pada kelompok ini, bukan pada segelintir kelompok kuat. Kaum elit biasanya jumlahnya sedikit, namun kuat dan kaya. Negara tidak perlu berpihak kepada mereka, karena mereka mampu mengurus dirinya sendiri.Istilah zakat memiliki kesamaan dengan sedekah yang oleh sebagian ulama didefinisikan sebagai ”pajak negara terhadap muslim”, karena mencakup ”kontribusi” yang harus dibayar oleh muslim kepada pemerintah terkait dengan usaha pertanian, peternakan, pertambangan, perdagangan, industri, tabungan, dan profesi (lihat Ali, 2007).
2. Jaminan sosial
Sementara negara-negara Eropa belum memiliki asuransi pengangguran (unemployment insurance) hingga akhir Abad ke-19, Dunia Islam telah memilikinya sejak awal. Ketika seseorang terluka atau kehilangan kemampuannya untuk bekerja, mereka kemudian menjadi tanggungan negara untuk memastikan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dia dan keluarganya memperoleh tunjangan dari dana publik (Hamid, 2008).
Hanya resiko-resiko yang berat saja yang menjadi objek asuransi dan inipun berbeda sesuai dengan waktu dan kondisi sosial. Semasa Islam mulai masuk di masyarakat Arab, penyakit-penyakit keseharian belum dikenal dan biaya perawatan medis hampir tidak pernah menjadi persoalan. Kebanyakan keluarga membangun rumahnya tanpa bantuan orang lain dan tidak memerlukan biaya bahkan untuk sebagian besar bahan bangunan. Karenanya, mudah dimengerti mengapa saat itu belum ada kebutuhan akan asuransi kesehatan, kebakaran dst.
Sementara itu, asuransi untuk penawanan dan pembunuhan merupakan kebutuhan bahkan semenjak pemerintahan Rasulullah SAW. Berbagai skema jaminan sosial juga sudah mulai dibuat, meskipun masih bersifat fleksibel dan terbuka bagi perkembangan dan penyesuaian. Dalam konstitusi Kota Madinah pada tahun awal hijrah, asuransi seperti ini dinamakan ma’aqil mekanismenya adalah : jika seseorang menjadi tawanan perang, tebusan diperlukan untuk memperoleh kebebasannya. Serupa dengan itu, semua bentuk penyiksaan badan atau pembunuhan harus ditebus dengan pembayaran kerusakan/kerugian atau uang darah (Ali, 2008).
Nabi sendiri mengorganisasi asuransi ini berdasarkan prinsip saling tolong-menolong.Para anggota suku dapat menunjuk kepala bendahara dari sukunya sendiri dan setiap orang harus memberikan kontribusi sesuai kemampuannya. Jika bendahara dari suatu suku dianggap kurang cakap, suku-suku yang bersaudara atau berdekatan memiliki kewajiban memberi bantuan. Hirarki juga disusun untuk mengatur unit-unit sehingga berjalan secara sinergis.
Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khatab, mutualitas dan unit-unit asuransi diatur berdasarkan profesi, administrasi sipil atau militer, serta wilayah. Pemerintah pusat atau provinsi memberi bantuan dan dukungan dana terhadap unit-unit tersebut berdasarkan peraturan anggaran belanja negara yang telah ditetapkan. Asuransi pada masa itu sudah mencerminkan prinsip gotong-royong dalam meringankan resiko-resiko yang dihadapi anggota masyarakat seperti prinsip asuransi modern saat ini. Tetapi, berbeda dengan perusahaan asuransi kapitalistik, asuransi Islam mengatur mekanismenya berdasarkan prinsip kebersamaan dan kerja sama yang saling menguntungkan yang ditopang oleh gradasi piramida unit-unit asuransi yang kemudian memuncak di pemerintahan pusat.
Pada masa Pemerintahan Umar, lembaga sosial berhasil membentuk skema asuransi pensiun (Ali, 2008). Asuransi ini mencakup semua penduduk termasuk non-muslim. Semenjak seorang bayi dilahirkan, dia sudah memiliki hak untuk memperoleh asuransi pensiun. Orang dewasa memperoleh tunjangan minimum yang cukup untuk hidup. Selain asuransi, jaminan sosial juga dapat berbentuk bantuan sosial, terutama bagi mereka yang dikategorikan miskin dan cacat yang tidak potensial.
Khalifah Umar melakukan ini dengan menentukan standar hidup minimum yang kelak menjadi rujukan dalam membuat garis kemiskinan (poverty line). Saat itu, selain menerima tunjangan uang, orang miskin menerima sekitar 50 kg terigu setiap bulannya. Untuk menghindari ketergantungan, mengemis dan bermalas-malasan tidak diberi toleransi. Mereka yang menerima bantuan sosial pemerintah diupayakan untuk dapat memberi kontribusi kepada masyarakat.
Daftar Pustaka
Ali, Syed Mumtaz (2008), Social Welfare: A Basic Islamic Value, http://muslimcanada.org/welfare.htm (diakses 10 Januari 2008)
Hamid, Shahid (2008), An Islamic Alternative? Equality, Redistributive Justice, and The Welfare State in the Caliphate of Umar (Rta), www.renaissance.com.pk/ (diakses12 Januari 2008)
Harris, John (1999), “State Social Work and Social Citizenship in Britain: From Clientelism to Consumerism” dalam The British Journal of Social Work, Vol.29,No.6, halaman 915-937
Husodo, Siswono Yudo (2006), “Membangun Negara Kesejahteraan”, makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
Spicker, Paul (1995), Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice Hall
------------------(2002), Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths, London: Catalyst
Sudewo, Erie (2008), Politik Ziswaf: Kumpulan Essay, Jakarta: Circle of Information and Development
Suharto, Edi (2007), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia, Bandung: Alfabeta
----------------(2006), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (cetakan ketiga), Bandung: Alfabeta
-----------------, (2008), Islam dan Negara Kesejahteraan, Makalah yang disampaikan pada Pengkaderan Darul Arqam (DAP), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Jakarta 8 Januari 2008
Anthony.J.S. Reid, 1996, “Revolusi Nasional Indonesia”, Pustaka Sinar Harapan, Indonesia.
Audrey Kahin, 2005, “Dari Pemberontakan Ke Integrasi; Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998”, Yayasan Obor Indoensia Jakarta.
C. Wright Mills, 2003, “Kaum Marxis; Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Douglas Kellner, 2003, “Teori Sosial Radikal”, Syarikat Indonesia, Yogyakarta.
Francois Furet & Denis Richet, 1989, “Revolusi Prancis” Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
George Mc Turnan Kahin, 1995, “Nasionalisme dan Revolusi Di Indonesia”, Sebelas Maret University Press & Pustaka Sinar Harapan, Jakrata.
Munafrizal Manan, 2005, “Gerakan Rakyat Melawan Elit”, Resist Book, Yogyakarta.
Piotr Sztompka, 2005, “Sosiologi Perubahan Sosial”, Prenada Media, Jakarta.
Roger Eatwell & Anthony Wright (ed) 2001, “Contemporary Political Ideologies”, Continuum, London dan New York.
Ted Grant dan Alan Woods, 1998. “Indonesia: Revolusi Asia Telah Dimulai” Indomarxis.Net.
Theda Skockpol, 1995 “Social Revolution in the Modern World”, New York; Cambridge University Press
Tabloid Pembebasan, 2004, “Sneevliet: Dari Belanda Menebar Benih Radikalisme di Indonesia”, Indomarxist.Net.
Umaruddin Masdar, “Pemilu 2004 dan Revolusi Sosial”, Kedaulatan Rakyat, 13 Februari 2004
Lihat Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
Wiiliam F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff: Sociology, edisi ke-4, A. Feffer dan Simons International University Edition, 1964, bagian 7.
H. Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, Rineka Cipta, Semarang, 1997
Revolusi dikutip dari Nurus Shalihin Djamra dalam jurnal Ijtihad, Vol. XI, No.1, 2007
Potret Kesejahteraan di Indonesia dan Negara dan Kebijakan Sosial dikutip dari artikel Islam dan Negara Kesejahteraan. Edi Suharto Disampaikan pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008, Jakarta 18 Januari 2008.
Menggugat Kapitalisme dikutip dari Edi Suharto Tuesday, 22 January 2008
http://www.pmb.or.id